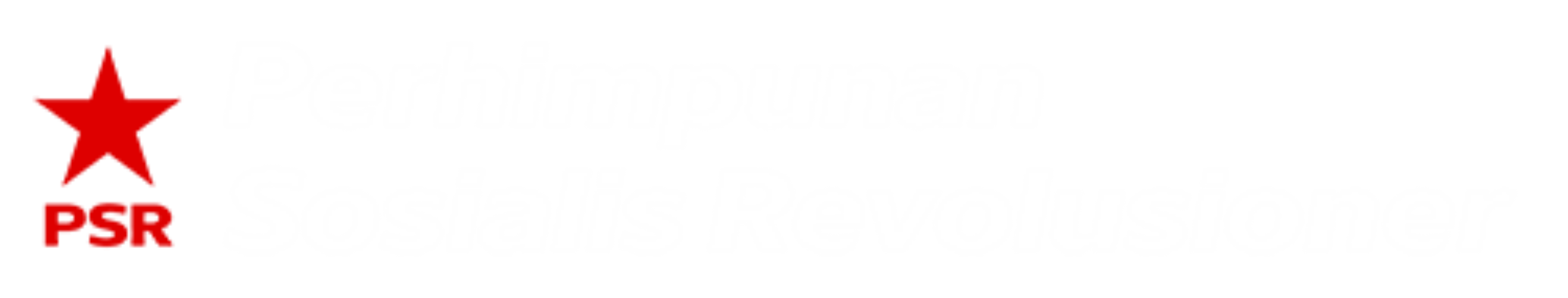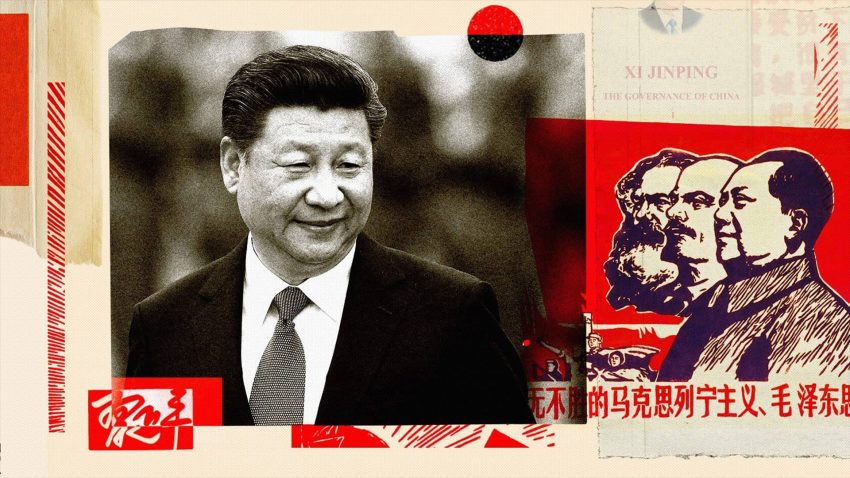Dalam sepuluh tahun terakhir, China telah menjadi pesaing utama kapitalisme Barat di pasar global. Pengaruhnya semakin meluas ke berbagai wilayah yang sebelumnya dikuasai Amerika Serikat, sehingga memicu persaingan yang semakin sengit. Artikel ini menganalisis perkembangan ekonomi dan politik China sejak 2016, yang ditulis oleh Fred Weston sebagai pengantar edisi terjemahan bahasa Mandarin buku China: From Permanent Revolution to Counter-Revolution.
Saat ini, semakin jelas bahwa pertumbuhan China sebagai negara kapitalis dan imperialis mulai menghadapi batasannya. Ini mempersiapkan konfrontasi besar, baik di dalam negeri—dalam bentuk perjuangan kelas—maupun di tingkat internasional, dengan menajamnya ketegangan inter-imperialis.
—
Buku ini (China: From Permanent Revolution to Counter-Revolution) pertama kali diterbitkan pada Februari 2016 dan membahas sejarah China dari sudut pandang Marxis, yang kini telah menjadi salah satu negara paling penting dalam revolusi dunia. Buku ini mencakup periode yang panjang, mulai dari runtuhnya Dinasti Qing di awal abad ke-20 hingga masa jabatan pertama Xi Jinping.
Dalam buku ini, dijelaskan bagaimana China berhasil keluar dari keterbelakangan, pertuantanahan, dan dominasi imperialis melalui Revolusi China 1949. Perubahan besar ini bukan dipimpin oleh kaum borjuis nasional, melainkan melalui proses panjang yang penuh kontradiksi, yang dipimpin oleh Partai Komunis yang mengekspropriasi kapitalisme dan mendirikan sistem ekonomi nasional yang terencana. Lewat proses inilah lahir Republik Rakyat China.
Revolusi China membuktikan kebenaran teori Marxis, terutama gagasan Leon Trotsky tentang Revolusi Permanen, walaupun secara terdistorsi. Teori Revolusi Permanen menyatakan rakyat bangsa-bangsa terjajah tidak bisa menyelesaikan problem-problem mereka dengan tetap berada dalam sistem kapitalisme. Revolusi China membebaskan jutaan pekerja dari eksploitasi dan penindasan pertuantanahan, kapitalisme, dan imperialisme dalam skala historis. Karena itu, kaum Marxis menganggap revolusi ini sebagai peristiwa paling bersejarah setelah Revolusi Rusia 1917.
Namun, kaum Marxis juga memahami bahwa negara yang terbentuk setelah revolusi ini tidak mengikuti model demokrasi buruh yang sempat berkembang di periode awal Uni Soviet di bawah kepemimpinan Lenin dan Trotsky. Sebaliknya, sistemnya lebih mirip dengan rejim birokratik di bawah Joseph Stalin, di mana kekuasaan politik kelas pekerja dirampas oleh birokrat negara.
Buku ini menjelaskan meskipun Mao Zedong dan para pemimpin revolusi awalnya ingin membentuk pemerintahan koalisi dengan elemen-elemen borjuasi nasional yang mereka anggap “patriotik dan progresif”, situasi yang berkembang dengan cepat memaksa mereka untuk menyingkirkan kapitalisme dan menerapkan ekonomi terencana agar revolusi bisa bertahan. Ini merupakan bukti konkret bahwa Revolusi China tidak bisa berhenti pada ‘tahap’ demokrasi borjuis. Jika mereka tidak mengambil langkah mengekspropriasi kapitalisme, kemungkinan besar China akan mundur menjadi rejim kapitalis yang otoriter, dan bukannya negara demokrasi borjuis.
Namun, dalam perkembangannya, karena berbagai alasan yang telah dijelaskan dalam buku ini, Republik Rakyat China akhirnya mengikuti model Uni Soviet di bawah kepemimpinan Stalin, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Meski begitu, pencapaian sistem ekonomi terencana yang dinasionalisasi, yang merupakan tugas fundamental dalam transisi menuju sosialisme, dengan sendirinya membuktikan kebenaran teori Revolusi Permanen yang dikemukakan oleh Trotsky.
Ekonomi terencana membebaskan jutaan rakyat dari sistem pertuantanahan yang menindas selama berabad-abad. Sistem ini mendorong industrialisasi besar-besaran dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya, serta mengurangi pengangguran, buta huruf, dan keterbelakangan. Dengan ekonomi terencana, China berhasil membebaskan dirinya dari kungkungan yang mencegahnya memasuki era modern. China bebas dari dominasi imperialis dan penghinaan yang dialaminya selama puluhan tahun, yang memungkinkannya untuk merealisasikan potensi besarnya, dan akhirnya bisa bangkit dan menjadi kekuatan penting di panggung dunia.
Pencapaian Revolusi China 1949 pada gilirannya menjadi stimulus besar bagi gelombang revolusi di seluruh dunia setelah Perang Dunia II. Keberhasilannya menginspirasi banyak orang yang hidup di bawah imperialisme untuk berjuang membebaskan bangsa mereka dari kapitalisme.
Namun, kepemimpinan Mao Zedong dan Partai Komunis China memiliki dua kelemahan utama yang diwarisinya dari Uni Soviet di bawah Stalin. Pertama, mereka menganut gagasan “sosialisme di satu negara,” yang berarti dalam praktik mereka mengabaikan tugas untuk secara aktif mempersiapkan sebuah partai dunia untuk revolusi sosialis – yaitu komunis internasional yang sejati – untuk menyebarkan revolusi ke negara-negara kapitalis maju, untuk mengakhiri kapitalisme secara global. Kedua, tidak adanya demokrasi buruh, yang mengalir dari bangkitnya birokrasi yang berdiri di atas kelas buruh, sehingga negara ada di bawah kendali satu partai tunggal.
Dalam bukunya The Revolution Betrayed (1936), Trotsky menjelaskan, walaupun transformasi sosialis bisa dimulai di satu negara, ini tidak akan bisa bertahan lama jika kapitalisme masih mendominasi dunia. Jika kepemimpinan politik negara buruh hanya membatasi revolusi di dalam perbatasan nasionalnya sendiri, maka revolusi akan terus berada di bawah tekanan kontra-revolusioner dari kapitalisme. Selain itu, jika pekerja tidak diberi kebebasan untuk mengelola masyarakat secara demokratis, maka inefisiensi, korupsi, dan cacat-cacat subjektif dari segelintir birokrat pada titik tertentu akan menjadi penghambat absolut bagi perkembangan ekonomi terencana, dan melemahkan dan menghancurkan revolusi.
Trotsky juga memprediksi tiga kemungkinan masa depan Uni Soviet. Pertama, kaum buruh bangkit meluncurkan revolusi politik untuk menggulingkan kediktatoran birokratik, sehingga mengakhiri kontradiksi perencanaan ekonomi yang nasionalis dan birokratik itu, dan menghidupkan kembali perekonomian yang terencana secara demokratik dan revolusi dunia. Kedua, jika revolusi politik ini tidak terjadi, maka negara – yang berada di bawah tekanan birokrasi – bisa digulingkan oleh kontra-revolusi, yang membuka jalan bagi kapitalisme untuk kembali berkuasa. Ketiga, selapisan birokrat akan memilih untuk merestorasi kapitalisme sebagai solusi untuk mengatasi kontradiksi ekonomi terencana yang birokratik, sementara menjaga kepentingan dan privilese mereka sendiri.
Puluhan tahun kemudian, apa yang diprediksi Trotsky terbukti benar. Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur mengalami kemunduran ekonomi yang parah sebelum akhirnya runtuh satu per satu. Hingga kini, massa di sana masih merasakan dampak buruk dari restorasi kapitalisme.
China juga mengalami problem serupa dalam sistem ekonominya yang dikendalikan oleh birokrasi. Di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, Partai Komunis China mulai menerapkan kebijakan “Reformasi dan Keterbukaan.” Kebijakan ini perlahan-lahan menghapus sistem ekonomi terencana yang sebelumnya membawa banyak kemajuan, sementara PKC tetap memegang kendali penuh atas aparatus negara.
Meskipun negara-partai masih mengendalikan banyak perusahaan dan bank milik negara, ekonomi China tidak lagi berdasarkan ekonomi terencana, tetapi diatur oleh prinsip kapitalisme: pasar yang anarkis, bisnis berorientasi profit, dan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi.
Buku ini menjelaskan proses restorasi kapitalisme secara rinci, termasuk peristiwa-peristiwa penting di era Mao Zedong, seperti Perang Korea, Lompatan Jauh ke Depan, Perpecahan Sino-Soviet, dan Revolusi Kebudayaan. Juga dibahas bagaimana kebijakan Deng Xiaoping, yang awalnya bertujuan memperbaiki kontradiksi internal di era Mao, justru membawa China kembali ke sistem kapitalis. Banyak orang berpikir bahwa kapitalisme hanya bisa kembali jika ada kontra-revolusi besar atau penggulingan pemerintah. Namun, di China, restorasi kapitalisme terjadi perlahan-lahan, dalam beberapa tahap, dan tetap berada di bawah kendali birokrasi. Fakta ini sering membuat kaum kiri limpung. Inilah kenyataan yang terjadi, dan Marxisme mengajarkan kita untuk memahami sejarah berdasarkan proses riil yang hidup, bukan dengan memaksakan pada realitas skema kita sendiri mengenai apa yang seharusnya terjadi.
Buku ini melacak bagaimana kapitalisme berkembang di China hingga hampir akhir masa jabatan pertama Xi Jinping, yang mulai memimpin pada 2012. Rejim PKC saat ini sering mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi pesat setelah restorasi kapitalisme (yang mereka sebut sebagai “ekonomi pasar sosialis” atau “sosialisme dengan karakteristik China) adalah bukti keberhasilan mereka.
Namun, kebenaran itu konkret. Buku ini menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi China terutama terjadi karena integrasinya ke dalam ekonomi kapitalisme global. Ini memberikan medan investasi yang baru dan menguntungkan bagi kapitalis Barat, yang saat itu sedang mencari tempat baru untuk menanamkan modal mereka. Dengan begitu, kapitalisme sebagai sistem dunia bisa bertahan lebih lama.
Buku ini juga menunjukkan, meskipun ekonomi China berkembang pesat, berbagai kontradiksi kapitalis terus tumbuh di bawah permukaan: ketimpangan sosial, pengangguran, pemberangusan hak-hak buruh, dan terutama overproduksi. Ini pada gilirannya mendorong perjuangan kelas di bawah rejim kapitalis satu-partai yang totaliter.
Sejak buku ini diterbitkan delapan tahun lalu, sudah ada sejumlah perubahan kualitatif dalam perkembangan China yang perlu kita kaji, dan yang sangat menentukan bagi perspektif revolusi dunia hari ini. Beberapa proses ini sebenarnya sudah mulai terlihat saat buku ini pertama kali ditulis, tetapi sekarang telah berkembang menjadi elemen-elemen utama yang mengubah posisi China di dunia. Pengantar baru ini akan membahas perubahan-perubahan tersebut.
Salah satu elemen kunci adalah bagaimana China yang sebelumnya memiliki hubungan simbiotik yang dalam dengan investasi barat kini telah menjadi pesaing utama mereka dalam perebutan pasar dan pengaruh global. Meskipun ekspor masih menjadi andalan ekonominya, China kini tidak hanya menerima investasi asing, tetapi juga menjadi salah satu eksportir modal terbesar ketiga di dunia.
Menurut fDi Markets, anak perusahaan Financial Times, pada 2023 China mencatat rekor investasi luar negeri sebesar 162,7 miliar dolar AS. Dari total investasi yang masuk dan keluar, 82,1 persen berasal dari investasi China ke luar negeri, sementara hanya 17,8 persen berasal dari investasi yang masuk ke China. Sebagian besar investasi China masih mengalir ke Asia Tenggara, tetapi sekarang juga semakin meluas ke Timur Tengah dan Amerika Latin, terutama sejak 2023.
Perkembangan ini terjadi karena kapital domestik China semakin kuat, sementara kapital barat mulai meninggalkan China. FDI Intelligence menjelaskan tren ini sebagai berikut:
“ Profil FDI (Foreign Direct Investment) China tampaknya mengalami pergeseran signifikan, dari negara pengimpor modal menjadi negara pengekspor modal. Selama beberapa dekade, strategi pertumbuhan ekonomi China sangat bergantung pada upaya menarik FDI masuk untuk memanfaatkan modal dan teknologi asing. Seiring dengan perkembangan ekonomi China, serta berkembangnya perusahaan-perusahaan domestik, kebutuhannya akan FDI – khususnya di bidang manufaktur – berkurang. Sementara itu, menarik FDI ke sektor jasa yang bernilai tambah tinggi, yang telah diprioritaskan oleh pemerintah, terbukti lebih sulit dari yang diharapkan.”
Pada saat yang sama, pemerintah China berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan swasta dalam negeri serta negara-negara penerima investasinya untuk membangun proyek-proyek infrastruktur besar. Program ini dikenal sebagai Belt and Road Initiative (Prakarsa Sabuk dan Jalan).
Banyak dari investasi ini digunakan untuk membangun infrastruktur dalam negeri di negara-negara penerima, dengan imbalan negara tersebut membuka sektor-sektor ekonominya yang lain untuk masuknya investasi China.
Laos, misalnya, mendapatkan hibah pembangunan kereta api cepat dari China yang menghubungkannya dengan China dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sebagai gantinya, Laos menyetujui Boten, sebuah kota kecil di dekat perbatasan China yang menjadi salah satu pemberhentian kereta cepat, dimasukkan ke dalam ‘zona kerja sama khusus’ di mana investor China diizinkan memiliki 100 persen kepemilikan atas bisnis dan properti.
Sejumlah proyek lain memiliki karakter lintas negara, yang bertujuan untuk memperlancar ekspor barang dari China ke pasar dunia. Di Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, dan Peru, China telah menandatangani kesepakatan pendanaan untuk membangun pelabuhan mega yang akan menjadi jalur alternatif untuk rute-rute perdagangan laut yang sudah ada, dengan ketentuan bahwa pelabuhan-pelabuhan tersebut beserta kawasan di sekitarnya akan berada di bawah pengelolaan langsung China. Jalur kereta cepat di Laos yang disebut sebelumnya pun merupakan bagian dari rencana besar untuk Asia Tenggara, yang akan menghubungkan Kunming di China dengan Singapura, salah satu pelabuhan utama di kawasan Asia Tenggara. Seluruh proyek ini dimaksudkan untuk menciptakan tekanan persaingan yang kuat terhadap jalur-jalur perdagangan seperti Selat Malaka, yang selama ini berada dalam pengaruh besar negara-negara Barat.
Bersamaan dengan itu, China mendorong pertumbuhan industri teknologi tinggi dan membangun perusahaan-perusahaan teknologi swasta raksasa yang kini menjadi pesaing serius bagi perusahaan-perusahaan Barat. Perkembangan ini baru mulai tampak pada paruh kedua 2010-an, dan mencerminkan langkah signifikan menuju kemandirian dari ketergantungan pada teknologi Barat.
China menjadi produsen kendaraan listrik (EV) terbesar di dunia pada 2022, dengan memproduksi 64 persen dari total EV global. China juga telah mencapai kemajuan signifikan dalam teknologi drone yang diproduksi dalam negeri, kecerdasan buatan, pembuatan mikrochip, sistem operasi smartphone, dan lainnya. Semua upaya ini didorong oleh kebijakan negara yang memberikan subsidi kepada perusahaan swasta, dengan tujuan mengakhiri ketergantungan China pada komponen-komponen yang disuplai Barat dan bersaing dengan mereka di pasar dunia.
Semua perkembangan dalam ekonomi kapitalis China ini – kebangkitan monopoli besar, dominasi kapital finansial, dan dorongan yang semakin kuat untuk mengekspor modal demi mendapatkan pangsa pasar dunia yang lebih besar – mengarah pada definisi klasik imperialisme yang digariskan Lenin dalam karyanya Imperialism: the Highest Stage of Capitalism.
Konflik dengan imperialisme Amerika Serikat, kekuatan imperialis dominan yang semakin menua di dunia, memang tak terhindarkan. Ini akhirnya meledak dengan terpilihnya Donald Trump pada 2016. Meskipun AS sebelumnya telah meluncurkan manuver-manuver licik terhadap China, pemerintahan Trump dengan cepat mengeskalasi ini menjadi perang dagang terbuka. Hubungan yang selama ini dangkal, ramah, dan kolaboratif antara kedua kekuatan itu pun runtuh. Sebagai gantinya, muncul persaingan baru yang semakin intens antara AS dan China.
Persaingan ini kemudian menjadi poros penentu yang melandasi munculnya era baru dalam hubungan dunia. Seiring dengan kemunduran relatif namun signifikan dari imperialisme AS, upaya putus asa untuk mempertahankan dominasinya memaksa negara tersebut mengadopsi kebijakan-kebijakan yang avonturis untuk melawan semua yang dianggapnya musuh, terutama China.
Pemerintahan Biden yang menggantikan kepresidenan pertama Trump tidak hanya tidak meredakan hubungan, tetapi dalam banyak hal justru mengeskalasi konflik tersebut lebih jauh melampaui bidang ekonomi, dengan semakin banyak upaya untuk menekan China di bidang militer, salah satunya dengan memanfaatkan secara sinis isu Taiwan. Perang di Ukraina, yang sebagian besar diprovokasi oleh AS dan NATO, juga merupakan upaya untuk menahan China dengan mengalahkan sekutunya, Rusia, sebuah pesan yang jelas dipahami Beijing.
Namun kebijakan pemerintahan Biden justru menjadi bumerang. Kebijakan AS tidak hanya gagal mengalahkan Rusia, tetapi malah menguatkan negara itu sebagai kekuatan militer. Selain itu, AS juga melemahkan sekutu tradisionalnya di Eropa secara ekonomi – terutama Jerman – dan berkontribusi pada semakin besarnya perpecahan dalam Uni Eropa. AS juga mendorong semua lawannya di berbagai wilayah untuk lebih merapat, terutama China, Rusia, Iran, dan Korea Utara. Di antara mereka, China menjadi kandidat alami untuk memimpin sebuah blok baru. Bahkan, BRICS, dengan China sebagai pemimpinnya, mulai memperluas keanggotaannya dalam upaya menantang tatanan kapitalis dunia yang selama ini didominasi oleh negara-negara imperialis Barat. Meskipun BRICS masih merupakan koalisi negara-negara dengan kepentingan yang berbeda-beda – beberapa di antaranya masih bersekutu dengan imperialisme AS, seperti India misalnya – namun koalisi ini mencerminkan perubahan perimbangan kekuatan antara negara-negara besar.
Selain itu, era baru perang dagang terbuka yang dimulai oleh masa jabatan pertama Trump juga mengakhiri peran AS sebagai pendukung utama perdagangan bebas dengan China. Hal ini sesuai dengan kondisi perkembangan kapitalis tiap-tiap negara. AS adalah kekuatan yang semakin menua, yang dengan mati-matian mencoba dengan segala cara menahan kemunduran relatifnya yang tak terhindarkan di dunia. Sementara itu, China masih merupakan pendatang baru dalam imperialisme, yang dengan keras kepala mencari cara untuk mengekspor barang dan modal yang terlampau banyak diproduksi.
Berbeda dengan klaim kaum kiri yang membela China di seluruh dunia, karakter konflik antara AS dan China saat ini bukanlah pertarungan antara dua sistem sosial yang berbeda. AS menghadapi China bukan sebagai pendukung kapitalisme yang mati-matian berusaha menghancurkan sebuah masyarakat sosialis baru yang tengah berkembang dan dapat menggulingkannya, dengan seluruh kemajuan dan vitalitas historisnya, melainkan sebagai pesaing dalam permainan poker yang sama. Keduanya berusaha untuk mendapatkan keunggulan, dan AS semakin kalah sementara China semakin unggul, namun keduanya berkomitmen untuk tetap memainkan permainan tersebut. Namun, kasino ini sedang terbakar. Ketika kapitalisme dunia tenggelam dalam kemunduran terminal, takdir kapitalisme China terikat padanya.
Penjelasan yang disajikan dalam buku ini, yang mencakup perkembangan China hingga 2015, dengan jelas menunjukkan bahwa perkembangan pesat di China yang dipicu oleh investasi asing sudah menunjukkan tanda-tanda klasik krisis overproduksi. Ini pada gilirannya memunculkan semua gejala yang sama seperti yang terlihat di Barat: jurang yang semakin lebar antara kaya dan miskin, biaya hidup yang terus naik sementara upah tidak pernah dapat mengejarnya, siklus boom-and-bust yang semakin liar, pertumbuhan utang publik dan swasta yang semakin cepat, dan teka-teki kapitalisme yang paling utama – pelambatan ekonomi. Semua komentator ekonomi China mengeluh mengenai “permintaan domestik yang tidak mencukupi.”
Seiring dengan itu, kontradiksi sosial yang tak terhitung jumlahnya mulai bermunculan dalam masyarakat China. Tanggung jawab untuk semua ini jatuh di pundak negara-partai PKC. Berbeda dengan demokrasi borjuis, yang dapat untuk sementara meredakan kemarahan kelas dari bawah melalui pemilu, dengan memilih partai atau koalisi yang berbeda – yang pada dasarnya semuanya membela kapitalisme – kemarahan kelas hanya dapat disalurkan ke satu tempat di China, yaitu ke Partai Komunis China.
Upaya generasi Deng untuk mencapai hasil yang terbaik dari semua skenario, yaitu mengembalikan kapitalisme tanpa menggulingkan kediktatoran politik PKC, awalnya dianggap sebagai solusi bagi birokrasi, namun kemudian menjadi masalah serius bagi mereka. PKC merestorasi kapitalisme dengan janji bahwa selama partai mempertahankan kekuasaan politik, ekonomi dan taraf hidup akan terus tumbuh tanpa henti. Namun kini, rezim ini dihadapkan pada kenyataan yang berlawanan, yang dirasakan oleh ratusan juta pekerja.
Kontradiksi yang tajam ini dan keresahan yang semakin berkembang di dalam masyarakat menjelaskan evolusi rezim Xi Jinping.
Ketika Xi menggantikan kepemimpinan Hu Jintao, dia hampir-hampir tidak dikenal baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai salah satu keturunan dari para pemimpin besar revolusi, jalan Xi menuju puncak lebih didorong oleh silsilahnya daripada pencapaian nyata dalam berbagai jabatan yang dipegangnya.
Xi berbeda dengan Jiang Zemin, yang fasih berbicara bahasa Inggris dan Rusia kepada wartawan asing, untuk mempresentasikan China dengan citra tertentu demi kepentingan kelas penguasa. Xi juga berbeda dengan Hu Jintao, yang mudah blusukan dengan rakyat, terutama saat bencana alam, dengan tampilan yang tulus dan penuh kasih. Xi tidak diberkahi dengan kompetensi, karisma, maupun keramahan. Lalu, bagaimana dia bisa menjadi sosok yang secara luas dianggap sebagai pemimpin PKC yang paling berkuasa sejak Mao Zedong?
Jawabannya terletak pada kemampuannya yang spesifik untuk memahami sedari awal bahaya yang dihadapi seluruh birokrasi. Dengan mengamati mobilisasi massa pada Musim Semi Arab di 2011, dia bisa melihat bagaimana China juga bisa dihadapkan dengan bahaya yang sama dalam momen krisis yang parah. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa rejim harus mengetatkan kontrolnya secara preemptif untuk menyelamatkan seluruh rejim.
Xi adalah salah satu pejabat pertama yang memperingatkan bahwa nasib para diktator di Timur Tengah bisa saja terulang di China jika tidak ada langkah yang diambil untuk mengubah citra PKC sebagai rejim yang sangat korup. Kampanye anti-korupsi menjadi kebijakan khasnya, sampai-sampai dia melanggar aturan lama dengan memenjarakan Zhou Yongkang, seorang mantan pemimpin tertinggi yang selama ini dianggap tidak dapat tersentuh.
Namun, langkah ini tidak dilakukan untuk benar-benar memberantas korupsi, karena semua lapisan birokrasi kini mendapatkan privilese mereka bukan dari ekonomi terencana, tetapi dari kapitalisme. Itu dilakukan untuk menipu kelas pekerja, yang kemarahannya sudah mendekati titik kritis yang berbahaya.
Selanjutnya, ada masalah dalam mengatasi problem ekonomi yang kini sepenuhnya didominasi oleh kekuatan pasar yang anarkis, serta kelas borjuasi yang kuat yang muncul darinya. Elemen-elemen borjuis ini pada dasarnya telah dibesarkan oleh birokrasi, namun karena sifat kelas borjuis yang secara alami selalu ingin mencari keuntungan lebih besar, ini kemudian mendorong sebagian dari mereka untuk mengadopsi langkah-langkah yang dapat mengganggu stabilitas sosial di dalam negeri.
Contoh terbaik adalah Jack Ma, yang dulunya adalah sekutu dekat Xi saat Xi menjabat sebagai gubernur Provinsi Zhejiang. Jack Ma adalah borjuis domestik, yang berangkat dari seorang guru Bahasa Inggris hingga menjadi miliarder pemilik konglomerat Alibaba, sekaligus anggota PKC.
Ketika bisnis Ma mulai merambah sektor keuangan, ia mencoba memperkenalkan skema yang memungkinkan pemberian pinjaman murah kepada jutaan orang dengan kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya bahkan di Barat. Skema ini, melalui Ant Group, berisiko menciptakan gelembung utang yang besar, yang dapat mengguncang stabilitas ekonomi. Negara berusaha mengintervensi untuk memperlambat rencana Ma, dan ketika Ma kemudian secara terbuka mengeluhkan “intervensi negara yang berlebihan,” ia akhirnya disingkirkan dari kepemilikan usahanya, dan perusahaannya diawasi dengan ketat oleh pemerintah.
Apa yang menimpa Ma adalah contoh tipikal strategi rejim PKC di bawah kepemimpinan Xi. Strateginya adalah memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan terbesar, mencegah mereka melakukan ekses-ekses seperti di Barat yang dapat memicu krisis ekonomi dan membangkitkan kemarahan sosial. Di saat yang sama, Xi tetap berusaha menghindari kontrol langsung terhadap ekonomi, dan mempertahankan ekonomi pasar kapitalis dengan segala cara. Untuk itu, penguatan aparatus birokrasi partai-negara menjadi keharusan. Inilah yang didorong oleh Xi, dan karenanya ia memperoleh dukungan dari sebagian besar birokrasi, yang memungkinkan ia memusatkan kekuasaan lebih besar di tangannya sendiri.
Birokrasi di bawah Xi percaya bahwa lewat kepemimpinan negara yang bijaksana dan kuat, sistem kapitalisme bisa diarahkan untuk menghindari kontradiksi-kontradiksi dasarnya. Mereka yakin pemberontakan buruh dapat ditekan dengan represi keras, sementara kapitalis-kapitalis yang berpotensi menggoyahkan stabilitas sistem secara keseluruhan bisa dikendalikan oleh negara. Mereka ingin mempertahankan bentuk kapitalisme yang bebas dari krisis.
Namun, ini hanyalah ilusi. Tidak mungkin ada kapitalisme tanpa krisis siklikal, yang pada gilirannya mempersiapkan kemerosotan serius pada titik tertentu. Hukum-hukum kapitalisme tidak berubah hanya karena ada birokrasi kuat yang bercokol di puncak kekuasaan. Apa yang diproduksi China tetap harus dijual di pasar dunia. Dan dengan berkembangnya alat produksi yang maju dan kompetitif, benturan yang lebih tajam dengan kekuatan-kekuatan kapitalis besar lainnya—khususnya Amerika Serikat—menjadi tak terhindarkan.
China harus merebut porsi pasar global yang lebih besar jika ingin mempertahankan laju pertumbuhan ekonominya yang tinggi. Perkembangan China telah mendorong migrasi besar-besaran ke kota-kota, sebuah pola yang juga terlihat di semua negara yang mengalami industrialisasi dan urbanisasi. Ini berarti, setiap tahun harus diciptakan puluhan juta lapangan kerja baru demi menjaga stabilitas sosial. Namun, dengan melambatnya ekonomi dunia dan meningkatnya kecenderungan proteksionisme secara global, China menghadapi ancaman ketidakstabilan internal yang makin besar.
Selama rezim Xi mampu menjamin pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup, kohesi sosial masih bisa dipertahankan. Tapi begitu jaminan ini mulai goyah, pengangguran pun mulai muncul, dan ini sudah terlihat jelas di kalangan anak muda, dengan tingkat pengangguran yang melampaui 20 persen pada 2023. Inflasi memang masih lebih rendah dibandingkan negara pesaing China, tetapi perlahan-lahan terus merangkak naik. Upah masih terus naik, namun laju kenaikannya mulai melambat. Fenomena penting lainnya adalah meningkatnya kasus upah tak dibayar, yang sudah memicu gelombang protes oleh buruh. Biarpun upah nominal naik, jika pekerja tidak menerima upah mereka, di mana letak manfaat nyatanya?
Kita bisa melihat ke mana semua ini akan bermuara. Cepat atau lambat, tekanan untuk menahan kenaikan upah akan semakin besar, seiring upaya kapitalisme China mempertahankan daya saingnya. Bersamaan dengan itu, dampak dari akumulasi utang yang luar biasa dalam perekonomian China juga akan mulai terasa. Pada Desember 2023, utang nasional China telah mencapai $4,23 triliun. Berdasarkan data IMF tahun 2025, rasio utang pemerintah terhadap PDB China kini sudah melewati 90 persen—angka tertinggi sepanjang sejarah—padahal rata-rata dari 1995 hingga 2023 hanya sekitar setengah dari itu. Dalam tiga tahun ke depan, diperkirakan angka ini akan melampaui 100 persen. Pada akhirnya, level utang seperti ini akan memicu lonjakan inflasi.
Semua yang dipaparkan ini menunjukkan bahwa cepat atau lambat akan ada ledakan perjuangan kelas pada titik tertentu, dan ini akan mengguncang stabilitas rezim. Potensi gelombang protes massa telah tercermin dalam gerakan besar yang memaksa pemerintah mengakhiri kebijakan lockdown COVID-19. Tekanan dari bawah begitu kuat hingga pemerintah terpaksa melonggarkan kebijakan mereka, karena mereka takut akan gelombang protes massa yang lebih luas dan tak terkendali. Ini sekilas memberikan gambaran tentang potensi kekuatan kaum pekerja dan pemuda China, sekaligus menjadi peringatan keras bagi elite penguasa.
Inilah sebabnya mengapa Xi Jinping mengonsolidasikan kekuasaan di tangannya. Ini adalah pola klasik kebangkitan seorang Bonapartis, yang berusaha mengendalikan China demi menjaga kepentingan keseluruhan sistem kapitalisme. Dalam kerangka ini, ia mungkin akan membuat beberapa konsesi kepada kelas pekerja—seperti memaksa perusahaan membayar tunggakan upah—seraya menghantam beberapa kapitalis yang tindakannya dinilai membahayakan kepentingan kapitalisme itu sendiri, sebagaimana yang telah terjadi dalam kasus Jack Ma.
Ini juga menjelaskan mengapa rezim ini berusaha mengalihkan perhatian massa ke luar negeri, dengan terus-menerus menggaungkan ancaman serangan dari kekuatan asing, terutama Amerika Serikat. Kembalinya Trump ke panggung politik tentu akan semakin memudahkan upaya ini. Trump punya rencana serius untuk menekan China di pasar dunia, sebuah kebijakan yang sebenarnya sudah ia mulai pada masa jabatan pertamanya, kemudian dilanjutkan oleh Biden.
China kini telah menjadi kekuatan imperialis baru yang memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia melalui ekspor modal dalam skala besar. Namun, bersamaan dengan kekuatan ekonomi, pada titik tertentu kebutuhan akan kekuatan militer juga muncul. Pada 2023, belanja militer China diperkirakan mencapai $296 miliar, sepuluh kali lipat dibandingkan 25 tahun yang lalu, yang menjadikannya negara dengan anggaran militer terbesar kedua setelah Amerika Serikat yang menghabiskan $916 miliar.
Kebijakan ekspansionis China tercermin dalam meningkatnya ketegangan di sekitar Taiwan. Di satu sisi, ini mencerminkan ambisi nyata China untuk memperluas dan memperkuat wilayah pengaruhnya, di mana Taiwan dianggap sebagai bagian integral China. Di sisi lain, isu ini juga menjadi alat untuk mengalihkan perhatian rakyat dari masalah-masalah domestik. Ketika kelas penguasa menghadapi tekanan ekonomi dan sosial di dalam negeri, yang berisiko memicu ketegangan kelas, mengarahkan perhatian publik pada “ancaman eksternal” menjadi salah satu cara klasik untuk membangkitkan semangat nasionalisme.
Xi Jinping telah memperhatikan bagaimana sanksi Barat menghantam ekonomi Rusia setelah pecahnya perang di Ukraina, dan ini mendorong China untuk mempertahankan Taiwan dalam lingkup pengaruhnya. China memiliki lebih dari US$3,3 triliun cadangan devisa, yang merupakan cadangan devisa terbesar di dunia. Mereka melihat bagaimana Amerika Serikat dan sekutunya membekukan aset Rusia di luar negeri. Untuk menghindari skenario serupa dalam menghadapi krisis serius terkait Taiwan, rezim kini berusaha mendiversifikasi cadangan devisanya yang tersimpan di luar negeri.
Namun, apapun upaya rezim untuk memperkuat posisinya dan membangun pertahanan terhadap sanksi-sanksi ekonomi seperti itu, mereka tetap tidak bisa menghindari dampak umum sanksi-sanksi ini, yang akan mengguncang ekonomi dunia secara keseluruhan. Sanksi-sanksi yang kemungkinan besar akan diterapkan oleh Amerika Serikat dan sekutu Baratnya terhadap China akan menandai awal dari perang dagang besar-besaran, yang akan mendorong ekonomi dunia ke jurang resesi yang dalam. Ini pada gilirannya akan sangat berdampak pada ekonomi China. China harus meningkatkan ekspornya untuk mempertahankan pertumbuhan dan stabilitas. Dalam skenario seperti itu, yang akan terjadi justru sebaliknya.
Ketergantungan China pada ekspor lahir dari kenyataan bahwa, seperti semua ekonomi kapitalis, ia pasti akan berhadapan dengan krisis overproduksi, yang kini tampak di mana-mana. Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan yang selama ini diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pengeluaran negara ala Keynesianisme, telah menciptakan problem lainnya, yaitu menumpuknya utang.
Semua ini niscaya mengarah pada perlambatan ekonomi China. Secara resmi, pertumbuhan tahunan saat ini berada di kisaran 5 persen, jauh lebih rendah dibandingkan masa kejayaan China ketika pertumbuhan mencapai 13 hingga 14 persen per tahun. Selama China mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan 7-8 persen per tahun, maka stabilitas sosial dapat terus terjaga, dengan menciptakan sekitar 20 juta lapangan kerja baru setiap tahunnya. Tapi masa itu sudah berakhir. Kini, pertumbuhan diperkirakan akan terus melambat, turun ke 4-5 persen, lalu 2-3 persen, dan pada satu titik, China bisa saja mengalami resesi ekonomi.
Semua ini berkontribusi pada perubahan besar dalam kesadaran, di mana ratusan juta pekerja dan kaum muda di China mulai melihat bahwa kapitalisme tidak menawarkan masa depan bagi mereka. Inilah yang mendorong rezim Xi Jinping berusaha keras menjaga stabilitas. Mereka melakukannya dengan dua cara. Di satu sisi, mereka mencoba memperluas pasar ekspor, tetapi kita melihat bagaimana ini dihadapkan dengan pasar dunia yang terbatas. Di sisi lain, rejim mengadopsi kebijakan yang semakin represif. Namun sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan berbasis represi semata tidak bisa bertahan selamanya.
Semua tanda mengarah pada kemungkinan besar terjadinya krisis ekonomi pada titik tertentu. Ini akan mempersempit ruang gerak rezim dan memicu krisis internal dalam pemerintahan. Dari rezim yang saat ini tampak stabil, yang kekuasaannya terkonsentrasi di tangan Xi, kita akan mulai melihat keretakan-keretakan, dengan berbagai faksi birokrasi saling bentrok soal bagaimana mempertahankan sistem mereka. Ketika itu terjadi, jalan akan terbuka bagi rakyat untuk memasuki arena politik. Perjuangan kelas akan meledak dalam skala yang belum pernah terlihat dalam sejarah China.
Puluhan tahun pertumbuhan pesat ekonomi China telah menciptakan sesuatu yang sangat penting: lahirnya kelas pekerja modern dan maju. Data terakhir menunjukkan bahwa ada lebih dari 470 juta pekerja upahan di kota-kota, dan mayoritas adalah buruh, dengan 30 persen di antaranya adalah buruh industri.
Secara objektif, perimbangan kekuatan kelas di China kini sangat menguntungkan kaum pekerja. Dan sekali kekuatan ini bergerak, tidak ada yang mampu menghentikannya. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah partai yang mampu memimpin mereka menuju revolusi sosialis yang sejati. Pada 1921, segelintir komunis mendirikan Partai Komunis China sebagai bagian dari Komunis Internasional. Pada masa-masa awalnya, mereka setia pada gagasan revolusioner Lenin, dan tumbuh cepat saat revolusi 1926 bergulir. Momen itu memberi kita gambaran tentang potensi besar yang dapat terulang hari ini.
Buku ini bertujuan untuk mengungkap sejarah sejati perjuangan kelas di China selama seratus tahun terakhir. Kini sejarah seolah berputar kembali, tetapi di tingkat yang jauh lebih tinggi. Masyarakat China sedang bergerak menuju sebuah krisis besar yang akan membangkitkan seluruh potensi kelas pekerja. Tugas kaum Marxis adalah menggali sepenuhnya pelajaran dari pengalaman masa lalu, agar kesalahan yang sama tidak terulang, sekaligus menunjukkan jalan yang benar bagi generasi baru kaum revolusioner di China hari ini.
14 Februari 2025