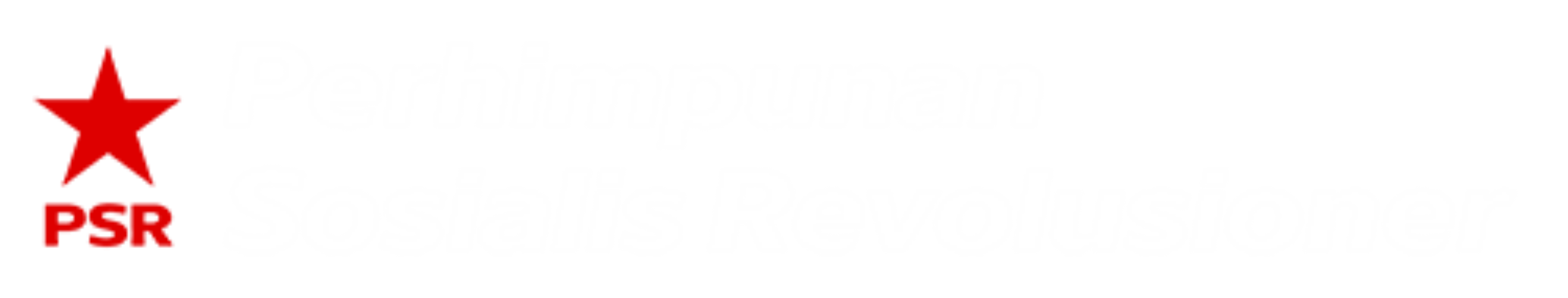Salah satu topik yang sering dibahas di kalangan komentator borjuis saat ini adalah kemunculan para pemimpin bergaya ‘strongman’(Pemimpin Kuat). Dalam beberapa tahun terakhir, para komentator ini mengatakan ada ‘kemunduran demokrasi’ yang melahirkan sosok-sosok pemimpin otoriter yang dianggap mengancam nilai-nilai demokrasi liberal. Fenomena ini menjadi sumber kekhawatiran besar bagi sayap kelas penguasa yang ‘lebih bertanggung jawab’.
Tahun lalu, Gideon Rachman, kolumnis utama urusan luar negeri di Financial Times Inggris, menerbitkan sebuah buku berjudul The Age of the Strongman: How the Cult of the Leader Threatens Democracy Around the World. Dalam bukunya, Rachman memperingatkan bahaya yang ditimbulkan oleh gelombang baru politik pemimpin kuat terhadap demokrasi liberal.
Ia memasukkan sejumlah nama ke dalam kategori ‘strongman’, di antaranya: Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Xi Jinping, Narendra Modi, Viktor Orbán, Boris Johnson, Donald Trump, Mohammed bin Salman Al Saud, Benjamin Netanyahu, Jair Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador, dan Abiy Ahmed.
Dalam analisisnya, Rachman secara superfisial mendaftarkan kesamaan-kesamaan di antara para pemimpin otoriter: nasionalisme, ketidaksukaan terhadap ‘elit global’, kultus individu, penggunaan media sosial, dan kecenderungan terhadap korupsi, di antara ciri-ciri lainnya. Namun, ia menghindari upaya untuk menjelaskan proses mendasar yang melahirkan rezim-rezim tersebut.
Misalnya, Rachman menyebut bahwa kekuasaan Putin di Rusia berdiri di atas korupsi dan nasionalisme. Tetapi ini sebenarnya tidak menjelaskan apa-apa. Korupsi dan nasionalisme, dalam kadar yang berbeda, selalu ada di hampir semua rezim kapitalis sepanjang sejarah. Yang tidak dijawab Rachman adalah mengapa dan bagaimana faktor-faktor itu melahirkan rezim seperti Putin dalam momen sejarah tertentu.
Sebaliknya, Rachman hanya menyajikan potret-potret dangkal tentang pemimpin-pemimpin ‘strongman’ secara terpisah, seolah-olah politik semata-mata ditentukan oleh karakter dan kehendak individu. Pendekatan seperti ini bukan hanya menutupi perbedaan penting di antara berbagai rejim – misalnya antara pemerintahan Putin dan pemerintah ‘populis’ seperti Donald Trump – tetapi juga membuat kita tidak mampu menarik kesimpulan penting untuk masa depan, jika kita mengikuti pola pikir Rachman.
Yang kurang dari analisis Rachman adalah pemahaman tentang perjuangan kelas di setiap masyarakat, dan dalam skala global. Setiap upaya memahami negara dan watak politiknya tanpa mempertimbangkan tempo dan kondisi perjuangan kelas pada momen tertentu, hanya akan menghasilkan kesimpulan yang dangkal.
Sebaliknya, Karl Marx meneliti sejarah dan perkembangan perjuangan kelas, arah pergerakannya, serta bentuk-bentuk politik yang lahir darinya.
Dalam Manifesto Komunis, Marx dan Engels menulis, “Sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga sekarang adalah sejarah perjuangan kelas.” Rezim-rezim politik yang akan mewarnai sejarah masa kita sekarang bukanlah hasil kreasi para ahli pencitraan atau pemimpin yang sekadar tahu cara menyuap pihak yang tepat. Mereka hanya bisa dipahami sebagai hasil dari tahapan tertentu dalam perkembangan perjuangan kelas.
Dalam karyanya The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, Marx menganalisis bagaimana seorang ‘strongman’ lainnya, Napoleon III, berhasil merebut kekuasaan. Kesimpulan teoretis yang ia tarik dari peristiwa tersebut hingga kini tetap menjadi alat penting untuk memahami hakikat negara dan prospek kemunculan para ‘strongman’ di zaman sekarang.
Teori Marxis Mengenai Negara
Sebelum kita bisa memahami watak politik dari suatu rezim – entah itu demokrasi liberal maupun kediktatoran – kita harus terlebih dahulu memahami peran negara dalam masyarakat.
Negara adalah alat kekuasaan kelas. Ia dimiliki dan dijalankan oleh kelas penguasa di setiap masyarakat. Negara modern, misalnya, terhubung erat dalam ribuan cara dengan kepentingan kapitalis.
Fenomena “pintu putar” antara dunia bisnis dan pemerintah sudah menjadi rahasia umum:, yang memastikan agar para menteri dan pejabat dapat dengan mudah pindah ke perusahaan-perusahaan yang seharusnya mereka awasi. Lobi-lobi korporasi besar memiliki akses langsung ke para pengambil keputusan negara, memanfaatkan berbagai bentuk “bujukan”, dari sogokan hingga ancaman, untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan kepentingan borjuasi. Sementara itu, lembaga-lembaga negara seperti pengadilan, penjara, polisi, dan militer, digunakan untuk melindungi kepemilikan pribadi kaum kaya, sedangkan hak-hak dasar rakyat miskin atas pangan dan papan diabaikan. Hak-hak ini hanya diperoleh lewat perjuangan kelas.
Para menteri, pejabat tinggi, hakim, jenderal, kepala kepolisian, dan aparat negara lainnya umumnya berasal dari lapisan masyarakat yang sangat sempit, yang dibesarkan dan dididik dengan cara pandang kelas kapitalis. Di Inggris, misalnya, 65 persen pejabat sipil tingkat atas bersekolah di institusi swasta elite, begitu pula 65 persen hakim senior, 70 persen jenderal, dan 65 persen menteri senior dalam pemerintahan.
Hubungan erat antara negara dan kelas penguasa bukanlah ciri khas kapitalisme semata. Sejak pertama kali muncul dalam sejarah sekitar 5.000 tahun lalu, negara sudah berfungsi sebagai alat kekuasaan kelas. Sejak masyarakat terbelah menjadi kelas yang menindas dan kelas yang ditindas, negara hadir untuk mengelola konflik di antara mereka – konflik yang, tanpa keberadaan negara, bisa saja menghancurkan masyarakat dari dalam.
Sebagaimana dijelaskan oleh Engels:
“Negara adalah pengakuan bahwa masyarakat ini telah terjerat dalam kontradiksi yang tak terpecahkan dengan dirinya sendiri, bahwa masyarakat ini telah terpecah belah ke dalam antagonisme-antagonisme tak-terdamaikan yang tak mampu ia singkirkan. Tetapi agar antagonisme-antagonisme ini, yaitu kelas-kelas dengan kepentingan ekonomi yang bertentangan, tidak lantas menghancurkan diri mereka sendiri dan masyarakat dalam perjuangan yang sia-sia, maka diperlukan sebuah kekuasaan, yang tampaknya berdiri di atas masyarakat, untuk melunakkan konflik tersebut dan menjaganya dalam batas-batas ‘ketertiban’.”
Negara bukanlah wasit netral di antara kelas-kelas yang saling bertentangan. Ia justru menjadi alat di tangan kelas yang berkuasa, digunakan untuk menjaga dominasi mereka dan mempertahankan hubungan kepemilikan yang ada. Seperti yang dijelaskan Engels, “Negara adalah ikatan utama dalam masyarakat beradab, yang dalam setiap periode sejarah selalu, tanpa pengecualian, merupakan negara milik kelas penguasa, dan dalam setiap kasus, pada hakikatnya tetap menjadi mesin untuk menindas dan mengeksploitasi kelas tertindas.”
Inilah sebabnya mengapa otoritas negara memiliki monopoli sah atas penggunaan kekerasan melalui polisi, tentara, dan penjara. Karena itulah Marx dan Engels menyatakan bahwa “lembaga eksekutif negara modern tidak lain adalah komite untuk mengelola masalah bersama seluruh borjuasi.”
Untuk bisa mempertahankan relasi kepemilikan di tengah konflik kelas, dan membenarkan monopoli kekerasannya, negara harus tampil seolah-olah berada di atas masyarakat, terpisah dari kepentingan kelas manapun. Ia mesti membungkus dirinya dengan kemegahan dan mistifikasi untuk menyembunyikan perannya sebagai alat kelas penguasa.
Dulu, para raja feodal di Eropa mengklaim bahwa kekuasaan mereka berasal dari hak ilahi, dipilih dan dipandu langsung oleh Tuhan. Di sisi lain, negara-negara ‘demokrasi’ modern kini membungkus kekuasaannya dengan bahasa ‘hak pilih’, ‘hak asasi manusia’, dan ‘supremasi hukum’.
Atribut-atribut ‘demokratis’ ini sangat berguna bagi kaum kapitalis. Melaluinya, kelas kapitalis bisa mengendalikan mekanisme negara secara keseluruhan, lewat wakil-wakil bayaran mereka di parlemen, media massa, lembaga peradilan, birokrasi negara yang luas, hingga angkatan bersenjata.
Kejatuhan yang begitu cepat dari pemerintahan Truss di Inggris pada 2022 memperlihatkan kenyataan ini dengan gamblang. Reaksi pasar terhadap kebijakan-kebijakannya, ditambah tekanan dari lembaga kapitalis seperti IMF, memaksanya turun hanya dalam 44 hari.
Lebih dari itu, ‘demokrasi’ borjuis juga menciptakan ilusi pilihan bagi rakyat, sehingga mereka bisa mengganti individu dan partai politik melalui pemilu tanpa pernah benar-benar mengancam sistem kapitalisme itu sendiri. Ini memperkuat mitos bahwa negara bersifat netral dan berada di atas pertentangan kelas.
Inilah mengapa, secara umum, bentuk negara yang paling efektif bagi kapitalisme adalah republik demokratik.
Seperti yang dijelaskan Lenin, “Republik demokratik adalah cangkang politik terbaik bagi kapitalisme; oleh karenanya, setelah kapital telah memperoleh cangkang terbaik ini, ia menegakkan kekuasaannya dengan begitu aman, begitu kokoh, sehingga tidak ada perubahan personel, lembaga atau partai dalam republik borjuis-demokratis yang dapat menggoyahkan kekuasaannya.” (Negara dan Revolusi)
Monopoli kekerasan dan alienasi negara dari masyarakat adalah krusial bagi efektivitas negara sebagai senjata kelas penguasa. Namun, dalam kondisi tertentu, kedua hal itu bisa berkembang menjadi kekuatan yang seolah-olah mandiri. Engels menjelaskan:
“Terdapat masa-masa di mana kelas-kelas yang bertikai saling menyeimbangkan satu sama lain sedemikian rupa sehingga kekuasaan negara memperoleh, untuk sementara waktu, kemandirian tertentu dari keduanya dan seolah-olah tampil sebagai penengah
Seperti dalam kisah The Sorcerer’s Apprentice, kelas penguasa kadang mendapati bahwa mereka telah membangkitkan kekuatan yang tak lagi mampu mereka kendalikan.
Contohnya, pada tahun 2000, Vladimir Putin menjadi Presiden Rusia dan segera menjebloskan Vladimir Gusinsky – seorang raja media, pemilik bank, dan taipan properti – ke penjara dan mengusirnya, setelah media milik Gusinsky mengkritik pemerintahannya.
Tak berhenti di situ, Putin juga menyasar Mikhail Khodorkovsky, taipan minyak, orang terkaya di Rusia sekaligus lawan politiknya. Pada 2003, Khodorkovsky dipenjara dan seluruh kekayaan serta asetnya disita.
Alih-alih menjadi pelayan bagi kelas penguasa Rusia, Putin justru tampil sebagai tuan atas mereka. Fenomena ketika aparatus negara mengangkat dirinya di atas masyarakat, dengan seorang ‘pemimpin besar’ di pucuknya, inilah yang oleh Marx disebut sebagai ‘Bonapartisme’.
Bonapartisme
Bukan pertama kalinya negara, yang seharusnya menjadi pelayan kelas penguasa, justru berbalik melawan sebagian tuannya sendiri. Sosok yang paling ikonik dari fenomena ini adalah Napoleon Bonaparte.
Napoleon naik ke tampuk kekuasaan di tengah surutnya Revolusi Prancis. Sejak 1789, aliansi antara kaum borjuis, massa semi-proletar Paris, dan kaum tani Prancis telah menggulingkan monarki, membagikan tanah kepada para petani, serta mengobarkan perang melawan Eropa feodal, membuka jalan bagi perkembangan kapitalisme.
Komite Keamanan Publik Revolusi meluncurkan Teror Jacobin untuk menghancurkan kekuatan kontra-revolusi yang hendak merestorasi monarki. Namun, terdorong oleh keberhasilan mereka, massa Paris mulai melangkah lebih jauh. Mereka menafsirkan semboyan “Liberté, Égalité, Fraternité” secara harfiah, dan mulai mengambil tindakan yang mengancam keberadaan hak milik pribadi.
Ini merupakan puncak tertinggi revolusi, namun justru pada titik ini kaum borjuis dan kaum tani mulai mundur. Jumlah mereka yang lebih besar dibandingkan “massa Paris” membuat arah revolusi perlahan berbalik Pertama-tama, Robespierre dan Komite Keamanan Publik dan digantikan oleh Direktori, yang melancarkan teror baru – teror putih – terhadap unsur-unsur paling revolusioner, dengan tuntutan agar “ketertiban” dipulihkan, yang sebenarnya berarti mempertahankan ketertiban borjuis yang baru dibangun.
Kaum borjuis telah mengerahkan massa untuk berjuang pada 1789, namun setelah berhasil menggulingkan monarki, mereka gagal menguasai keadaan secara menentukan. Revolusi pun terjebak dalam kebuntuan, dan kekerasan menjadi faktor penentu.
Terdampar di antara konspirasi dan pemberontakan kaum royalist – seperti pemberontakan Chouan di wilayah Barat – serta ancaman kebangkitan kembali kaum Jacobin di Paris, kaum borjuis mendambakan adanya “pemerintahan yang stabil” dan mereka ingin mengakhiri kondisi “anarki” secara tuntas.
Napoleon, yang baru saja meraih kemenangan militer dan didukung secara setia oleh pasukannya – yang sebagian besar berasal dari kalangan tani – muncul sebagai penyelamat yang selama ini dinantikan borjuasi. Abbé de Sieyès, salah satu tokoh penting dalam Direktori, bersama Joseph Fouché, Menteri Kepolisian, dan Charles-Maurice de Talleyrand, Menteri Luar Negeri, mengundang Napoleon untuk menggunakan kekuatan militer menggulingkan pemerintahan mereka sendiri pada 18 Brumaire, tahun VIII Republik (9 November 1799).
Begitu berkuasa, Bonaparte menyeimbangkan kelas-kelas yang saling bertikai. Kepada kaum borjuis, ia menjanjikan ketertiban dan penghentian kerusuhan serta gejolak revolusioner. Sementara kepada para prajurit dan rakyat, ia berjanji untuk menyelamatkan revolusi dari ancaman konspirasi kaum monarki. Sementara, ia mengangkat dirinya dan aparatus kekerasannya ke atas semua kelas sosial.
Meski demagoginya sering kali kontradiktif dan penuh eufemisme karena dia mencoba memuaskan semua pihak, pada intinya Napoleon tetap mempertahankan sistem kepemilikan pribadi yang telah ditegakkan melalui revolusi borjuis.
Napoleon tak punya banyak pilihan dalam hal ini, sebab kekuatan utamanya bertumpu pada kaum tani yang mengisi barisan tentaranya. Kaum tani ini tidak tertarik pada tuntutan kaum semi-proletar Paris; yang mereka inginkan adalah mempertahankan kepemilikan tanah yang telah mereka peroleh dari revolusi melawan monarki.
Seiring pertumbuhan ekonomi, Napoleon mampu meredam keresahan massa sambil mengkonsolidasikan kekuasaannya. Ia tetap berbicara seolah membela revolusi, namun secara bertahap membongkar tatanan politik yang telah dibangun revolusi itu. Yang dipertahankannya hanyalah fondasi ekonomi baru berbasis kapitalisme, yang telah menggantikan sistem feodal.
Setelah posisinya aman, Napoleon mengandalkan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. Ia membangun jaringan mata-mata, membuka kembali penjara-penjara monarkis, memberangus kebebasan pers, memulihkan kedudukan gereja, serta melancarkan ekspedisi militer dan penjarahan ke luar negeri. Dia berkuasa dengan pedang, dan pada 1804 ia menobatkan dirinya sendiri sebagai Kaisar. Semua ini disajikan kepada rakyat sebagai fait accompli, kemudian disahkan melalui ‘plebisit’ (referendum) tanpa adanya kebebasan berdiskusi ataupun pilihan alternatif.
Meski demikian, tak ada perubahan mendasar terhadap watak borjuis dari rezim pasca-revolusi. Napoleon tidak membatalkan pencapaian utama revolusi seperti penghapusan kepemilikan feodal dan pembagian tanah. Yang berubah adalah karakter politik rezim tersebut: dari demokrasi menjadi kediktatoran, dengan mesin negara raksasa yang dibiayai bersama oleh kaum borjuis dan rakyat.
Inilah Bonapartisme dalam bentuk tipikalnya, yang oleh Trotsky didefinisikan sebagai “pemerintahan birokratik-polisi yang berdiri di atas masyarakat dan mempertahankan dirinya melalui keseimbangan relatif antara dua kubu yang saling bertentangan,” yang mengajukan dirinya sebagai “Penengah Imparsial” bangsa. (Trotsky, The Struggle Against Fascism in Germany)
Pemimpin kuat ini kemudian memerintah dengan kekerasan terbuka, menundukkan semua pihak di bawah kekuasaan eksekutifnya, tanpa mengubah karakter kelas dari rezim yang ada. Kekerasan kerap kali diarahkan, baik kepada individu-individu dari kelas penguasa atau lapisan penguasa tertentu maupun terhadap massa rakyat, saat rezim mencoba mempertahankan keseimbangan di antara berbagai kekuatan sosial.
Keponakan Napoleon, Louis Bonaparte, meniru jejak pamannya ketika ia menggulingkan Republik Kedua Prancis melalui kudeta militer pada 1851, lalu memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar pada tahun berikutnya.
Dalam The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, Marx menjelaskan bahwa dalam upayanya untuk menumpas gerakan massa setelah Revolusi 1848, kaum borjuis terpaksa membongkar seluruh organ-organ demokratis negara supaya tidak direbut oleh kaum “Merah” dari Partai Sosial Demokrat. Pada saat yang sama, borjuasi semakin menyerahkan kekuasaan ke tangan eksekutif negara, yang dipimpin oleh presiden saat itu, Louis Bonaparte. Seperti kata Marx, Bonaparte akhirnya “diangkat ke tampuk kekuasaan di atas pundak serdadu mabuk, yang ia suap dengan wiski dan sosis.”
Para tentara mabuk ini membantai ratusan pekerja yang memprotes kudeta Louis Bonaparte, menangkap puluhan ribu lainnya, dan memberlakukan sensor ketat terhadap pers.
Namun kekerasan dan represi tidak hanya ditujukan kepada kaum pekerja. Marx mencatat: “Kaum borjuis yang fanatik akan ketertiban ditembaki dari balkon mereka oleh gerombolan serdadu mabuk, rumah-rumah mereka dijarah, rumah-rumah mereka dibombardir sekadar untuk hiburan.”
Meski ada kekerasan terhadap individu-individu dari kalangan borjuis dan penjarahan oleh pasukan Bonaparte, struktur masyarakat borjuis secara fundamental tidak pernah diancam. Relasi kepemilikan pribadi tetap dipertahankan. Individu-individu dari kelas borjuis tidak selalu imun dari pedang rejim ini, namun secara keseluruhan, kelas borjuis bersedia menoleransi kekejaman Louis Bonaparte selama ia mampu menjamin “ketertiban” dan mengakhiri masa gejolak revolusioner pasca-1848.
Rusia di bawah Putin
Baik rezim Napoleon maupun rezim keponakannya bukanlah sebuah cetak biru yang selalu harus diikuti. Ketika kaum Marxis menyebut suatu rezim sebagai ‘Bonapartis’, yang dimaksud adalah analogi dengan pemerintahan Napoleon, bukan jiplakan persis.
Ada sejumlah kemiripan, misalnya, antara Napoleon Bonaparte dan Vladimir Putin, meskipun tentu jauh dari sekadar jiplakan.
Restorasi kapitalisme di Rusia pada awal 1990-an merupakan pukulan besar bagi rakyat Rusia. Proses itu memicu pesta pora gangsterisme oleh borjuasi baru yang tengah muncul. Aset-aset negara dijual murah, sementara korupsi menyusup ke setiap lapisan masyarakat.
Di bawah Presiden Boris Yeltsin, kelas kapitalis begitu busuk dan rakyat pekerja begitu melarat sehingga ini mengancam stabilitas sosial, dengan potensi ledakan ketidakpuasan massa yang sempat beberapa kali muncul ke permukaan. Sebagai respons, rezim “demokratis” Yeltsin semakin mengandalkan represi, bahkan sampai membombardir Gedung Kongres Rusia pada 1993 dengan para deputi masih berada di dalamnya.
Metode-metode semacam itu biasanya akan dianggap sangat “otoriter” oleh para komentator liberal. Namun menariknya, pada saat itu, Yeltsin justru dipuji sebagai pemimpin pemberani dan pembela demokrasi oleh seluruh media borjuis. Alasannya sederhana: tindakan represif Yeltsin bukanlah bentuk kekuasaan pedang yang berdiri di atas semua kelas, melainkan pedang di tangan oligarki kapitalis, meskipun digunakan dalam situasi yang sangat tidak stabil.
Seiring berlarutnya krisis, bukan hanya Yeltsin, melainkan seluruh lapisan penguasa menjadi sangat dibenci rakyat. Antara 1996 hingga 1998, gelombang pemogokan dan pendudukan pabrik meletus di seluruh negeri, yang mengekspresikan perlawanan sengit terhadap upaya pemulihan kapitalisme. Namun, potensi besar dari gerakan ini justru disia-siakan oleh para pemimpin “Komunis” yang ada saat itu.
Gagalnya kelas pekerja untuk menggulingkan rezim tidak menghentikan krisis dan ketidakstabilan yang mencengkeram masyarakat Rusia. Dalam kondisi yang putus asa ini, hukum dan ketertiban mulai runtuh; penculikan dan pembunuhan terhadap para pengusaha kaya menjadi hal yang lumrah. Fenomena ini menebarkan ketakutan di kalangan ‘oligarki’ kapitalis baru, yang telah memperkaya diri dengan merampok aset-aset negara.
Situasi ini mendorong kebutuhan akan sosok “netral”, seseorang yang dapat melindungi kekayaan para oligarki tanpa terlihat terlalu dekat dengan imperialisme Amerika atau korupsi brutal di pemerintahan. Putin, mantan agen KGB sekaligus birokrat ulung, memenuhi kriteria ini. Awalnya ia tidak merebut kekuasaan dengan kekuatan sendiri; melainkan dipilih oleh faksi tertentu dari kalangan oligarki dan disajikan kepada rakyat sebagai simbol “perubahan” dari masa lalu.
Putin naik ke tampuk kekuasaan pada 1999, membawa janji kepada para oligarki: kekayaan mereka akan aman selama mereka mendukungnya. Di saat yang sama, ia secara publik menyerang sejumlah kapitalis Rusia dengan tuduhan korupsi, sementara membangun citra dirinya sebagai “sahabat rakyat”.
Dengan cerdik, ia menyeimbangkan kelas-kelas yang bertikai, melontarkan janji-janji dan seruan populis kepada kelas kapitalis dan kelas buruh. Namun di balik itu, ia secara sistematis memperkuat negara dan aparatus keamanannya, mengangkat dirinya di atas masyarakat dan menundukkan semua kelas di bawah kendali negara.
Pergulatan kelas di Rusia kala itu mencapai titik keseimbangan tertentu, akibat kelelahan kedua belah pihak. Kaum borjuasi terlalu lemah untuk memerintah secara langsung, sementara massa buruh belum mampu merebut kekuasaan. Meskipun kondisi ini berbeda dari yang terjadi di Prancis era Napoleon, hasil akhirnya tetap serupa: kebuntuan di antara dua kelas utama.
Namun, situasi seperti ini tak bisa bertahan selamanya. Pada akhirnya, jalan keluar dari krisis harus ditemukan. Bila solusi politik tak muncul dari kemenangan satu kelas atas yang lain, maka kekuasaan akan beralih ke “badan khusus orang-orang bersenjata” yang membentuk negara, yang dipimpin oleh pemimpin kuat di puncaknya.
Tak lama setelah terpilih pada 2000, sebuah dokumen bocor ke harian Kommersant di Rusia – sebuah cetak biru tentang rencana memperkuat aparatus negara demi menopang kekuasaan Putin.
Dokumen itu, berjudul Revisi Nomor Enam, memaparkan strategi memperluas kekuasaan Dinas Keamanan Federal (FSB), membatasi kebebasan media, serta memanipulasi hasil pemilu melalui pengawasan negara dan operasi intelijen tersembunyi.
Selama dua dekade terakhir, inilah yang menjadi ciri khas Rusia di bawah Putin. Para lawan politiknya ditangkap, bahkan ada yang dibunuh. Pemilu dimanipulasi, sementara konstitusi Rusia diinjak-injak.
Di bawah Putin, aparatus negara diperkuat secara besar-besaran untuk mengukuhkan kekuasaannya. Negara melindungi kepentingan kelas kapitalis Rusia, namun tetap berdiri di atas mereka, bukan di bawah kendalinya. Inilah yang membuat rezim Putin bersifat Bonapartis.
Trump, Johnson dan Bolsonaro
Namun, jika kita melihat rezim-rezim lain yang disebutkan oleh Rachman dan mencoba menarik analogi yang sama dengan rezim Napoleon, kita akan menemukan bahwa analoginya tidak berlaku.
Donald Trump, Boris Johnson, dan Jair Bolsonaro tidak naik ke tampuk kekuasaan karena kebuntuan perjuangan kelas yang membuat letih kelas-kelas yang bertikai. Amerika Serikat, Inggris, dan Brasil jelas tidak mengalami guncangan sosial besar seperti Revolusi Prancis 1789, atau pemulihan kapitalisme di Rusia awal 1990-an.
Faktanya, ketika mereka semua terpilih, di ketiga negara tersebut, kelas buruh justru mulai bangkit kembali, merenggangkan ototnya, dan bersiap untuk berjuang.
Di Amerika Serikat, misalnya, gerakan Black Lives Matter (BLM) yang meledak setelah pembunuhan George Floyd oleh seorang polisi Minneapolis, menjadi salah satu mobilisasi massa terbesar dalam sejarah negara itu – dan terjadi saat Trump masih berkuasa.
Antara 26 Mei hingga 22 Agustus 2020, tercatat lebih dari 7.750 demonstrasi yang terkait dengan gerakan Black Lives Matter (BLM) terjadi di lebih dari 2.240 lokasi di seluruh Amerika Serikat. Begitu kuatnya tekanan gerakan ini hingga Dewan Kota Minneapolis memutuskan untuk membubarkan departemen kepolisian mereka sendiri.
Di Brasil, situasi serupa terjadi. Pada 14 Juni 2019, jutaan buruh melakukan aksi mogok massal menentang serangan pemerintahan Bolsonaro terhadap tunjangan pensiun dan pendidikan. Aksi protes ini meluas ke 380 kota di seluruh negeri. Sementara itu, upaya Bolsonaro untuk mengerahkan demonstrasi tandingan hanya mampu menarik sekitar 20.000 orang di kota-kota besar.
Jauh dari kondisi kebuntuan, perjuangan kelas di negara-negara ini justru mulai memanas. Oleh karena itu, menyamakan Trump, Johnson, atau Bolsonaro dengan Putin merupakan kesalahan besar dalam membaca tahapan perjuangan kelas yang tengah berlangsung di masing-masing negara tersebut.
Memang benar, secara pribadi, Trump, Johnson, dan Bolsonaro memiliki kecenderungan untuk bergerak di luar kendali penuh kelas penguasa mereka. Ketiganya kerap melontarkan seruan demagogi kepada massa, meski tetap merupakan bagian dari kelas penguasa itu sendiri. Ada unsur menyeimbangkan kelas-kelas dalam retorika “anti-kemapanan” yang mereka usung.
Namun, motivasi pribadi para pemimpin hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan gambarannya. Bahkan jika Trump, Johnson, atau Bolsonaro ingin menjadi sosok Bonapartis, keinginan itu saja tidak cukup untuk mewujudkannya. Semuanya bergantung pada perimbangan kekuatan kelas dalam masyarakat, serta tahapan perjuangan kelas yang sedang berlangsung.
Dalam ketiga kasus tersebut, aparatus negara – khususnya lembaga-lembaga bersenjata yang menjadi inti kekuatan negara – tetap berada kokoh di bawah kendali kelas penguasa, bukan di tangan para pemimpin yang tidak dapat diandalkan di Gedung Putih, Downing Street, atau Palácio da Alvorada.
Pada 2019, Boris Johnson sempat membekukan parlemen Inggris. Dia melangkahi prosedur konstitusional demokratis demi memaksakan agenda Brexit – sebuah langkah yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Di Brasil, Bolsonaro memenuhi pemerintahannya dengan tokoh-tokoh militer, termasuk jenderal aktif dan komandan militer lainnya. Ia bahkan mengancam akan meminta militer menghitung suara secara terpisah dalam pemilu presiden 2022, dengan dalih adanya keberpihakan di kalangan hakim dan lembaga pemilu.
Di sisi lain, Trump menyerang para jurnalis yang tidak disukainya, mencabut izin pers mereka, dan secara terbuka menyerukan amandemen bahkan pembalikan Konstitusi AS. Seperti Bolsonaro, Trump juga dituduh berupaya memanipulasi hasil pemilu.
Jelas bahwa ketiga sosok ini bukanlah penganut demokrasi borjuis klasik. Bolsonaro memandang masa kediktatoran militer Brasil dengan penuh nostalgia, sementara Trump terang-terangan mengagumi rezim Bonapartis Putin. Namun, satu orang tidak membentuk sebuah rezim.
Terlepas dari kebencian mereka terhadap norma-norma demokrasi borjuis, Johnson, Trump, dan Bolsonaro tetap beroperasi di dalam batasan-batasan tersebut. Tidak satu pun dari mereka yang memerintah dengan pedang.
Saat Louis Bonaparte menghadapi kemungkinan kehilangan kursi presiden Republik Kedua Prancis melalui jalur konstitusional, ia melancarkan kudeta militer, setelah terlebih dahulu mengamankan kesetiaan kepala staf dan sebagian besar jajaran militer.
Sebaliknya, ketika menghadapi masalah serupa, Bolsonaro dan Trump justru mengerahkan massa bersenjata dari para pendukung fanatik mereka untuk menyerbu gedung-gedung pemerintahan. Namun dalam kedua kasus tersebut, mereka dengan cepat dan tegas dihentikan oleh angkatan bersenjata negara, yang tetap berada di bawah kendali kelas penguasa.
Kelemahan ‘upaya-upaya kudeta’ ini memperlihatkan betapa kecilnya kemampuan Trump dan Bolsonaro untuk mengandalkan kekuatan kekerasan yang terorganisir, meskipun mereka sangat menginginkannya. Dalam kasus Trump, bahkan diragukan apakah ia benar-benar berharap gerombolan pendukungnya berhasil mencapai Capitol. Para ‘pemberontak’ itu sendiri tampak tidak tahu harus berbuat apa, sekadar berkeliaran, merusak mesin penjual makanan, dan berfoto-foto.
Menyebut suatu rezim sebagai Bonapartis berarti menganggapnya sebagai kediktatoran, meskipun dengan tingkat kekerasan yang bervariasi. Jelas, hal ini tidak berlaku untuk rezim Trump, Bolsonaro, maupun Johnson. Tidak ada pula peluang bagi mereka untuk membangun rezim semacam itu selama masa jabatan mereka. Dan inilah hal penting yang gagal disadari – atau sengaja diabaikan – oleh Rachman: perimbangan kekuatan kelas di negara-negara tersebut.
Perspektif akan Bonapartisme Hari Ini
Gideon Rachman mengatakan bahwa kita tengah hidup di “Era Para Penguasa Kuat,” dan menggambarkan dunia di mana seolah-olah satu per satu negara jatuh ke tangan para pemimpin Bonapartis yang mengancam akan memusnahkan demokrasi liberal untuk selamanya.
Pandangan ini sering diulang-ulang oleh banyak komentator yang mengaku dari “kiri”. Namun, sekadar melabeli setiap pemerintahan yang tidak kita sukai sebagai “otoriter” atau bahkan “fasis” adalah tindakan yang ceroboh dan malas. Lebih dari itu, kemalasan ini melahirkan pesimisme – ciri khas mereka yang tidak memahami peran dan kekuatan kelas buruh. Pesimisme dan kecerobohan seperti ini tidak memberikan kontribusi apapun dalam menganalisis karakter berbagai rezim yang berbeda-beda. Dan tanpa memahaminya, tidak ada harapan untuk bisa menggulingkannya.
Faktanya, karakter utama zaman ini, dalam skala global, adalah pergulatan antara revolusi dan kontra-revolusi, dengan perjuangan kelas yang semakin memanas.
Perjuangan kelas semakin menajam karena krisis kapitalisme yang tidak ada preseden ini. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, pada Oktober 2022 mengatakan bahwa periode kestabilan relatif, suku bunga rendah, dan inflasi terkendali sebelumnya telah berakhir, digantikan oleh periode di mana “setiap negara bisa tergelincir dari jalurnya dengan lebih mudah dan lebih sering.”
Ia juga menambahkan hal yang cukup penting: “Kita sedang mengalami pergeseran mendasar dalam ekonomi global, dari dunia yang relatif dapat diprediksi … menuju dunia yang jauh lebih rapuh – dengan ketidakpastian yang lebih besar, volatilitas ekonomi yang lebih tinggi, konfrontasi geopolitik yang semakin tajam, serta bencana alam yang lebih sering dan lebih menghancurkan.”
Kedalaman krisis ini telah menimbulkan ketidakstabilan besar di seluruh lapisan masyarakat. Rezim demokrasi liberal kini menghadapi krisis, akibat polarisasi di kalangan massa dan perpecahan di dalam kelas penguasa sendiri. Fenomena inilah – bukan semata-mata ‘otoritarianisme’ – yang menjelaskan munculnya pemerintahan-pemerintahan yang tidak stabil dan tidak dapat diandalkan, seperti pemerintahan Johnson dan Trump. Ini bukan pertanda masyarakat pasti jatuh ke dalam kekuasaan Bonapartis, melainkan menunjukkan lemahnya kelas penguasa dan rezim mereka.
Di saat yang sama, krisis ini juga memicu gelombang perjuangan kelas yang tajam di berbagai negara. Di banyak belahan dunia, kelas buruh masih belum dikalahkan dan siap bertarung.
Bahkan di negara-negara dengan rezim Bonapartis yang telah lama berkuasa, seperti Iran, kita tidak melihat diktator baru yang berkuasa atas kelas buruh yang tunduk dan kalah. Sebaliknya, rezim Iran muncul dari kekalahan Revolusi 1979, dan kini kelas buruh Iran jelas telah bangkit kembali.
Gerakan massa yang meledak di akhir 2022 di Iran, yang dipicu oleh pembunuhan Mahsa Amini oleh polisi moral, mengguncang fondasi rezim Iran. Ini hanyalah gempa terbaru dari serangkaian letusan sosial yang sejak 2018 terus menggoyahkan rezim Bonapartis reaksioner di negara itu.
Sementara itu di Rusia, popularitas Putin telah terguncang akibat krisis ekonomi yang berlarut sejak 2015, hingga akhirnya rezim berhenti mempublikasikan hasil survei dukungan publik. Dalam kondisi ini, Putin memperketat represi dan memanfaatkan perang di Ukraina untuk mencoba menggalang dukungan rakyat. Semua ini bukanlah ciri rezim yang stabil yang berkuasa atas kelas buruh yang kelelahan, melainkan tanda-tanda bahwa landasan kekuasaan mereka mulai rapuh, membuka jalan bagi perjuangan kelas yang lebih hebat di masa depan.
Konsentrasi kekuasaan di tangan Xi Jinping di China juga mencerminkan ketidakstabilan mendasar dalam rezim Partai Komunis China (PKC), yang semakin kehilangan keyakinan bahwa mereka dapat mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara lama.
Di semua negara, hambatan utama bagi revolusi bukanlah kekuatan luar biasa para “pemimpin kuat”, melainkan kelemahan dan kepengecutan kepemimpinan kelas buruh itu sendiri.
Saat ini, di mana-mana kelas penguasa berusaha memperkuat aparatus represinya untuk menghadapi kemarahan massa. Ini menunjukkan bahwa semua negara kapitalis – entah itu rejim diktator atau demokratis – harus mempertahankan sistem kapitalisme. Dan kini, semua rezim di dunia berdiri di atas pondasi yang jauh lebih rapuh dibandingkan masa lalu. Namun, di negara-negara kapitalis maju, kelas penguasa sangat berhati-hati untuk tidak tergelincir ke dalam pemerintahan berbasis kekerasan terbuka, karena mereka tahu itu justru bisa memicu perlawanan besar dari rakyat pekerja. Perwakilan kapitalis yang paling waras memahami bahwa langkah semacam itu malah bisa mempercepat datangnya revolusi.
Namun, perspektif ini tidak seharusnya membuat kita lengah. Dalam situasi krisis kapitalis yang ekstrem di satu sisi, dan ketiadaan kepemimpinan revolusioner dalam gerakan buruh di sisi lain, berbagai kemungkinan bisa muncul. Jika kelas penguasa gagal menstabilkan kekuasaannya, sementara kelas buruh belum mampu merebut kekuasaan untuk mengakhiri krisis dengan jalan sosialisme, bisa saja kekuasaan eksekutif mengangkat dirinya di atas masyarakat secara Bonapartis.
Leon Trotsky pernah menganalisis rezim di masa antar-perang di Prancis dan Jerman, dan menggambarkannya dengan cara ini. Ia menjelaskan, misalnya, bahwa pemerintahan Doumergue di Prancis yang terbentuk pada 1934 sebagai “Pemerintahan Persatuan Nasional” dan memerintah di luar kontrol parlemen, adalah sebuah bentuk kekuasaan Bonapartis. Seperti kata Trotsky: “Kubu kontra-revolusi yang menyerang dan kubu revolusi yang bertahan relatif ada dalam posisi seimbang, dan mereka saling menyeimbangkan; berkat keseimbangan relatif ini sebuah poros kekuasaan mengangkat dirinya di atas kelas-kelas dan di atas perwakilan parlementer mereka.” (Trotsky, Bonapartisme dan Fasisme, Juli 1934)
Jika kekuasaan Napoleon sebelumnya bertumpu pada kelelahan kedua kelas, maka “keseimbangan relatif” yang menopang pemerintahan Doumergue di Prancis justru lahir dari antisipasi akan revolusi di tengah krisis kapitalisme yang mendalam. Pada kenyataannya, badai ekonomi, sosial, dan politik yang melanda rezim tersebut akhirnya menumbangkannya hanya dalam sembilan bulan, di tengah gelombang pemogokan umum dan ancaman perang saudara.
Saat ini, bangkitnya rezim stabil – baik dalam bentuk demokrasi liberal maupun Bonapartis – tidak ada di agenda. Justru ketidakstabilan dan krisis yang semakin menguat di mana-mana.
Martin Wolf, Kepala Komentator Ekonomi Financial Times Inggris, mencatat meningkatnya jumlah negara yang disebut anocracies oleh Polity IV, yaitu negara-negara dengan pemerintahan yang tidak konsisten, tidak stabil, dan tidak efektif. Ia menunjukkan bahwa jumlah anocracies melonjak dari 21 negara pada 1984 menjadi 39 pada 1989, dan kemudian 49 pada 2016.
Rezim-rezim Bonapartis muncul dengan menyeimbangkan kelas-kelas utama yang bertikai ketika ada semacam keseimbangan dalam perjuangan kelas. Namun, di periode ke depan, keseimbangan semacam itu kemungkinan besar akan sangat rapuh. Jika gejolak perjuangan kelas menghasilkan rezim-rezim dengan ciri-ciri Bonapartis, mereka cenderung tidak bertahan lama dan sangat rentan. Seperti yang pernah dikatakan Trotsky: “Bonapartisme tidak akan mencapai kestabilan selama kamp revolusi dan kamp kontra-revolusi belum mengukur kekuatan mereka dalam pertempuran.” (Trotsky, Before the Decision, Feb 1933)
Perlu juga ditekankan bahwa pada 1930-an, bahkan negara-negara kapitalis kuat seperti Prancis dan Jerman masih memiliki populasi petani yang besar. Saat ini, di sebagian besar dunia, perimbangan kekuatan kelas jauh lebih menguntungkan kelas buruh.
Secara jumlah, tak pernah sebelumnya ada sebanyak ini kaum buruh di dunia seperti hari ini, akibat proletarisasi kaum tani dan kelas menengah kecil di banyak negara. Menurut data Bank Dunia, misalnya, 56 persen populasi dunia – sekitar 4,4 miliar orang – kini tinggal di wilayah perkotaan, dan mayoritas besar dari mereka adalah kaum buruh. Basis sosial yang dulu menopang reaksi dan Bonapartisme – seperti di masa Napoleon – telah tergerus.
Di negara-negara kapitalis maju, kelas petani bahkan sudah sepenuhnya lenyap. Hal ini membuat upaya mendirikan rezim Bonapartis, bahkan dalam bentuk yang paling rapuh sekalipun, menjadi jauh lebih sulit. Kita sedang memasuki periode panjang revolusi dan kontra-revolusi, di mana kelas buruh akan memiliki beberapa kesempatan untuk merebut kekuasaan.
Bagaimana Melawan Bonapartisme
Meski begitu, keinginan untuk melawan setiap kecenderungan otoritarian adalah naluri sehat yang dimiliki banyak pekerja dan anak muda. Pertanyaannya adalah: bagaimana kelas buruh bisa membela dan memenangkan hak-hak demokratis?
Ada sebagian kelompok yang mengaku ‘kiri’ yang berharap bisa melindungi demokrasi dengan membentuk aliansi bersama kaum liberal borjuis. Kaum liberal, seperti Gideon Rachman, mengaku menolak kekuasaan pedang. Mereka lebih memilih lembaga-lembaga demokrasi liberal, yang mereka anggap sebagai cara terbaik untuk menjaga kepemilikan pribadi dan kepentingan borjuasi. Karena itu, beberapa organisasi dan komentator kiri berkesimpulan bahwa kita harus membangun ‘front persatuan’ seluas mungkin untuk melawan kecenderungan ‘otoritarian’ atau bahkan ‘fasis’ dari tokoh-tokoh seperti Trump, Bolsonaro, Johnson, dan lainnya.
Namun justru pemerintahan borjuis liberal inilah yang telah melahirkan pemerintahan populis tersebut. Kaum Liberal-lah yang menerapkan program penghematan dan menerapkan undang-undang anti-serikat buruh. Sejarah pun berulang kali menunjukkan bahwa, ketika kapitalisme terancam oleh revolusi, kaum liberal borjuis akan lebih memilih bersekutu dengan calon diktator yang berjanji menjaga tatanan kapitalis, ketimbang menyerahkan kekuasaan kepada kaum buruh. Contohnya, majalah The Economist yang terkenal ‘cinta kebebasan’ pernah mendukung berdirinya kediktatoran brutal Pinochet di Chile.
Marx mengupas hal ini dengan tajam dalam The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. Ia menunjukkan bagaimana, di tengah gelombang perjuangan kelas buruh, kaum liberal borjuis perlahan menyerahkan lebih banyak kekuasaan kepada Louis Bonaparte atas nama ‘pemulihan ketertiban’.
Marx merangkum proses itu dengan menulis: “Dengan sorak-sorai borjuasi industri menyambut kudeta 2 Desember, penghancuran parlemen, kejatuhan kekuasaan mereka sendiri, dan lahirnya kediktatoran Bonaparte.”
Pelajaran penting dari ini semua adalah bahwa Bonapartisme tidak bisa dilawan dengan demokrasi liberal.
Pendekatan Marxis, ketika perjuangan kelas memasuki kondisi keseimbangan rapuh dan bergolak, adalah mendorong resolusi keseimbangan itu ke arah kelas buruh. Dengan menghancurkan keadaan keseimbangan tersebut, kita mencegah seorang Bonapartis untuk menyeimbangkan kelas-kelas yang bertarung dan mengangkat dirinya di atas perjuangan dengan kekuatan pedang.
Inilah yang terjadi di Rusia antara Februari hingga Oktober 1917. Rezim Kerensky, yang berkuasa setelah Revolusi Februari menggulingkan Tsar, berusaha menjadi rejim Bonapartis.
Saat itu, kaum buruh mulai bergerak, tetapi para pemimpin mereka di Soviet masih lemah dan enggan merebut kekuasaan untuk kelas buruh. Di sisi lain, borjuasi juga terlalu lemah untuk mempertahankan kekuasaan sendiri.
Kerensky memberi janji-janji muluk pada kedua belah pihak, bermanuver di antara mereka, dan mencoba bergantung pada dukungan tentara. Alih-alih ikut terjebak dalam manuver ini, atau bergantung pada kepemimpinan liberal seperti yang dilakukan kaum Menshevik, Lenin, Trotsky, dan Bolshevik memilih membangun posisi independen kelas buruh – yang dirangkum dalam slogan: “Semua kekuasaan untuk Soviet!”
Lenin pada waktu itu menjelaskan: “Kabinet Kerensky jelas merupakan kabinet yang mulai melangkah ke arah Bonapartisme.” Ia menegaskan bahwa “adalah kebodohan filistinisme bila masih memelihara ilusi terhadap konstitusi,” dan justru menekankan pentingnya “memulai perjuangan nyata dan gigih untuk menggulingkan Bonapartisme, perjuangan politik skala-besar yang berdasarkan kepentingan kelas.” (Lenin, The Beginning of Bonapartism, 29 Juli 1917.)
Pendekatan proletariat yang tegas dan independen inilah yang akhirnya mengakhiri keseimbangan rapuh tersebut, mengarahkannya ke kemenangan buruh, dan menggagalkan upaya Kerensky – atau calon diktator lainnya – untuk membangun rezim Bonapartis.
Bonapartisme hanya bisa dilawan lewat perjuangan mandiri kelas buruh untuk merebut kekuasaan, bukan melalui kolaborasi kelas. Tragedi mengerikan yang tengah berlangsung di Sudan saat artikel ini ditulis memberikan peringatan keras tentang hal ini.
Ini adalah pelajaran penting bagi kaum buruh di mana pun. Di Rusia atau China, misalnya, kaum Marxis tidak memiliki kesamaan dengan kaum liberal borjuis yang terus meratapi ketiadaan demokrasi borjuis. Kita juga menolak politik kolaborasi kelas yang hanya akan menyeret buruh tunduk pada kaum liberal borjuis.
Yang kita perjuangkan adalah perlawanan terhadap rezim-rezim ini yang bertumpu pada metode revolusioner dan kekuatan massa, dipimpin oleh kelas proletariat. Di bawah rezim Bonapartis, perjuangan semacam ini bisa saja mengangkat tuntutan dan slogan-slogan demokratis, namun kita harus selalu menegaskan bahwa hak-hak ini hanya bisa diperoleh melalui kekuatan kelas buruh.
Kebijakan proletariat independen inilah yang menjadi poros pembangunan partai revolusioner. Tugas terpenting kaum Marxis adalah mengembangkan kebijakan ini dan membangun wadah politik, dalam bentuk partai revolusioner, untuk membawanya ke tengah-tengah gerakan buruh. Hanya dengan jalan ini perjuangan kita melawan Bonapartisme, kapitalisme, dan masyarakat kelas bisa meraih kemenangan.