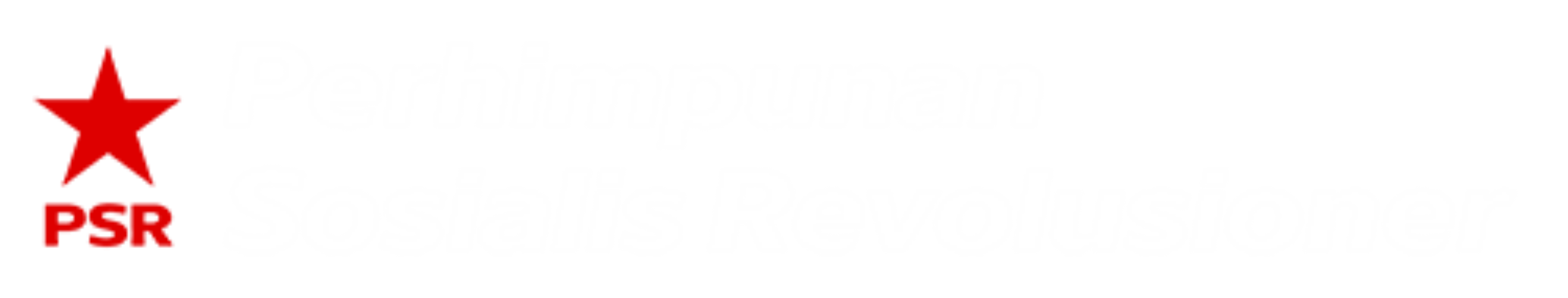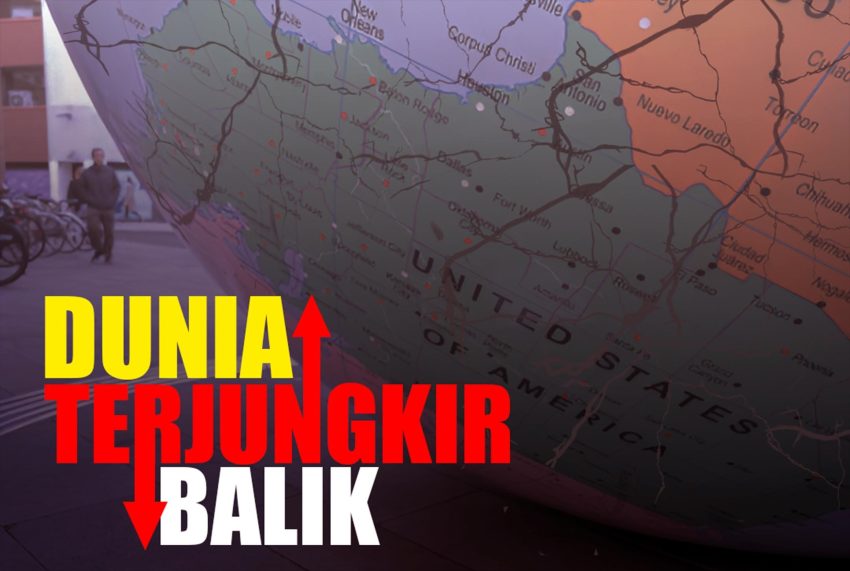Kita sedang hidup melalui masa yang penuh dengan gejolak dan perubahan tajam dalam situasi dunia. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, beserta kebijakan-kebijakannya, telah membawa ketidakstabilan yang luar biasa besar dalam politik dunia, ekonomi dunia, dan hubungan antarnegara besar.
Trump bukanlah penyebab dari seluruh kekacauan ini, yang merupakan hasil dari krisis kapitalisme. Namun, tindakannya jelas telah mempercepat proses tersebut secara drastis. Kontradiksi-kontradiksi yang selama ini telah mengumpul di bawah permukaan akhirnya meledak dengan tiba-tiba dan mengguncang seluruh tatanan yang ada. Apa-yang-disebut tatanan dunia liberal, yang telah eksis selama puluhan tahun, kini runtuh di depan mata kita.
Untuk menganalisis situasi dunia, kita harus mulai dari hal-hal yang fundamental. Kapitalisme adalah sistem yang telah lama melampaui peran historisnya. Dalam periode pembusukannya, sistem ini melahirkan perang, krisis, dan kerusakan lingkungan, yang dalam jangka panjang mengancam keberlangsungan hidup di bumi. Dokumen ini bertujuan menjabarkan fitur-fitur utama krisis ini dan menegaskan pentingnya membangun sebuah organisasi revolusioner yang mampu menggulingkannya, satu-satunya jalan untuk menjamin masa depan umat manusia.
Dalam analisa terakhir, akar dari krisis ini adalah ketidakmampuan sistem kapitalisme untuk mengembangkan kekuatan produktif. Pertumbuhan ekonomi terhambat oleh batas-batas negara-bangsa dan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Selama puluhan tahun, kaum kapitalis telah mencoba berbagai cara untuk mengatasi hambatan ini: mulai dari memperbesar likuiditas hingga memperluas perdagangan dunia, dan seterusnya. Namun kini, semua upaya itu justru berbalik arah dan menjadi sumber masalah baru.
Terpilihnya Trump
Terpilihnya Donald Trump pada November 2024 menandai pergeseran politik yang signifikan dan manifestasi krisis legitimasi dalam demokrasi borjuis, tidak hanya di AS, tetapi juga di semua negara lainnya. Meskipun lapisan utama kelas penguasa AS telah berupaya keras untuk menggagalkan kemenangannya, Trump justru berhasil meraih kemenangan yang meyakinkan.
Hasil pilpres ini telah banyak ditafsirkan, terutama oleh komentator liberal, media arus utama, dan sebagian kalangan ‘kiri’, sebagai tanda pergeseran politik ke kanan, baik di AS maupun secara global.
‘Penjelasan’ semacam itu dangkal dan menyesatkan. Lebih dari itu, pandangan tersebut mendorong kita pada kesimpulan yang sangat berbahaya. Misalnya, anggapan bahwa Joe Biden dan Partai Demokrat merupakan pilihan alternatif yang lebih progresif dan ‘demokratis’, padahal kenyataannya sama sekali tidak mencerminkan hal tersebut.
Pemerintahan Biden sepenuhnya reaksioner, yang terutama terlihat jelas dalam kebijakan luar negerinya. Kita bisa ingat bagaimana ‘Genocide Joe’ memberi dukungan penuh kepada Netanyahu untuk meluncurkan pembantaian massal terhadap rakyat Palestina di Gaza. Ia juga memimpin kampanye represi yang brutal terhadap mahasiswa dan siapa pun yang berani menentang kebijakan reaksioner tersebut.
Demikian juga dalam kasus Ukraina, Biden bertanggung jawab memprovokasi konflik yang telah mengakibatkan pertumpahan darah, menggelontorkan miliaran dolar dalam bentuk dana dan bantuan militer untuk rezim reaksioner di Kiev, serta menjalankan kebijakan provokatif terhadap Rusia.
Dalam kampanye pemilihannya, Trump memosisikan dirinya sebagai ‘kandidat perdamaian’, berlawanan dengan kebijakan perang dari kelompok Biden. Perbedaan ini memiliki pengaruh besar, terutama di dapil-dapil yang didominasi oleh komunitas Muslim dan Arab.
Memang benar ada selapisan elemen reaksioner yang mendukung Trump, namun faktor ini saja tidak cukup menjelaskan betapa besarnya dukungan yang ia peroleh dan bagaimana jumlah suaranya meningkat di hampir semua kelompok demografis, bahkan di antara kelas pekerja kulit hitam dan Latino. Kenyataannya, di sejumlah negara bagian di mana Trump menang telak atau meningkatkan perolehan suaranya, para pemilih di saat yang sama juga mendukung inisiatif progresif seperti perlindungan hak aborsi atau kenaikan upah minimum.
Faktor kunci di balik kemenangan Trump terletak pada kemampuannya menangkap, menyuarakan, dan memobilisasi sentimen anti-kemapanan yang luas dan mengakar kuat dalam masyarakat Amerika.
Contoh mencolok dari fenomena ini terlihat dalam reaksi publik terhadap Luigi Mangione yang dituduh membunuh CEO United Healthcare. Meski tindakannya mengejutkan, justru respons publik menunjukkan simpati kepada terduga pelaku ketimbang korban. Mangione bahkan dipandang oleh banyak orang sebagai semacam pahlawan rakyat. Menariknya, reaksi ini tidak hanya datang dari kalangan kiri, tetapi juga dari sebagian kaum konservatif dan pemilih Partai Republikan, termasuk pendukung Trump.
Situasi ini menghadirkan sebuah paradoks. Meskipun Trump adalah seorang miliarder yang dikelilingi oleh para miliarder lainnya, ia berhasil memosisikan dirinya sebagai corong suara kemarahan anti-status-quo. Kontradiksi ini menunjukkan tidak koheren dan terdistorsinya mood politik saat ini. Namun demikian, ini mencerminkan ketidakpuasan yang sejati dan luas terhadap institusi-institusi arus utama: terhadap bisnis besar, elite politik, dan seluruh aparatur negara.
Akar dari kemarahan anti-kemapanan ini terletak pada krisis kapitalisme. Sejak krisis 2008, di mana sistem kapitalisme belum sepenuhnya pulih darinya, kegeraman ini telah mencapai proporsi yang masif. Kita tidak sedang melalui siklus krisis kapitalisme seperti biasanya, tetapi krisis organik kapitalisme. Dukungan terhadap demokrasi borjuis di negara-negara kapitalis maju selama puluhan tahun bertumpu pada keyakinan bahwa kapitalisme mampu memenuhi kebutuhan dasar kelas buruh (layanan kesehatan, pendidikan, pensiun, dll.) serta harapan bahwa taraf hidup setiap generasi akan lebih baik dari generasi sebelumnya, bahkan bila hanya sedikit lebih baik saja.
Kini, harapan itu telah runtuh. Di AS pada 1970, lebih dari 90 persen orang berusia 30 tahun memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan orang tua mereka pada usia yang sama. Namun pada 2010, angka ini merosot menjadi 50 persen. Dan pada 2017, hanya 37 persen warga Amerika yang masih percaya bahwa anak-anak mereka kelak akan hidup lebih sejahtera daripada mereka sendiri.
Menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja, sejak awal 1980-an upah riil buruh Amerika entah stagnan atau menurun, terutama karena banyak pekerjaan yang di-outsource ke luar negeri. Hal serupa disampaikan oleh Economic Policy Institute, yang mencatat bahwa upah rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah nyaris tak tumbuh sejak akhir 1970-an, sementara biaya hidup terus melonjak tanpa henti.
Di saat yang sama, kesenjangan kekayaan menjadi semakin tak masuk akal. Di satu sisi, segelintir miliarder terus menumpuk kekayaan. Di sisi lain, semakin banyak pekerja yang kesulitan mencukupi kebutuhan hidup mereka. Mereka dihadapkan pada pemangkasan anggaran publik, daya beli upah yang tergerus inflasi, tagihan energi yang melonjak, krisis perumahan, dan berbagai beban lainnya.
Media, politisi, partai-partai status-quo, parlemen, hingga lembaga peradilan, semuanya dipandang, dan dengan alasan yang tepat, sebagai perwakilan segelintir elite yang berprivilese. Mereka membuat keputusan demi menjaga kepentingan sempit dan egois mereka sendiri, alih-alih memenuhi kebutuhan rakyat banyak.
Krisis 2008 disusul oleh gelombang pemangkasan anggaran yang brutal di berbagai negara. Semua pencapaian sosial yang telah diraih di masa lalu diserang. Rakyat menyaksikan penurunan dalam taraf hidup mereka, sementara bank-bank diselamatkan dengan dana publik. Dari situ, muncul kemarahan besar, gerakan protes massal, dan, yang terpenting, krisis legitimasi tanpa-preseden terhadap seluruh institusi borjuis.
Pada awalnya, gelombang kemarahan ini, yang tersalurkan dalam gerakan massa anti-pemangkasan sekitar tahun 2011, menemukan ekspresinya di sayap kiri. Muncul tokoh-tokoh dan partai-partai kiri anti-kemapanan di Eropa dan Amerika Serikat: Podemos, Syriza, Jeremy Corbyn, Bernie Sanders, dan lainnya. Namun pada akhirnya, masing-masing gerakan ini mengkhianati harapan yang telah mereka bangun. Keterbatasan politik reformis yang dianut para pemimpinnya pun terekspos.
Kegagalan total para pemimpin kiri inilah yang membuka jalan bagi bangkitnya para demagog reaksioner seperti Trump.
Proses serupa tengah berlangsung di sebagian besar negara kapitalis maju: krisis kapitalisme, serangan terhadap kelas pekerja, kebangkrutan kaum ‘kiri’, dan kemunculan para demagog sayap kanan yang menunggangi gelombang sentimen anti-kemapanan.
Bahaya fasisme atau Bonapartisme?
Bahkan sebelum Trump terpilih, media borjuis dan kaum Kiri sudah ramai-ramai melancarkan kampanye untuk mengutuknya sebagai seorang fasis.
Marxisme adalah sebuah ilmu. Seperti halnya ilmu-ilmu lainnya, ia memiliki terminologi ilmiah. Kata seperti ‘fasisme’ bagi kami memiliki makna yang tegas dan spesifik—bukan sekadar umpatan atau label yang bisa sembarangan ditempelkan kepada siapa pun yang tidak kita sukai.
Mari kita mulai dengan definisi yang tepat tentang fasisme. Dalam pengertian Marxis, fasisme adalah gerakan kontra-revolusioner—sebuah gerakan massa yang terutama terdiri dari kaum lumpen proletar dan borjuis kecil yang marah. Fasisme digunakan sebagai alat pemukul untuk menghancurkan dan memecah belah kelas pekerja, serta mendirikan negara totaliter di mana borjuasi menyerahkan kekuasaan negara kepada birokrasi fasis.
Ciri utama negara fasis adalah sentralisasi ekstrem dan kekuasaan negara yang absolut, di mana bank-bank dan monopoli besar tetap dilindungi, tetapi berada di bawah kendali pusat yang kuat oleh birokrasi fasis yang besar dan berkuasa. Dalam What is National Socialism?, Trotsky menjelaskan:
“Fasisme Jerman, seperti halnya fasisme Italia, naik ke tampuk kekuasaan dengan menunggangi borjuasi kecil, yang dijadikannya alat pemukul untuk menghancurkan organisasi kelas buruh dan lembaga-lembaga demokrasi. Namun, fasisme yang telah berkuasa sama sekali bukanlah pemerintahan borjuasi kecil. Sebaliknya, ia adalah kediktatoran kapital monopoli yang paling kejam.”
Secara umum, itulah ciri-ciri utama fasisme. Lalu bagaimana ini dibandingkan dengan ideologi dan isi dari fenomena Trump? Kita sudah pernah mengalami satu periode pemerintahan Trump, yang—menurut peringatan keras Partai Demokrat dan seluruh kalangan liberal—katanya akan segera menghapus demokrasi. Namun hal itu tak pernah terjadi.
Tak ada kebijakan besar yang diambil untuk membatasi hak mogok atau hak berdemonstrasi, apalagi sampai membubarkan serikat buruh. Pemilu tetap diselenggarakan seperti biasa, dan pada akhirnya—meskipun diwarnai kekisruhan—Trump digantikan oleh Joe Biden melalui pemilu. Apa pun pendapat orang mengenai pemerintahan Trump yang pertama, itu sama sekali tak mencerminkan bentuk apa pun dari fasisme.
Selain itu, perimbangan kekuatan kelas telah berubah secara signifikan sejak 1930-an. Di negara-negara kapitalis maju, kaum tani—yang dulu merupakan bagian besar dari populasi—telah tereduksi menjadi sangat kecil, dan profesi-profesi yang sebelumnya dianggap sebagai ‘kelas menengah’ (pegawai negeri, dokter, guru) telah mengalami proletarianisasi, dengan banyak dari mereka bergabung ke dalam serikat buruh dan melakukan pemogokan. Bobot sosial kelas buruh justru menguat secara luar biasa seiring perkembangan kekuatan produktif dalam boom ekonomi besar setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua.
Ideologi Trumpisme—sejauh dapat dikatakan ada ideologi semacam itu—sangat jauh dari fasisme. Alih-alih menginginkan negara yang kuat, cita-cita Donald Trump adalah kapitalisme pasar bebas, di mana negara berperan sangat sedikit atau bahkan tidak berperan sama sekali (dengan pengecualian tarif proteksionis).
Ada juga yang menyebut bahwa Trump mewakili rezim Bonapartis. Intinya, ini kembali pada upaya menggambarkan Trump sebagai diktator yang berniat menumpas kelas buruh. Namun pelabelan semacam ini tidak menjelaskan apa-apa. Kenyataannya, alih-alih berusaha meremukkan kelas buruh, Trump justru berusaha memenangkan dukungan mereka secara demagogis dan berusaha menenangkan mereka. Tentu saja, sebagai politisi borjuis, ia tetap mewakili kepentingan yang secara fundamental bertentangan dengan kepentingan buruh. Tapi itu tidak menjadikannya seorang diktator.
Kita bisa saja menunjuk pada elemen ini atau itu dalam situasi saat ini yang bisa disebut sebagai elemen Bonapartisme. Mungkin benar demikian. Namun hal serupa juga bisa dikatakan tentang hampir semua rezim demokrasi borjuis belakangan ini.
Hanya karena suatu hal mengandung beberapa elemen dari sebuah fenomena, tidak berarti fenomena itu benar-benar telah muncul sepenuhnya. Memang bisa dikatakan bahwa ada elemen Bonapartisme dalam Trumpisme. Namun itu sangat berbeda dengan mengatakan bahwa rezim Bonapartis benar-benar ada di Amerika Serikat.
Masalahnya, istilah ‘Bonapartisme’ sangat lentur maknanya. Ia mencakup banyak hal, mulai dari konsep klasik Bonapartisme, yang pada dasarnya berarti kekuasaan pedang. Pendekatan semacam ini tidak berguna untuk menganalisis pemerintahan Trump saat ini di Washington, yang meskipun memiliki banyak keunikan, tetap merupakan sebuah demokrasi borjuis. Tugas kita bukan memberi label, melainkan mengikuti proses yang terjadi dan memahami aspek-aspek esensialnya.
Pergeseran tektonik dalam hubungan dunia
Kebijakan luar negeri Trump menandai perubahan besar dalam hubungan dunia dan berakhirnya tatanan dunia liberal yang telah eksis selama 80 tahun sejak Perang Dunia Kedua. Ini adalah pengakuan atas kemunduran relatif imperialisme AS dan munculnya kekuatan-kekuatan imperialis saingan, yakni Rusia dan terutama Cina, yang kini menjadi saingan utama di panggung dunia.
Di akhir Perang Dunia Kedua, AS muncul sebagai kekuatan yang sangat dominan. Dengan Eropa dan Jepang hancur akibat perang, Amerika menyumbang 50 persen dari PDB dunia dan 60 persen dari total produksi industri global. Satu-satunya saingan seriusnya di panggung dunia saat itu adalah Uni Soviet, yang juga tampil lebih kuat setelah mengalahkan Nazi Jerman dan bergerak maju melintasi benua Eropa.
Revolusi Cina semakin memperkuat blok Stalinis. AS berupaya membangun kembali Eropa Barat dan Jepang sebagai langkah untuk membendung ‘kemajuan Komunisme’. Birokrasi Soviet tidak tertarik pada revolusi dunia dan cukup siap mencapai kesepakatan dengan Washington, yang tercermin dalam kebijakan ‘koeksistensi damai’.
Setelah itu, ada periode keseimbangan relatif antara AS dan Uni Soviet, dua kekuatan nuklir, yang dikenal sebagai Perang Dingin. Di atas basis dominasi Amerika, dibentuklah serangkaian lembaga multilateral formal untuk mengatur hubungan internasional (Perserikatan Bangsa-bangsa) dan perekonomian dunia (IMF dan Bank Dunia yang dibentuk dalam Konferensi Bretton Woods). Keseimbangan ini diperkuat oleh boom ekonomi pasca-perang, yaitu masa perkembangan luar biasa kekuatan produktif dan pasar dunia.
Periode ini berlangsung hingga runtuhnya Stalinisme pada 1989–1991 dan pemulihan kapitalisme di Rusia dan Cina. Peristiwa itu menghasilkan satu lagi perubahan besar dalam situasi dunia. AS muncul sebagai kekuatan imperialis dominan tanpa ada yang bisa menyainginya.
Perang imperialis pada 1991 terhadap Irak diluncurkan di bawah naungan PBB, di mana Rusia mendukung mosi tersebut dan Cina memilih untuk hanya abstain. Tampaknya tak ada perlawanan terhadap dominasi imperialisme AS. Dari sisi ekonomi, Washington terus mendorong globalisasi dan ‘neoliberalisme’: yakni integrasi lebih jauh pasar dunia di bawah kendali imperialisme AS, serta pengurangan peran negara.
Periode dominasi mutlak imperialisme AS perlahan-lahan terkikis selama 35 tahun terakhir, hingga akhirnya muncul situasi yang benar-benar baru.
Didorong oleh arogansi yang luar biasa, AS melancarkan invasi ke Irak dan Afghanistan. Namun, di sinilah sejarah mulai berbalik arah. Amerika terjebak dalam perang yang tak bisa dimenangkan selama 15 tahun, dengan kerugian besar baik dari segi biaya maupun nyawa. Pada Agustus 2021, mereka terpaksa mundur secara memalukan dari Afghanistan
Pengalaman-pengalaman ini membuat publik AS enggan mendukung petualangan militer di luar negeri, sementara kelas penguasa Amerika menjadi sangat berhati-hati untuk mengerahkan pasukan darat ke luar negeri. Seiring bangkitnya kekuatan-kekuatan regional dan global baru, perimbangan kekuatan dunia mulai bergeser. Namun, imperialisme AS tidak belajar dari pengalaman tersebut. Ia menolak mengakui perimbangan kekuatan yang baru ini dan justru berupaya mempertahankan dominasinya, yang membuatnya terseret ke dalam serangkaian konflik yang tidak bisa dimenangkannya.
Dunia multipolar?
Situasi dunia saat ini didominasi oleh ketidakstabilan yang luar biasa besar dalam hubungan dunia. Ini merupakan dampak dari persaingan untuk hegemoni dunia antara AS, kekuatan imperialis terkuat namun tengah mengalami kemunduran relatif, dan Cina, kekuatan imperialis yang lebih muda dan dinamis. Kita sedang menyaksikan pergeseran besar, sebanding dengan pergerakan lempeng tektonik di kerak Bumi. Pergeseran seperti ini selalu disertai dengan ledakan-ledakan dalam berbagai bentuk. Perang di Ukraina – yang tengah menuju kekalahan memalukan bagi AS-NATO – dan konflik di Timur Tengah, merupakan cerminan dari kenyataan ini.
Pendekatan Trump terhadap hubungan internasional mencerminkan upaya untuk mengakui bahwa AS tak lagi bisa bertindak sebagai satu-satunya “polisi dunia”. Menurut pandangannya, dan pandangan para penasihat terdekatnya, usaha AS untuk mempertahankan hegemoni dan dominasi total dianggap terlalu mahal, tidak realistis, dan merugikan kepentingan keamanan nasionalnya sendiri.
Ini sama sekali tidak berarti AS berhenti menjadi kekuatan imperialis, atau kebijakan Trump berpihak pada bangsa-bangsa tertindas di dunia. Kenyataannya justru sebaliknya. Kebijakan luar negeri Trump menunjukkan batas yang tegas tentang apa yang dianggap sebagai kepentingan inti keamanan nasional AS, yang dimulai dari kawasan Amerika Utara.
Ketika Trump mengatakan Amerika harus menguasai Terusan Panama dan Greenland, yang ia suarakan adalah kepentingan imperialisme AS. Terusan Panama merupakan jalur perdagangan vital yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Teluk Meksiko, dan menopang 40 persen lalu lintas kontainer milik AS.
Greenland selalu memiliki posisi geo-strategis yang penting. Inilah mengapa AS memiliki pangkalan militer di pulau tersebut. Pemanasan global telah meningkatkan lalu lintas pelayaran antara Samudra Pasifik dan Atlantik melalui Arktik. Es yang mencair berarti akses yang lebih mudah ke dasar laut yang kaya akan cadangan mineral tanah jarang. Pulau itu sendiri menyimpan deposit mineral-mineral penting (mineral tanah jarang, uranium) serta minyak dan gas, dan semuanya kini semakin mudah diakses akibat perubahan iklim. Di sini, AS bersaing dengan Cina dan Rusia dalam memperebutkan jalur perdagangan dan sumber daya tersebut.
Kebijakan luar negeri Trump didasari oleh pengakuan atas keterbatasan kekuatan Amerika Serikat. Konsekuensinya adalah upaya melepaskan diri dari serangkaian konflik yang menguras biaya (seperti di Ukraina dan Timur Tengah) melalui kesepakatan-kesepakatan, demi membangun kembali kekuatannya dan memusatkan perhatiannya pada pesaing utamanya di panggung dunia: Cina.
Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, atau bahkan mungkin sebelumnya, imperialisme AS terus berpura-pura bertindak demi hak asasi manusia, menyebarkan demokrasi dan “tatanan berbasis aturan”, serta membela “prinsip kedaulatan wilayah”, dan seterusnya.
Mereka bertindak melalui lembaga-lembaga internasional ‘multilateral’ yang tampaknya netral dan memberi ruang bagi semua negara untuk bersuara: PBB, WTO, IMF, dan sebagainya. Namun kenyataannya, semua itu hanyalah kedok belaka. Sejak awal, itu adalah sandiwara. Entah kepentingan imperialisme AS tersalur lewat lembaga-lembaga itu, atau mereka akan mengabaikannya sama sekali. Bedanya sekarang, Trump sama sekali tak peduli dengan kepura-puraan semacam itu. Ia tampak bertekad merobek seluruh aturan main dan menyatakan segala sesuatu secara terus terang, apa adanya.
Sebagian orang berpendapat bahwa, dalam menghadapi kekuatan AS yang tak terkendali, gagasan dunia multipolar adalah sesuatu yang progresif, yang memberi ruang kedaulatan lebih besar bagi negara-negara tertindas, sebuah cita-cita yang patut diperjuangkan. Namun kini, kita mulai melihat sekilas seperti apa rupa dunia ‘multipolar’ itu: kekuatan-kekuatan imperialis membagi-bagi dunia ke dalam zona pengaruh, memaksa negara-negara lain untuk tunduk pada satu blok atau blok lainnya.
Kemunduran relatif imperialisme AS
Perlu kita tekankan bahwa saat kita berbicara tentang kemunduran imperialisme AS, yang kita maksud adalah kemunduran secara relatif, yakni kemunduran dibandingkan posisinya sebelumnya sehubungan dengan kekuatan-kekuatan rival lainnya. Amerika Serikat, dalam semua indikator, tetap merupakan kekuatan terbesar dan paling reaksioner di dunia.
Pada 1985, AS menyumbang 36 persen dari total PDB dunia. Namun pada 2024, angkanya menurun menjadi 26 persen. Dalam kurun waktu yang sama, PDB Cina melonjak dari 2,5 persen menjadi 18,5 persen dari total dunia. Sementara itu, Jepang yang sempat mencapai puncaknya di angka 18 persen pada 1995, kini merosot tajam menjadi hanya 5,2 persen.
AS masih mendominasi ekonomi dunia lewat kontrolnya atas pasar keuangan global. Sebesar 58 persen cadangan devisa dunia disimpan dalam bentuk dolar AS (sementara hanya 2 persen dalam renminbi Cina), meskipun angka ini telah menurun dari 73 persen pada 2001. Dolar juga digunakan dalam 58 persen transaksi ekspor dunia. Jika dilihat dari arus keluar Investasi Langsung Luar Negeri (Foreign Direct Investment/FDI), yang menjadi tolak ukur ekspor modal, AS berada di posisi teratas dengan US$454 triliun, disusul oleh Cina (termasuk Hong Kong) dengan US$287 triliun.
Kekuatan ekonomi suatu negara adalah fondasi dari pengaruh internasionalnya, namun pengaruh itu harus ditopang oleh kekuatan militer. Pengeluaran militer AS mencakup 40 persen dari total belanja militer dunia, jauh di atas Cina yang berada di urutan kedua dengan 12 persen, dan Rusia di posisi ketiga dengan 4,5 persen. Amerika menghabiskan anggaran militer lebih besar daripada gabungan sepuluh negara berikutnya.
Kendati demikian, AS tak lagi bisa mengklaim dirinya sebagai penguasa dunia tanpa tandingan. Kekuatan ekonomi Cina yang luar biasa, disertai peningkatan kemampuan militernya, serta keunggulan militer yang diperlihatkan Rusia di medan perang Ukraina, menjadi tantangan besar bagi dominasi AS. Dengan begitu, batas-batas kekuasaan global Amerika kini terlihat dengan gamblang dari berbagai penjuru.
Kemunduran relatif ini menemui ekspresinya secara ekonomi dengan lari keluarnya modal secara parsial dari dolar, sekuritas Treasury AS, dan saham-saham Amerika. Dengan persaingan yang semakin besar yang dihadapi oleh monopoli-monopoli AS dari pesaing-pesaing internasional, terutama Cina, saham-saham AS sudah bukan lagi dianggap sebagai investasi yang terjamin seperti sebelumnya. Demikian juga, dengan semakin tingginya hutang pemerintahan federal AS, dan dengan semakin tergantungnya pemerintahan AS pada pembiayaan defisit, surat-surat hutang AS sudah tidak lagi dilihat sebagai aset investasi yang aman seperti sebelumnya. Ini telah menyebabkan melemahnya dolar – kendati tarif yang dikenakan AS – dan melemahnya dominasinya dalam arena keuangan dunia.
Ini mewakili ‘koreksi pasar’, yang membawa harga mata uang, aset, dan surat utang AS lebih dekat dengan posisi ekonomi kapitalisme AS yang sesungguhnya, yang telah melemah. Meskipun begitu, seperti halnya dengan kekuatan militer AS dan peran AS sebelumnya sebagai polisi dunia, tidak ada alternatif yang memadai untuk dolar dalam perdagangan dunia dan keuangan dunia. Inilah mengapa para ahli strategi borjuis sangat khawatir akan kekacauan terhadap sistem keuangan dunia dan perekonomian dunia bila kepercayaan pada dolar runtuh.
Inilah salah satu cara bagaimana kemunduran relatif kapitalisme AS dan kemunculan ‘multipolaritas’ akan berkontribusi pada ketidakpastian dan ketidakstabilan yang lebih besar dalam skala dunia. Satu demi satu, semua pilar tatanan pasca-perang sedang tergerus dan dilemahkan, dengan konsekuensi-konsekuensi yang eksplosif, secara ekonomi, militer, dan politik.
Kekuatan militer Rusia
Meski Rusia bukan raksasa ekonomi sekelas Cina, negara ini telah membangun fondasi ekonomi dan teknologi yang kokoh. Hal ini memungkinkannya bertahan menghadapi agresi ekonomi luar biasa dari Barat yang dikemas dengan label ‘sanksi’. Bahkan, Rusia mampu melakukannya sembari melanjutkan perang yang berhasil menahan serangan berbagai sistem persenjataan yang dihantarkan oleh imperialisme Barat. Rusia kini memiliki angkatan bersenjata yang sebanding dengan gabungan kekuatan militer negara-negara Eropa; ia telah membangun industri pertahanan yang kuat, yang mampu memproduksi tank, artileri, amunisi, misil, dan drone dalam jumlah yang melampaui AS dan Eropa; dan ia juga mewarisi dari Uni Soviet persenjataan nuklir terbesar di dunia.
Setelah runtuhnya Uni Soviet dan penjarahan besar-besaran terhadap ekonomi terencana, kelas penguasa Rusia sempat berangan-angan untuk diterima sejajar di panggung dunia. Bahkan, sempat muncul gagasan untuk bergabung dengan NATO. Namun tawaran itu ditolak. AS menginginkan dominasi penuh dan tanpa batas atas dunia, dan mereka tidak melihat alasan untuk berbagi kekuasaan dengan Rusia yang saat itu lemah dan dilanda krisis.
Rusia benar-benar dipermalukan, pertama ketika Jerman dan AS merekayasa pecahnya Yugoslavia – wilayah yang secara historis berada dalam pengaruh Rusia – dan kemudian saat Serbia dibombardir pada 1999. Yeltsin, seorang pemabuk yang konyol dan boneka imperialisme AS, menjadi simbol dari hubungan yang timpang tersebut.
Namun, dengan pulihnya Rusia dari krisis ekonomi secara perlahan-lahan, lingkaran penguasa Rusia tidak lagi siap menerima dipermalukan di panggung dunia. Inilah yang menjadi basis kebangkitan Putin, seorang Bonapartis yang licik, yang naik ke tampuk kekuasaan dengan segala macam manuver.
Mereka mulai melawan perluasan NATO ke timur, sebuah langkah yang mengingkari semua janji yang telah dibuat kepada Rusia pada 1990, ketika Rusia dijanjikan tidak akan ada perluasan NATO ke timur sebagai imbalan bila mereka menerima unifikasi Jerman dalam NATO.
Pada 2008, Rusia meluncurkan perang singkat namun efektif di Georgia, menghancurkan angkatan bersenjata negara itu yang sebelumnya telah dilatih dan dipersenjatai oleh NATO. Itu merupakan peringatan pertama dari Rusia bahwa mereka tak lagi akan menoleransi perluasan pengaruh Barat. Setelah itu, Suriah dan Ukraina menjadi ajang berikutnya. Di kedua negara ini, kekuatan Rusia dalam melawan imperialisme AS diuji. Sementara itu, kemunduran relatif kekuatan imperialisme AS semakin tampak jelas ketika mereka harus secara memalukan mundur dari Afghanistan pada Agustus 2021.
Invasi Rusia ke Ukraina merupakan kesimpulan logis dari penolakan Barat untuk mengakui kekhawatiran Rusia atas keamanan nasionalnya, khususnya tuntutannya agar Ukraina bersikap netral dan NATO menghentikan ekspansinya ke timur. Ketika Donald Trump menyatakan bahwa perang ini sebenarnya bisa dihindari dan tak akan terjadi jika ia menjadi presiden, ini mungkin ada benarnya. Imperialisme AS dan sekutu Eropanya sangat paham bahwa keanggotaan Ukraina dalam NATO adalah garis merah bagi kepentingan keamanan nasional Rusia. Meski begitu, pada 2008 mereka tetap mengundang Ukraina untuk mengajukan permohonan keanggotaan NATO. Ini merupakan provokasi terang-terangan yang secara logis membuka jalan menuju konsekuensi paling serius. Langkah fatal inilah yang pada akhirnya memicu perang.
Barat bersikeras pada apa yang mereka sebut sebagai “hak Ukraina untuk bergabung dengan NATO”, padahal status netral Ukraina, larangan terhadap pangkalan militer asing, dan ketidakikutsertaannya dalam blok militer sebenarnya telah disepakati dan bahkan tercantum dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Kepala CIA, William J. Burns, telah berulang kali memperingatkan bahaya langkah tersebut. Namun, kelompok penghasut perang yang mengendalikan kebijakan luar negeri pemerintahan Biden, termasuk Joe Biden sendiri, memiliki agenda yang berbeda.
Biden mengira bisa memanfaatkan Ukraina sebagai tumbal dalam upaya melemahkan Rusia dan melumpuhkan perannya di panggung dunia. Bagi AS, negara seperti Rusia, yang menjadi pesaing imperialisme Amerika, tidak boleh dibiarkan mengancam dominasi globalnya. Tetapi intervensi AS di Ukraina memiliki tujuan lainnya, walaupun tujuan ini tidak terlalu jelas tampak, yakni sehubungan dengan Jerman dan UE. Melemahkan hubungan ekonomi antara UE dan Rusia berarti melemahkan fondasi kapitalisme Jerman. Ini menjelaskan mengapa pada awalnya Jerman terutama tidak terlalu antusias dengan perang ini, tetapi karena terlalu lemah maka terpaksa harus mengikuti imperialisme AS setelah perang ini pecah.
Pada Maret 2022, dalam kesombongannya, Biden bahkan sempat menyuarakan ide perubahan rezim di Moskow! Bersama para sekutu Eropanya, ia yakin sanksi ekonomi dan kelelahan militer akan menggiring Rusia menuju kehancuran. Namun mereka sangat meremehkan kekuatan ekonomi dan militer Rusia. Akibatnya, imperialisme AS justru menemukan dirinya terseret dalam perang yang tak bisa dimenangkan, dan kini harus menanggung beban besar secara finansial maupun militer.
Trump kini bersikeras bahwa bencana ini bukan ulahnya. Ia mengatakan, “Ini bukan perang saya. Ini perangnya Joe Biden.” Dan itu memang benar. Para ahli strategi kapital tak jarang membuat kesalahan akibat perhitungan yang keliru, dan ini salah satunya. Ketika Trump menyatakan perang di Ukraina bukan bagian dari “kepentingan inti” Amerika, pernyataan itu sepenuhnya tepat. Amerika menghadapi ancaman yang jauh lebih besar di Asia dan Pasifik dengan bangkitnya kekuatan Cina, belum lagi persoalan lainnya di Timur Tengah serta krisis ekonomi yang kian memburuk. Itulah sebabnya ia begitu tergesa-gesa ingin menarik imperialisme AS keluar dari lumpur berbahaya yang bernama Ukraina itu. Namun problem yang diciptakan oleh Biden dan para kacung Eropanya ternyata tidak mudah untuk diselesaikan.
Lingkaran penguasa di Washington dan London secara sistematis menggagalkan setiap upaya untuk mencapai solusi damai bahkan sebelum perang ini pecah. Pada April 2022, perundingan antara Ukraina dan Rusia di Turki sebenarnya telah mencapai kemajuan yang signifikan dan berpotensi mengakhiri perang dengan menerima sejumlah tuntutan Rusia. Namun, imperialisme AS, didukung oleh Boris Johnson dari Inggris, menghentikan proses tersebut dengan menekan Zelensky agar tidak menandatangani kesepakatan, sambil menjanjikan dukungan tanpa batas yang katanya akan membawa Ukraina menuju kemenangan penuh. Hari ini, kelas penguasa Eropa-lah, yang dipimpin oleh Jerman, Prancis, dan lagi Inggris, yang menekan Trump untuk terus mendukung Ukraina dan terus mengobarkan api perang. Perhitungan mereka cukup sinis: mereka ingin mengikat AS dan mencegah AS menarik mundur kekuatan militernya dari Eropa. Pada saat yang sama, dengan darah puluhan ribu nyawa rakyat Ukraina dan Rusia, mereka ingin membeli waktu sebelum program penyenjataan ulang mereka mulai.
Pada awal perang, administrasi Biden percaya mereka dapat membuat Rusia menjadi paria di panggung dunia dan membuat Putin menjadi persona non grata. Perang ini justru memperdalam ketegangan relasi dunia, dan mengekspos kebohongan “komunitas internasional” yang mendukung imperialisme AS.
Selain UE, Jepang, Inggris dan Kanada, AS kesulitan memperoleh dukungan dari mayoritas luas kelas penguasa di negara-negara lain untuk perang proksinya dengan Rusia. Ini adalah konfirmasi mencolok bagaimana AS sudah tidak lalu mampu menggunakan pengaruh politiknya seperti 30 tahun yang lalu. Seperti yang diperingatkan Larry Summers, mantan sekretaris keuangan AS, mengenai keterisolasian kekuatan barat: “Semakin banyak orang menerima fragmentasi yang ada, dan – bahkan yang lebih mengkhawatirkan – ada perasaan yang semakin besar bahwa fragmen kita bukanlah fragmen yang paling dipilih oleh banyak pihak.”
Saat ini, AS menghadapi kekalahan yang memalukan di Ukraina. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Alih-alih mengalami keruntuhan ekonomi, Rusia justru menikmati pertumbuhan ekonomi yang stabil dan jauh melampaui negara-negara Barat. Bukannya terisolasi, Rusia kini menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Cina dan sejumlah negara kunci yang seharusnya berada dalam pengaruh AS. Negara-negara seperti India, Arab Saudi, Turki, dan lainnya telah membantunya mengatasi sanksi.
Cina dan Rusia kini menjalin aliansi yang semakin erat, dipersatukan oleh oposisi mereka terhadap dominasi global AS. Semakin banyak negara yang merapat ke mereka. Ketika kekalahan AS di Ukraina akhirnya menjadi kenyataan, dampaknya akan sangat besar dan panjang terhadap tatanan hubungan internasional, sekaligus semakin melemahkan cengkeraman imperialisme AS di seluruh dunia.
Kekalahan AS-NATO di Ukraina akan menjadi pesan yang kuat bagi dunia: kekuatan imperialis terbesar tidak selalu bisa memaksakan kehendaknya. Selain itu, Rusia justru keluar dari konflik ini dengan kekuatan militer besar yang telah teruji dalam berbagai metode dan teknik perang modern, serta didukung oleh kompleks industri pertahanan yang tangguh.
Kebijakan Trump dalam hal ini menandai perubahan tajam dari arah sebelumnya yang ditempuh oleh imperialisme AS. Ia menyadari bahwa perang melawan Rusia tidak dapat dimenangkan, dan karena itu berupaya menarik AS keluar dari konflik tersebut. Ada juga perhitungan strategis bahwa menjalin kesepakatan dengan Rusia, yakni dengan mengakui kepentingan keamanan nasionalnya (dalam kata lain kepentingan imperialisme Rusia), ini mungkin bisa menjauhkan Rusia dari aliansi dekatnya dengan Cina, rival utama imperialisme AS di panggung global. Namun, kemungkinan besar perhitungan strategis ini akan meleset, karena selama tiga tahun perang Barat telah mendorong Rusia terlalu dekat ke Cina, sehingga akan sulit memisahkan mereka. Berbagai pernyataan dan tindakan pemerintahan Rusia dan Cina baru-baru ini mengindikasikan bahwa mereka melihat aliansi mereka sebagai aliansi strategis.
Kebangkitan Cina sebagai kekuatan imperialis
Transformasi cepat Cina dari ekonomi yang sangat terbelakang menjadi negara kapitalis yang kuat hampir tidak ada presedennya dalam sejarah modern. Dalam waktu yang sangat singkat, Cina berhasil bangkit hingga ada dalam posisi yang mampu menantang kekuatan besar imperialisme AS.
Cina hari ini sama sekali berbeda dengan Cina pada 1938, yang lemah, setengah feodal dan setengah jajahan. Kini, Cina bukan hanya negara kapitalis, tetapi juga telah menunjukkan seluruh fitur kekuatan imperialis.
Transformasi ini mustahil dipahami tanpa melihat peran krusial Revolusi Cina tahun 1949, yang menghapuskan pertuantanahan dan kapitalisme serta membangun landasan bagi ekonomi terencana yang dinasionalisasi. Inilah syarat utama yang memungkinkan transformasi Cina dari negara setengah kolonial yang terbelakang menjadi raksasa ekonomi seperti sekarang.
Sebagai pendatang baru di panggung internasional, Cina harus berjuang keras untuk menguasai sumber bahan mentah dan energi bagi industrinya, wilayah investasi bagi modalnya, jalur perdagangan ekspor-impor, serta pasar bagi produknya. Di semua bidang ini, Cina telah meraih keberhasilan yang menonjol.
Kebangkitan Cina selama 30 tahun terakhir merupakan hasil dari investasi besar-besaran dalam alat-alat produksi serta ketergantungan pada pasar dunia. Pada awalnya, Cina memanfaatkan cadangan tenaga kerja murah yang melimpah untuk mengekspor barang-barang seperti tekstil dan mainan ke pasar dunia.
Sekarang, ia merupakan ekonomi kapitalis yang maju secara teknologi, dengan posisi dominan di dunia dalam sejumlah pasar teknologi tinggi (kendaraan listrik dan baterai EV, sel fotovoltaik, bahan baku antibiotik, drone komersial, infrastruktur komunikasi seluler 5G, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan sebagainya), tidak hanya dari segi volume penjualan, tetapi juga dalam hal inovasi.
Cina juga memimpin dunia dalam bidang robotika. Negara ini menempati peringkat ketiga dalam kepadatan robot industri, dengan 470 robot untuk setiap 10.000 pekerja manufaktur, meskipun jumlah tenaga kerjanya di sektor ini melebihi 37 juta orang. Angka ini menempatkan Cina di belakang Korea Selatan (1012) dan Singapura (770), namun di depan Jerman (429) dan Jepang (419), serta jauh melampaui Amerika Serikat (295). Data ini dari tahun 2023, dan kemungkinan peringkat Cina telah meningkat sejak saat itu, karena pada tahun tersebut Cina menyumbang 51 persen dari seluruh pemasangan robot industri baru di dunia.
Dalam hal ekspor modal, Cina berada di posisi kedua setelah AS. Pada 2023, AS menyumbang 32,8 persen dari total arus keluar FDI global, sementara gabungan Cina dan Hong Kong mencapai 20,1 persen. Untuk akumulasi total FDI, AS menguasai 15,1 persen dari keseluruhan global, sedangkan Cina dan Hong Kong menyumbang 11,3 persen. Meskipun Amerika mendominasi ekspor kapital, rencana strategis jangka panjang China untuk ekspor modal ini telah memungkinkan mereka, selama dua dekade terakhir, untuk memperkuat kontrol yang signifikan atas rute perdagangan maritim serta produksi dan pengolahan mineral yang penting bagi sebagian besar teknologi modern. Tiongkok mendominasi pertambangan mineral tanah jarang global (69%) dan pengolahan (92%). Tiongkok juga mendominasi pengolahan mineral penting seperti kobalt (80%), nikel (68%), dan litium (60%). Selain itu, Tiongkok terus memperkuat kendalinya atas ekstraksi cadangan utama, seperti di Kongo (di mana Tiongkok mengendalikan 15 dari 19 tambang kobalt terbaik di negara itu) dan Argentina (43% ekspor litiumnya dikirim ke Tiongkok, dibandingkan dengan 11% ke AS). Hal ini penting tidak hanya untuk mendominasi produksi sektor-sektor teknologi penting yang disebutkan di atas, tetapi juga untuk menetapkan kontrol tertentu terhadap ekspor mineral-mineral ini ke AS, yang merupakan alat tawar-menawar penting dalam negosiasi tarif dengan Trump.
Sebagai hasil dari bagaimana kapitalisme dipulihkan di Cina, negara memainkan peran penting dalam perekonomian. Pemerintah secara sadar menjalankan kebijakan untuk mendorong dan mendanai pengembangan teknologi. Program ‘Made in China 2025’ bertujuan mendorong lompatan besar dalam industri-industri kunci, serta menjadikan Cina mandiri dan tidak bergantung pada Barat. Pengeluaran Cina untuk riset dan pengembangan telah meningkat secara signifikan dan kini hampir setara dengan AS.
Kesuksesan ini tidak dicapai tanpa menimbulkan kontradiksi dan ketegangan yang semakin besar dengan negara-negara kapitalis lainnya, yang pada akhirnya memicu perang dagang dengan AS saat ini.
Setelah runtuhnya Uni Soviet dan terbukanya pasar-pasar baru lewat kebijakan globalisasi, pertumbuhan ekonomi kapitalis di Cina awalnya dipandang oleh para ekonom dan investor Barat sebagai peluang emas.
Investor Barat berbondong-bondong berebut membangun pabrik di Cina, demi memanfaatkan pasokan tenaga kerja murah yang tampaknya tak ada habisnya. Antara tahun 1997 hingga 2019, 36 persen pertumbuhan stok modal global (pertumbuhan jumlah aset produktif seperti mesin, peralatan, gedung, dan infrastruktur) datang dari Cina. Begitu dalamnya penetrasi modal AS di Cina hingga kedua ekonomi tersebut tampak seperti tak terpisahkan satu sama lain.
Pertumbuhan di Cina sebenarnya memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi dunia selama beberapa dekade. Pada 2008, kaum borjuis Barat bahkan berharap Cina dapat membantu menarik ekonomi global keluar dari resesi. Namun, seperti yang telah kita tunjukkan saat itu, ini juga membawa dampak negatif yang sangat serius dan mengancam bagi mereka.
Pabrik-pabrik tersebut, yang menggunakan teknologi modern, menghasilkan sejumlah besar komoditas murah yang harus diekspor, karena permintaan di dalam negeri Cina sendiri masih terbatas. Pada akhirnya, ini menimbulkan masalah serius bagi AS dan ekonomi Barat lainnya.
Segalanya berubah menjadi kebalikannya. Pertanyaan yang semakin sering muncul adalah: siapa sebenarnya yang membantu siapa? Memang benar para investor Barat meraup keuntungan besar, namun lewat investasi tersebut Cina membangun kemampuan manufaktur canggih, keahlian teknologi, infrastruktur, dan tenaga kerja terampil. Ini semakin dianggap sebagai ancaman, terutama di Amerika.
Kini Cina telah menjadi supplier krusial bagi produsen global, baik dalam hal produk konsumen seperti iPhone maupun barang modal dan komponen penting. Sebanyak 36 persen impor AS berasal dari Cina, yang memenuhi lebih dari 70 persen kebutuhan AS atas produk-produk tersebut.
Cina telah menjelma menjadi rival sistemik bagi AS di panggung global. Inilah makna sesungguhnya dari perang dagang yang dilancarkan Trump terhadap Cina. Ini adalah perebutan pengaruh antara dua kekuatan imperialis untuk menegaskan dominasi mereka di pasar dunia.
Washington telah menempuh langkah-langkah ekstrem untuk menjaga dominasinya, mulai dari melarang penjualan mikrochip tercanggih ke Cina, memblokir akses terhadap mesin litografi mutakhir, hingga mencegah perusahaan seperti Huawei ikut serta dalam tender proyek infrastruktur 5G di berbagai negara, dst.
Namun upaya AS untuk menghambat perkembangan teknologi mutakhir Cina justru menjadi bumerang. Sebagai tanggapan, Cina mempercepat langkah menuju kemandirian. Meski masih menghadapi sejumlah kendala, misalnya karena tidak mendapat akses ke mesin litografi EUV tercanggih yang digunakan untuk membuat mikroprosesor paling mutakhir, Cina berhasil menemukan jalan keluar parsial dengan mengandalkan kecerdikan dan inovasi.
Memang benar bahwa, terlepas dari kemajuannya, ekonomi Cina masih menyimpan banyak kontradiksi. Produktivitas tenaga kerja di Cina terus meningkat lewat kemajuan ilmu pengetahuan, industri, dan teknologi, sementara di Eropa telah lama stagnan dan di AS hanya tumbuh secara moderat dalam beberapa tahun terakhir. Namun secara keseluruhan, produktivitas tenaga kerja Cina masih tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan AS. Butuh waktu untuk menutup kesenjangan itu.
Wajar pula untuk menganggap bahwa laju pertumbuhan luar biasa yang dicapai Cina selama beberapa dekade terakhir tidak akan terus berlanjut. Perlambatan itu, kenyataannya, sudah mulai terasa. Pada 1990-an, Cina tumbuh dengan laju mencengangkan sebesar 9 persen per tahun, bahkan sempat menyentuh 14 persen. Antara 2012 hingga 2019, pertumbuhannya berkisar antara 6 hingga 7 persen. Kini hanya sekitar 5 persen. Namun demikian, ekonomi Cina secara keseluruhan masih tumbuh lebih cepat dibanding negara-negara kapitalis maju di Barat.
Tentu saja, dengan kenyataan bahwa Cina telah menjadi ekonomi kapitalis yang sangat terintegrasi ke dalam pasar dunia, cepat atau lambat ia harus menghadapi seluruh persoalan yang menyertainya. Ketimpangan pembangunan antarwilayah sudah tampak jelas, begitu pula ketimpangan pendapatan yang sangat lebar. Pengangguran meningkat, terutama di kalangan pekerja migran dan kaum muda.
Paket stimulus ekonomi besar-besaran dan kebijakan Keynesian telah mendorong lonjakan utang. Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang pada tahun 2000 hanya 23 persen naik menjadi 60,5 persen pada 2024. Ini kenaikan yang signifikan, meskipun masih lebih rendah dibanding sebagian besar negara kapitalis maju. Namun jika dihitung secara keseluruhan (utang negara, korporasi, dan rumah tangga) angkanya telah mencapai 300 persen dari PDB.
Bangkitnya proteksionisme dan melambatnya perdagangan dunia sudah pasti akan berdampak pada Cina. Satu-satunya cara untuk keluar dari krisis ini adalah dengan semakin agresif mendorong overproduksinya ke pasar dunia, yang pada gilirannya akan memperuncing ketegangan global sekaligus memperdalam krisis sistem secara keseluruhan.
Dalam pertarungan raksasa antara dua kekuatan ekonomi ini, pertanyaannya muncul secara terang-terangan: siapa yang akan unggul? Kolom-kolom pers Barat dipenuhi penilaian negatif dan peringatan suram mengenai masa depan ekonomi Cina.
Pers Barat secara konsisten berupaya menggambarkan kondisi ekonomi Cina dalam warna yang suram, sebagaimana mereka selalu lakukan terhadap ekonomi Rusia, yang kenyataannya masih mencatat laju pertumbuhan sehat di kisaran 4 hingga 5 persen per tahun. Ini sama sekali bukan ekonomi yang berada di ambang kehancuran.
Cina tentu tidak imun dari krisis, tetapi ia juga memiliki cadangan yang cukup besar untuk menghadapi tantangan ini dan keluar darinya dengan dampak yang jauh lebih kecil daripada yang kerap digembar-gemborkan oleh pers Barat. Yang terpenting, perlu diingat bahwa Cina, meskipun merupakan negara kapitalis, masih memiliki banyak kekhasan.
Kenyataannya, negara masih memainkan peran yang cukup besar dalam mengontrol, mengintervensi dan merencanakan ekonomi Cina. Ini justru menjadi keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan negara-negara seperti AS.
Ada pula faktor-faktor politik, kultural, dan psikologis yang penting dan dapat memainkan peran menentukan dalam setiap konflik dengan kekuatan imperialis asing. Rakyat Cina menyimpan ingatan yang panjang dan pahit bagaimana mereka dulunya dijajah, dieksploitasi, dan dipermalukan oleh imperialisme.
Seburuk apa pun pandangan mereka terhadap kelas penguasa di negeri mereka sendiri, kebencian terhadap imperialis asing jauh lebih besar dan dapat menjadi penopang kuat bagi rezim dalam konfrontasinya dengan AS.
Lingkaran penguasa AS menyaksikan kebangkitan Cina dengan kepanikan yang terus meningkat. Mereka mengambil sikap agresif, yang tercermin di satu sisi lewat kenaikan tarif yang drastis oleh Trump, dan di sisi lain melalui provokasi yang terus-menerus terkait Taiwan.
Para penghasut perang di Washington terus-menerus menuduh Cina merencanakan invasi terhadap Taiwan, yang dianggap oleh Cina sebagai wilayah pemberontak yang secara sah merupakan bagian mereka.
Namun lingkaran penguasa di Cina dipimpin oleh orang-orang yang telah lama menguasai seni kesabaran dalam diplomasi. Mereka tidak merasa perlu menyerbu Taiwan. Mereka yakin, cepat atau lambat, pulau itu akan kembali bersatu dengan Cina daratan. Mereka menunggu selama puluhan tahun untuk merebut kembali Hong Kong dari tangan Inggris, dan mereka tak melihat alasan untuk menempuh solusi militer yang tergesa-gesa.
Hanya kesalahan perhitungan serius dari para penghasut perang di Washington, atau keputusan gegabah dari kaum nasionalis Taiwan untuk menyatakan kemerdekaan, yang bisa mendorong Cina mengambil langkah militer. Dalam situasi seperti itu, para penguasa di Beijing akan berada dalam posisi yang kuat.
Taiwan tak akan mampu bertahan lama menghadapi kekuatan militer darat dan laut Cina yang hanya berjarak beberapa mil jauhnya, sementara Amerika harus mengerahkan pasukan besar melintasi samudra, menghadapi kondisi yang sulit dan penuh risiko.
Bagaimanapun juga, tak ada tanda bahwa Donald Trump sendiri tengah mencari konfrontasi militer dengan Cina. Ia lebih memilih cara lain, yakni dengan menerapkan sanksi yang melumpuhkan dan tarif tinggi untuk memaksa Cina tunduk. Namun Cina sama sekali tak berniat menyerah, baik dalam perang ekonomi maupun konflik militer yang nyata.
Hingga beberapa waktu lalu, Cina lebih banyak memproyeksikan kekuatannya melalui cara-cara ekonomi, namun kini mereka juga tengah membangun kekuatan militer. Baru-baru ini, Cina mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan sebesar 7,2 persen. Mereka telah memiliki angkatan darat yang besar dan kuat, dan kini sedang mengembangkan kekuatan angkatan laut yang modern dan sebanding untuk melindungi kepentingannya di lautan lepas.
Sebuah artikel dari BBC belum lama ini melaporkan saat ini Cina memiliki angkatan laut terbesar di dunia, melampaui AS. Tidak benar pula jika dikatakan bahwa angkatan bersenjatanya masih bergantung pada teknologi dan peralatan usang. Artikel yang sama menyatakan bahwa:
“Cina kini sepenuhnya berkomitmen mengembangkan bentuk peperangan ‘berbasis kecerdasan’, atau metode militer masa depan yang didasarkan pada teknologi disruptif, khususnya kecerdasan buatan, menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat.”
Mereka juga menambahkan bahwa:
“Akademi Ilmu Militer Cina telah diberi mandat untuk memastikan hal ini terwujud melalui apa yang disebut sebagai “fusi sipil-militer”, yaitu menggabungkan perusahaan teknologi sektor swasta Cina dengan industri pertahanannya. Laporan menengarai bahwa Cina kemungkinan sudah mulai menggunakan kecerdasan buatan dalam robotika militer dan sistem panduan rudal, serta kendaraan udara tak berawak dan kapal laut tak berawak.”
Selain itu, Cina memiliki salah satu program antariksa paling aktif di dunia. Di antara misi-misinya, Cina memiliki rencana ambisius untuk membangun stasiun luar angkasa di bulan dan mengunjungi Mars. Selain untuk kepentingan ilmiah, rencana ini jelas terkait dengan program militer yang sangat ambisius.
Perkembangan kekuatan produktif di Cina kini merupakan fakta yang tak terbantahkan. Tidak ada gunanya menyangkalnya. Lagi pula, secara objektif, ini bukanlah perkembangan yang negatif dari sudut pandang revolusi dunia, karena telah melahirkan kelas buruh yang masif, yang terbiasa dengan peningkatan taraf hidup dari tahun ke tahun dalam kurun waktu yang panjang. Ini adalah kelas buruh yang muda dan segar, belum terbebani oleh kekalahan, dan tidak terikat pada organisasi-organisasi reformis.
“Cina adalah naga yang sedang tidur. Biarkan ia tidur, karena ketika ia terbangun, ia akan mengguncang dunia” adalah pernyataan yang kabarnya diucapkan oleh Napoleon. Entah benar ia mengatakannya atau tidak, ungkapan itu jelas berlaku untuk proletariat Cina yang kuat saat ini. Momen kebenaran mungkin masih tertunda untuk sementara waktu. Namun ketika kekuatan dahsyat itu mulai bergerak, ia akan memicu ledakan dengan proporsi seismik.
Bermain dua kaki di antara kekuatan-kekuatan Besar
Kemunduran relatif imperialisme AS dan bangkitnya Cina telah menciptakan situasi di mana sejumlah negara bermain dua kaki di antara kedua kekuatan ini dan memperoleh sedikit otonomi untuk mengejar kepentingan mereka sendiri, setidaknya di tingkat regional. Ini mencakup negara-negara seperti Turki, Arab Saudi, India, dan lainnya dalam berbagai tingkatan.
Kemunculan BRICS, yang secara resmi diluncurkan pada 2009, merupakan upaya Cina dan Rusia untuk memperkuat posisi mereka di panggung dunia, melindungi kepentingan ekonomi mereka, dan menarik serangkaian negara ke dalam lingkup pengaruh mereka.
Penerapan sanksi-sanksi ekonomi oleh imperialisme AS terhadap Rusia telah mempercepat proses ini. Dalam upayanya untuk mencari cara untuk menghindari dan mengatasi sanksi tersebut, Rusia membentuk serangkaian aliansi dengan negara-negara lain, termasuk Arab Saudi, India, Cina, dan banyak lagi.
Alih-alih menunjukkan kekuatan AS, kegagalan sanksi ini justru mengungkapkan batas kemampuan imperialisme AS dalam memaksakan kehendaknya, dan mendorong sejumlah negara untuk mempertimbangkan alternatif terhadap dominasi AS dalam transaksi keuangan. Keanggotaan BRICS pun meluas, dengan negara-negara baru diundang atau mengajukan diri untuk bergabung.
Dalam menyikapi persoalan ini, penting untuk mengkajinya secara proporsional dan tidak berlebihan. Walaupun perubahan-perubahan ini penting, BRICS dipenuhi berbagai kontradiksi. Brasil, misalnya, meskipun menjadi bagian dari BRICS, pada saat yang sama juga tergabung dalam Mercosur, blok perdagangan bebas Amerika Selatan yang sedang merundingkan perjanjian perdagangan bebas dengan UE.
India termasuk dalam blok tersebut, namun enggan menerima anggota baru karena ini dapat mengurangi bobotnya dalam BRICS. Di saat yang sama, India menjalin ‘kemitraan strategis’ dengan AS; menjadi bagian dari aliansi keamanan dan militer Quad bersama AS, Jepang, dan Australia; serta angkatan lautnya secara rutin menggelar latihan militer bersama dengan AS.
Yang menarik di sini adalah bahwa negara seperti India, sekutu AS sekaligus saingan Cina, telah memainkan peran penting dalam membantu Rusia menghindari sanksi AS. India membeli minyak Rusia dengan harga diskon, lalu menjualnya kembali ke Eropa dalam bentuk produk olahan dengan harga lebih tinggi. Untuk saat ini, AS memilih untuk tidak mengambil tindakan terhadap India.
Hingga kini, BRICS masih merupakan aliansi yang longgar. Tindakan semena-mena imperialisme AS terhadap para rivalnya justru mendorong mereka semakin merapat satu sama lain dan menarik minat negara-negara lain untuk bergabung.
Krisis di Eropa
Meski kekuatan dan pengaruh global AS telah mengalami kemunduran relatif, kekuatan imperialis lama di Eropa—seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan lainnya—telah merosot lebih jauh sejak masa kejayaan mereka dulu. Mereka telah menjadi kekuatan kelas dua di dunia. Perlu dicatat peran imperialis negara-negara Eropa mengalami pelemahan yang signifikan dalam dekade terakhir. Serangkaian kudeta militer, misalnya, telah menyingkirkan Prancis dari Afrika Tengah dan Sahel, yang sebagian besar menguntungkan Rusia.
Negara-negara Eropa membuntuti imperialisme AS dalam perang proksi di Ukraina melawan Rusia, yang berdampak buruk pada perekonomian mereka. Sejak runtuhnya Stalinisme pada 1989–1991, Jerman menjalankan kebijakan memperluas pengaruhnya ke Timur dan membangun hubungan ekonomi erat dengan Rusia. Industri Jerman mendapat keuntungan besar dari energi murah dari Rusia. Sebelum perang di Ukraina, lebih dari setengah pasokan gas alam Jerman, sepertiga kebutuhan minyak, dan setengah impor batubara berasal dari Rusia.
Inilah salah satu faktor keberhasilan industri Jerman di dunia, di samping dua faktor lainnya: deregulasi pasar tenaga kerja (yang dilaksanakan di bawah pemerintahan sosial demokrat) dan investasi besar-besaran di sektor industri pada paruh kedua abad lalu. Dominasi kelas penguasa Jerman atas Uni Eropa serta perdagangan bebas dengan Cina dan AS melengkapi siklus positif yang memungkinkan Jerman keluar dari krisis 2008 dengan kondisi baik.
Situasi serupa juga terjadi di Uni Eropa secara keseluruhan, di mana Rusia merupakan pemasok utama minyak bumi (24,8 persen), gas pipa (48 persen), dan batubara (47,9 persen). Sanksi-sanksi Eropa terhadap Rusia setelah dimulainya perang Ukraina menyebabkan lonjakan harga energi, yang menyebabkan inflasi dan menurunnya daya saing ekspor Eropa. Akibatnya, Eropa terpaksa mengimpor LNG dari AS dengan harga jauh lebih mahal, serta produk minyak Rusia yang juga lebih mahal melalui India.
Faktanya, sebagian besar pasokan gas Jerman masih datang dari Rusia, hanya saja kini dalam bentuk LNG dengan harga yang jauh lebih mahal. Kelas penguasa di Jerman, Prancis, dan Italia telah menembak kaki mereka sendiri dan kini harus menanggung akibatnya. Bahkan sejak masa kepresidenan Biden, Amerika Serikat membalas para sekutu Eropanya dengan melancarkan perang dagang melalui serangkaian kebijakan proteksionis dan subsidi industri.
Masyarakat Ekonomi Eropa yang kemudian menjadi Uni Eropa, merupakan upaya dari kekuatan-kekuatan imperialis yang melemah di benua itu untuk bersatu setelah Perang Dunia Kedua dengan harapan dapat memainkan peran lebih besar dalam politik dan ekonomi global. Dalam praktiknya, kapital Jerman mendominasi ekonomi-ekonomi lain yang lebih lemah. Selama ada pertumbuhan ekonomi, tingkat integrasi ekonomi tertentu dapat tercapai, bahkan hingga penggunaan mata uang tunggal.
Namun, kelas-kelas penguasa nasional yang membentuknya tetap eksis, masing-masing dengan kepentingannya sendiri. Terlepas dari semua retorika, tidak ada kebijakan ekonomi bersama, tidak ada kebijakan luar negeri yang terpadu, dan tidak ada satu angkatan bersenjata untuk melaksanakannya. Sementara kapital Jerman bertumpu pada ekspor industri yang kompetitif dan kepentingannya terletak di Timur, Prancis memperoleh subsidi pertanian dalam jumlah besar dari UE, dan kepentingan imperialisnya terletak di bekas koloni-koloni Prancis, terutama di Afrika.
Krisis utang negara yang menyusul resesi 2008 telah mendorong UE hingga ke limitnya. Kini situasinya bahkan semakin memburuk. Laporan terbaru dari mantan presiden Bank Sentral Eropa, Mario Draghi, menggambarkan krisis kapitalisme Eropa dengan nada yang mengkhawatirkan, dan dia tidak keliru. Pada dasarnya, alasan UE tidak mampu bersaing dengan rival imperialisnya di dunia adalah karena UE bukanlah satu kesatuan entitas ekonomi-politik, melainkan sekumpulan ekonomi kecil dan menengah, masing-masing dengan kelas penguasa mereka sendiri, industri nasional mereka sendiri, serta seperangkat regulasi yang berbeda-beda. Ekonomi Eropa kini stagnan dan telah tertinggal dari para pesaingnya dalam hal pertumbuhan produktivitas.
Kekuatan produktif telah melampaui batas-batas negara bangsa, dan masalah ini terasa sangat tajam di negara-negara Eropa yang kecil namun secara ekonomi sangat maju.
Kemunduran kekuatan imperialis Eropa yang berlangsung lama ini tersamarkan oleh fakta bahwa AS menanggung biaya pertahanannya dan memberikan dukungan politik kepada UE. Selama hampir 80 tahun, imperialisme AS menopang Eropa di bawah dominasinya, sebagai benteng untuk menghadapi Uni Soviet. Bagi kapitalisme Eropa, pengaturan ini sangat menguntungkan karena memungkinkan mereka mengalihkan sebagian besar biaya pertahanan militernya kepada “sepupu” kuat mereka di seberang Atlantik.
Semua itu kini telah berakhir. Imperialisme AS di bawah Trump memutuskan untuk mengelola kemunduran relatifnya dengan mencoba mencapai kesepakatan dengan Rusia, agar bisa lebih fokus menghadapi rival utamanya di panggung dunia: Cina. Pusat politik dan ekonomi dunia tidak lagi berada di Atlantik, melainkan telah bergeser ke Pasifik. Pergeseran ini sebenarnya telah berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, namun kini muncul ke permukaan secara eksplosif.
Ini merupakan guncangan besar dalam hubungan internasional yang tak bisa diabaikan siapa pun. Jika AS ingin menjalin kesepahaman dengan Rusia, maka imperialisme Eropa berada dalam posisi yang sangat lemah. AS sudah bukan lagi temannya dan sekutunya. Bahkan ada yang berpendapat Washington kini memandang Eropa sebagai saingan, atau bahkan musuh.
Yang jelas, Trump telah menyatakan dengan tegas bahwa AS tidak lagi bersedia menyubsidi pertahanan Eropa. Penarikan “payung perlindungan” AS, sebagaimana sebagian orang menyebutnya, telah memperlihatkan dengan gamblang semua kelemahan imperialisme Eropa yang telah menumpuk selama dekade-dekade kemundurannya.
Krisis kapitalisme Eropa membawa dampak politik dan sosial yang signifikan. Munculnya kekuatan populis sayap kanan, euro-skeptis, dan anti-kemapanan di seluruh benua Eropa merupakan akibat langsung dari krisis ini. Kelas pekerja Eropa, yang kekuatannya sebagian besar masih utuh dan belum dikalahkan, tidak akan menerima gelombang baru pemotongan anggaran dan pemecatan massal tanpa perlawanan. Panggung telah disiapkan untuk ledakan perjuangan kelas.
Perang di Timur Tengah
Konflik yang terjadi saat ini di Timur Tengah hanya bisa dipahami dalam konteks situasi dunia secara keseluruhan. Imperialisme AS telah melemah di kawasan ini, sementara Rusia, Cina, dan juga Iran menjadi lebih kuat. Israel merasa terancam. Serangan 7 Oktober menjadi pukulan serius bagi kelas penguasa Israel. Serangan itu menghancurkan mitos tentang ketakterkalahan Israel dan membuat rakyat Yahudi mempertanyakan kemampuan negara Zionis untuk melindungi mereka, isu utama yang selama ini digunakan oleh kelas penguasa Israel untuk menggalang dukungan rakyat.
Peristiwa itu juga dengan jelas mengungkapkan runtuhnya Kesepakatan Oslo, yang ditandatangani setelah keruntuhan Stalinisme. Keseluruhan proses tersebut sejak awal hingga akhir adalah penipuan yang sinis. Kelas penguasa Zionis tak pernah benar-benar berniat memberikan tanah air yang layak bagi rakyat Palestina. Mereka memandang Otoritas Nasional Palestina (PA) semata-mata sebagai cara untuk meng-outsource tugas pengawasan terhadap rakyat Palestina. Ini mendiskreditkan Fatah dan PA—yang secara luas dipandang, dengan tepat, sebagai boneka Israel—dan pada akhirnya, dengan restu diam-diam dari Israel, membuka jalan bagi bangkitnya Hamas, yang oleh banyak orang dipandang sebagai satu-satunya kekuatan yang benar-benar memperjuangkan hak nasional rakyat Palestina.
Namun pada kenyataannya, cara-cara reaksioner yang ditempuh oleh Hamas justru menjerumuskan rakyat Palestina ke dalam jalan buntu yang sulit untuk ditemukan jalan keluarnya.
Kesepakatan Abraham, yang ditandatangani pada 2020 di bawah tekanan pemerintahan Trump pertama, dimaksudkan untuk meneguhkan posisi Israel di kawasan itu sebagai aktor yang sah serta menormalisasi hubungan dagang antara Israel dan negara-negara Arab. Ini pada dasarnya berarti mengubur aspirasi nasional rakyat Palestina—sesuatu yang dengan senang hati diterima oleh rezim-rezim Arab yang reaksioner. Serangan 7 Oktober merupakan respons putus asa terhadap hal tersebut.
Serangan itu awalnya disambut dengan sorak-sorai oleh warga Palestina, namun dampaknya sangat mengerikan. Netanyahu, yang sebelumnya tengah menghadapi gelombang besar protes massal, mendapat dalih sempurna untuk melancarkan kampanye genosida terhadap Gaza. Netanyahu, Ben Gvir, Smotrich dkk. melihat serangan 7 Oktober sebagai peluang emas. Dengan dalih ‘keamanan’ dan ‘keselamatan’ warga Israel, mereka bertujuan melakukan penghapusan etnis terhadap rakyat Palestina dengan mengusir mereka dari tanah air mereka. Mereka juga berupaya menegaskan kembali perang imperialis mereka di wilayah Timur Tengah dengan memulai perang di berbagai front.
Setahun kemudian, Israel telah meratakan Gaza menjadi puing-puing, namun tujuan yang mereka nyatakan – pembebasan para sandera dan penghancuran Hamas – belum tercapai. Kedua tujuan perang ini bertentangan langsung satu sama lain. Tujuan pertama membutuhkan kesepakatan dengan Hamas, sementara tujuan yang kedua mengecualikan kesepakatan seperti itu. Ada kemarahan yang luas bahwa pemerintahan Israel hanya memikirkan bagaimana menghancurkan musuh mereka. Ini memicu demonstrasi besar-besaran oleh ratusan ribu warga Israel, bahkan sempat terjadi pemogokan umum yang singkat pada September 2024.
Demonstrasi-demonstrasi tersebut bukanlah bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina, atau penolakan langsung terhadap perang itu sendiri. Namun, kenyataan bahwa terjadi penolakan massal terhadap perdana menteri di tengah situasi perang mencerminkan betapa besarnya perpecahan di dalam masyarakat Israel.
Runtuhnya dukungan terhadapnya mendorong Netanyahu untuk mengeskalasi situasi dengan meluncurkan invasi ke Lebanon dan menyerang Hizbullah, yang disertai dengan provokasi terus-menerus terhadap Iran. Demi menyelamatkan posisinya secara politik, ia berulang kali menunjukkan kesiapannya memicu perang regional, yang akan memaksa AS turun tangan langsung untuk mendukungnya.
Meski pembantaian di Gaza berisiko secara revolusioner mengguncang stabilitas rezim-rezim reaksioner Arab (termasuk di Arab Saudi, Mesir, dan terutama Yordania), Biden menegaskan bahwa dukungannya terhadap Israel “kokoh tak tergoyahkan.” Netanyahu pun berulang kali memanfaatkan kepercayaan buta ini, dengan terus mendorong eskalasi menuju perang regional. Selain pembantaian genosida di Gaza, ia meluncurkan invasi darat ke Lebanon, serangan udara ke Iran, Yaman, dan Suriah, serta kemudian invasi darat ke Suriah.
Meskipun motivasi utama Netanyahu untuk memperluas konflik ke Iran adalah demi keselamatan politiknya karena problem-problem yang dia hadapi di dalam negeri, tampak jelas bahwa perang terbatas 12 hari antara Israel dan Iran Juni lalu memang mendapat dukungan yang lebih luas di kalangan kelas penguasa Israel. Penguatan rezim Iran di kawasan tersebut selama 20 tahun terakhir dipandang oleh kaum borjuis Zionis sebagai ancaman bagi Israel. Namun, Iran berada dalam posisi yang lebih rapuh di kawasan tersebut dengan runtuhnya rezim Al-Assad di Suriah dan dengan melemahnya Hizbullah serta Hamas. Dengan demikian, perang mini yang dapat menghancurkan program nuklir Iran, atau bahkan menggulingkan rezim tersebut, merupakan tujuan yang dapat didukung oleh kelas penguasa Israel. Pada akhirnya, Israel gagal mencapai tujuan ini, dan terulangnya konfrontasi militer baru antara keduanya hanyalah masalah waktu.
Runtuhnya rezim Assad di Suriah secara tiba-tiba dan tak terduga kembali mengubah perimbangan kekuatan di kawasan ini. Turki, meskipun hanya kekuatan kapitalis kecil dalam skala ekonomi global, memiliki ambisi besar di tingkat regional. Erdogan dengan cerdik memanfaatkan pertentangan antara imperialisme AS dan Rusia untuk kepentingannya sendiri.
Menyadari bahwa Iran dan Rusia, yang pernah membuat kesepakatan dengannya di Suriah pada 2016, sedang sibuk di tempat lain (Rusia di Ukraina dan Iran di Lebanon), Erdogan memutuskan untuk mendukung serangan kelompok jihad HTS dari Idlib. Secara mengejutkan, serangan ini memicu runtuhnya rezim Suriah secara total. Ternyata, tingkat kehancuran internal rezim Suriah akibat sanksi ekonomi, korupsi, dan sektarianisme jauh lebih parah dari yang diperkirakan. Wilayah Suriah kini dipecah-belah, yang hanyalah kelanjutan dari lebih dari 100 tahun campur tangan imperialisme sejak Perjanjian Sykes-Picot.
Pada akhirnya, perdamaian di Timur Tengah tak akan pernah tercapai selama masalah kebangsaan Palestina belum terselesaikan. Namun ini tak mungkin terwujud di bawah sistem kapitalisme. Kepentingan kelas penguasa Zionis di Israel—yang didukung oleh kekuatan imperialis terkuat di dunia—tidak memberi ruang bagi terbentuknya tanah air sejati bagi rakyat Palestina, apalagi bagi hak kembali jutaan pengungsi.
Dari sudut pandang militer semata, rakyat Palestina tidak mungkin mengalahkan Israel—sebuah kekuatan kapitalis imperialis modern yang memiliki teknologi militer tercanggih dan dinas intelijen yang tak tertandingi. Israel juga sepenuhnya didukung oleh imperialisme AS.
Lantas, kekuatan apa lagi yang bisa diandalkan oleh rakyat Palestina? Tidak ada kepercayaan yang dapat diberikan kepada rezim-rezim reaksioner Arab, yang hanya sebatas mengumbar retorika soal perjuangan Palestina, namun nyatanya terus mengkhianatinya dan bekerja sama dengan Israel serta kekuatan imperialis di setiap langkah.
Satu-satunya sahabat sejati bagi rakyat Palestina dapat ditemukan di jalanan Arab, yaitu massa tertindas dari kalangan buruh, tani, pedagang kecil, serta kaum miskin kota dan desa. Namun tugas mendesak mereka adalah melawan dan menumbangkan kelas penguasa reaksioner di negeri mereka sendiri. Ini mengajukan problem menghapus kapitalisme dengan mengekspropriasi kaum tuan tanah, bankir, dan kapitalis. Tanpa itu, revolusi di Afrika Utara dan Timur Tengah tak akan pernah berhasil.
Ada kelas buruh yang kuat di kawasan ini, terutama di Mesir dan Turki, juga di Arab Saudi, negara-negara Teluk, dan Yordania. Sebuah pemberontakan yang berhasil di salah satu negara tersebut, yang membawa kelas pekerja ke tampuk kekuasaan, akan mengubah perimbangan kekuatan secara menyeluruh. Ini akan menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi pembebasan rakyat Palestina, sekaligus membuka jalan bagi perang revolusioner melawan Israel, yang pasti akan mengalir dari keseluruhan situasi tersebut.
Negara Israel dan kelas penguasa Zionisnya hanya dapat dikalahkan dengan memecah populasi Israel berdasarkan garis kelas. Untuk saat ini, kemungkinan terjadinya perpecahan kelas di Israel tampak masih jauh. Namun, peperangan dan konflik yang terus-menerus pada akhirnya bisa membuat sebagian rakyat Israel menyadari bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah melalui penyelesaian yang adil atas masalah kebangsaan Palestina.
Tanpa perspektif mentransformasikan masyarakat secara sosialis dan revolusioner, perang demi perang yang dilancarkan oleh rezim reaksioner dengan kekuatan imperialis di balik layar tidak akan menghasilkan solusi apa pun. Selama imperialisme tetap berkuasa, gencatan senjata dan kesepakatan damai hanya akan menjadi jeda sementara sebelum meletusnya perang-perang baru. Namun, ketidakstabilan umum yang menjadi sebab sekaligus akibat dari perang akan menciptakan kondisi bagi bangkitnya gerakan revolusioner massa di periode yang akan datang.
Revolusi Palestina hanya akan menang sebagai revolusi sosialis dan sebagai bagian dari pemberontakan umum kaum buruh dan tani miskin melawan rezim-rezim reaksioner di kawasan tersebut—jika tidak, maka ia tak akan menang sama sekali. Negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara memiliki sumber daya raksasa yang belum tergarap dan seharusnya mampu menjamin kehidupan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Namun, alih-alih demikian, seluruh sejarah Timur Tengah dan Afrika Utara pasca kemerdekaan formal dari kekuasaan imperialisme justru menjadi mimpi buruk berkepanjangan bagi mayoritas rakyatnya. Kelas borjuasi telah terbukti tidak mampu menyelesaikan satu pun dari persoalan-persoalan mendasar yang ada.
Peran yang sangat merusak telah dimainkan oleh kaum Stalinis yang mendasarkan strategi mereka pada teori “dua tahap” yang keliru, yang secara artifisial memisahkan revolusi proletar dari apa yang mereka sebut sebagai revolusi borjuis-demokratik. Teori reaksioner ini telah menyebabkan kekalahan demi kekalahan yang tragis, membuka jalan bagi bangkitnya rezim-rezim diktator yang opresif serta kegilaan fundamentalisme agama di berbagai negeri. Hanya kemenangan revolusi sosialis yang mampu mengakhiri mimpi buruk ini.
Hanya sebuah federasi sosialis yang dapat menyelesaikan masalah kebangsaan secara tuntas. Dalam kerangka federasi semacam itu, seluruh rakyat—baik Palestina, Yahudi Israel, maupun Kurdi, Armenia, dan bangsa-bangsa lainnya—akan memiliki hak untuk hidup damai. Potensi ekonomi kawasan ini dapat dimaksimalkan melalui perencanaan produksi sosialis bersama. Pengangguran dan kemiskinan akan menjadi masa lalu. Hanya di atas dasar itulah kebencian nasional dan religius yang lama dapat dilampaui. Mereka akan menjadi seperti kenangan buruk dari mimpi yang telah usai.
Inilah satu-satunya harapan yang nyata bagi bangsa-bangsa Timur Tengah
Perlombaan senjata dan militerisme
Secara historis, setiap perubahan besar dalam perimbangan kekuatan antar berbagai negara imperialis biasanya diselesaikan lewat perang, terutama dua perang dunia di abad ke-20. Kini, keberadaan senjata nuklir membuat kemungkinan terjadinya perang dunia terbuka dalam waktu dekat menjadi sangat kecil.
Kaum kapitalis berperang demi memperebutkan pasar, ladang investasi, dan zona pengaruh. Perang dunia di masa kini hanya akan membawa kehancuran total atas infrastruktur dan kehidupan, tanpa ada satu kekuatan pun yang diuntungkan. Perang dunia semacam itu hanya mungkin terjadi jika ada seorang pemimpin Bonapartis yang gila, yang berkuasa di negara nuklir utama. Itu pun hanya mungkin terjadi setelah kekalahan telak kelas pekerja. Ini bukanlah perspektif yang ada di depan kita.
Meskipun begitu, konflik antar kekuatan imperialis, yang mencerminkan perseteruan untuk membagi ulang dunia, mendominasi situasi dunia hari ini. Ini terekspresikan dalam berbagai perang regional yang menimbulkan kehancuran besar dan menewaskan puluhan ribu orang, serta dalam ketegangan perdagangan dan diplomasi yang terus meningkat. Tahun lalu mencatat jumlah perang terbanyak sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua.
Ini telah memicu perlombaan senjata yang baru, menguatnya militerisme di negara-negara Barat, serta meningkatnya tekanan untuk membangun kembali, mempersenjatai ulang, dan memodernisasi angkatan bersenjata di berbagai belahan dunia. AS diperkirakan akan menghabiskan sekitar $1,7 triliun dalam 30 tahun ke depan untuk memperbarui arsenal nuklirnya. Kini, mereka juga telah memutuskan untuk kembali menempatkan rudal jelajah di Jerman untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin.
Semua negara anggota NATO kini berada di bawah tekanan kuat untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka. Cina telah mengumumkan kenaikan belanja militer sebesar 7,2 persen. Akibat perang, pada 2024 pengeluaran militer Rusia melonjak 40 persen, mencapai 32 persen dari total belanja negara dan 6,68 persen dari PDB. Secara global, pengeluaran militer pada 2023 mencapai $2,44 triliun—naik 6,8 persen dari tahun sebelumnya. Ini adalah kenaikan terbesar sejak 2009 sekaligus tingkat tertinggi yang pernah tercatat.
Angka-angka ini mencengangkan, belum lagi tenaga kerja dan perkembangan teknologi yang terbuang sia-sia. Padahal semuanya bisa digunakan untuk keperluan sosial yang mendesak. Inilah poin yang harus terus ditekankan kaum revolusioner dalam propaganda dan agitasi kita.
Adalah penyederhanaan berlebihan jika dikatakan bahwa kaum kapitalis memulai perlombaan senjata baru demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenyataannya, belanja militer secara inheren memiliki dampak inflasioner, dan pengaruhnya terhadap ekonomi hanya bersifat jangka pendek dan akan terimbangi oleh pemangkasan di sektor-sektor lain. Dalam jangka panjang, belanja militer menjadi beban bagi ekonomi produktif karena menyedot nilai lebih. Sesungguhnya, yang mendorong lonjakan belanja militer adalah konflik antar kekuatan imperialis untuk membagi ulang dunia. Kapitalisme pada tahap imperialisnya niscaya mengarah ke benturan antar kekuatan besar dan, pada akhirnya, perang.
Perjuangan melawan militerisme dan imperialisme telah menjadi isu sentral di zaman kita. Kita dengan tegas menentang perang imperialis dan imperialisme, namun kita bukan kaum pasifis. Kita harus menekankan bahwa satu-satunya cara untuk menjamin perdamaian adalah dengan menghapus sistem kapitalisme yang melahirkan perang.
Persenjataan kembali kapitalisme Eropa
Dalam kasus Eropa, dorongan menuju militerisme dan peningkatan belanja senjata merupakan akibat dari menguatnya imperialisme Rusia yang keluar sebagai pemenang dari perang di Ukraina, mundurnya dukungan militer AS, serta upaya kekuatan-kekuatan Eropa untuk menunjukkan bahwa mereka masih memiliki peran di panggung dunia.
Pengeluaran militer Rusia untuk tahun 2024 mencapai sekitar 13,1 triliun rubel (setara $145,9 miliar), atau sekitar 6,68 persen dari PDB. Angka ini menunjukkan kenaikan lebih dari 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika disesuaikan dengan paritas daya beli, nilainya mendekati $462 miliar.
Sementara itu, Eropa telah meningkatkan belanja militernya secara signifikan sebesar 50 persen secara nominal sejak 2014, mencapai total kolektif sebesar $457 miliar pada 2024. Dalam hal ini, penyesuaian angka Rusia berdasarkan paritas daya beli menjadi relevan, karena yang dibandingkan adalah jumlah tank, artileri, atau amunisi yang bisa dibeli oleh setiap dolar, baik di Rusia maupun di Eropa. Dengan kata lain, Rusia mengungguli seluruh Eropa dalam hal pengeluaran militer.
Rusia juga melampaui seluruh NATO, termasuk AS, dalam hal produksi amunisi, roket, dan tank. Menurut perkiraan intelijen NATO, Rusia memproduksi sekitar 3 juta peluru artileri per tahun. Seluruh NATO, termasuk AS, hanya mampu memproduksi sekitar 1,2 juta—kurang dari setengah jumlah produksi Rusia.
Selain itu, perang di Ukraina telah sepenuhnya mengubah metode peperangan. Seperti biasanya, perang menjadi ajang uji coba teknologi dan teknik baru dalam kondisi nyata, yang kemudian berkembang pesat dan langsung disesuaikan dengan kebutuhan di medan tempur. Pasukan yang terlibat pun dipaksa untuk segera mengembangkan metode dan taktik untuk menghadapinya. Kita telah menyaksikan penggunaan besar-besaran drone (udara, darat, dan laut), teknik pengintaian elektronik, serta sistem pengacauan sinyal, dan sebagainya.
Satu-satunya angkatan bersenjata yang memiliki pengalaman langsung dengan metode-metode baru ini adalah Ukraina dan Rusia. Barat tertinggal jauh dalam semua bidang tersebut. Perang di Ukraina telah secara drastis menggeser perimbangan kekuatan militer ke Rusia.
Ini bukan berarti Rusia memiliki kepentingan untuk menginvasi Eropa. Ancaman ini telah dibesar-besarkan secara masif oleh kelas penguasa demi membenarkan lonjakan besar dalam belanja militer dan untuk meredam penolakan publik. Rusia tidak memiliki kepentingan untuk menginvasi Ukraina barat—yang akan menjadi upaya yang jauh lebih mahal dan membebani dibandingkan kampanye militer Rusia saat ini—apalagi untuk menyerang negara-negara anggota NATO.
Ancaman dari sudut pandang kapitalisme Eropa sebenarnya bukan invasi Rusia atau konflik militer terbuka antara pasukan Rusia dan Eropa. Perang seperti itu akan sangat mahal bagi kedua belah pihak. Selain itu, konflik semacam itu akan melibatkan dua kekuatan yang sama-sama memiliki senjata nuklir, suatu kemungkinan yang sangat berbahaya.
Ancaman nyata bagi imperialisme Eropa yang tengah mengalami krisis adalah ditinggalkan atau dipinggirkan oleh kekuatan imperialisme terbesar di dunia, sementara di saat yang sama mereka bertetangga dengan kekuatan imperialis lain yang muncul dari perang saat ini dengan posisi yang jauh lebih kuat.
Rusia memiliki pengaruh besar, baik secara militer maupun dalam hal sumber daya energi, dan sudah mulai memainkan peran yang kuat dalam percaturan politik Eropa. Negara-negara seperti Hungaria dan Slovakia telah pecah dari orientasi Atlantik kekuatan-kekuatan dominan di Eropa. Di negara-negara lain, kekuatan-kekuatan politik yang tengah bangkit juga bergerak ke arah serupa, dalam berbagai tingkatan, seperti di Jerman, Austria, Rumania, Ceko, dan Italia.
Yang dipertahankan oleh imperialisme Eropa bukanlah kehidupan dan rumah rakyat Eropa, melainkan profit perusahaan multinasionalnya dan ambisi imperialis yang rakus dari kelas penguasa kapitalisnya. Rusia merupakan saingan kapitalisme Jerman di Eropa Timur dan Tengah. Rusia juga merupakan saingan imperialisme Prancis di Afrika.
Krisis panjang yang melanda kapitalisme Eropa berarti bahwa begitu perlindungan dari AS dicabut, Eropa tidak akan mampu berdiri sendiri. Kawasan ini terancam terpecah oleh kepentingan-kepentingan AS, Rusia, dan Cina yang menyainginya. Kecenderungan sentrifugal semakin menguat; tiap-tiap kelas kapitalis mulai menegaskan kepentingan nasionalnya masing-masing. Tidak bisa dikesampingkan bahwa pada akhirnya kecenderungan ini dapat membawa pada perpecahan Uni Eropa.
Ekonomi dunia: dari globalisasi menuju perang dagang dan proteksionisme
Pengenaan tarif luas oleh Trump pada 2 April menandai titik balik dalam perekonomian dunia. Namun, proses melambatnya globalisasi dan pergeseran menuju proteksionisme sebenarnya telah dimulai lebih awal.
Resesi global tahun 2008 menjadi titik balik dalam krisis kapitalisme. Pada periode sebelum krisis tersebut, ekonomi dunia tumbuh sekitar 4 persen per tahun. Antara krisis 2008 dan guncangan pandemi 2020, pertumbuhan hanya mencapai 3 persen. Bahkan sebelum tarif yang diberlakukan Trump, laju pertumbuhan sudah menurun ke sekitar 2 persen, tingkat terendah dalam tiga dekade terakhir.
Faktanya, ekonomi dunia tak pernah benar-benar pulih dari resesi 2008. Saat itu sektor perbankan menerima bail-out masif, sebuah langkah putus asa untuk menyelamatkan sektor finans. Negara-negara di Eropa menanggung utang dan defisit anggaran yang sangat besar, sehingga terpaksa menerapkan kebijakan penghematan. Kelas pekerjalah yang akhirnya dipaksa menanggung beban dari krisis kapitalisme ini.
Kelas penguasa, dalam kepanikan, merespons dengan program pelonggaran kuantitatif besar-besaran, yaitu menyuntikkan sejumlah besar uang ke dalam perekonomian, serta menurunkan suku bunga secara drastis hingga nol atau bahkan negatif. Namun langkah ini tidak menghasilkan pemulihan, karena rumah tangga juga terbebani oleh utang. Tidak ada bidang investasi produktif di sektor produksi, sehingga kelebihan likuiditas justru memicu gelembung harga saham, mata uang kripto, dan sebagainya.
Kebijakan penghematan yang diterapkan oleh pemerintah di berbagai negara memicu gerakan massa di seluruh dunia pada 2011: revolusi di Afrika Utara dan Timur Tengah, gerakan Occupy di AS, gerakan ‘indignados’ di Spanyol, gerakan lapangan Syntagma di Yunani, dan lain-lain.
Ini mencerminkan ketidakpuasan yang semakin meluas terhadap sistem kapitalis yang membebankan biaya penyelamatan bank kepada kelas pekerja, dan menyebabkan merosotnya kepercayaan terhadap seluruh institusi borjuis. Perubahan kesadaran ini—sebagaimana telah kita lihat—mendapatkan ekspresi politiknya dalam kebangkitan reformisme kiri tipe baru sekitar tahun 2015: Podemos, Syriza, Corbyn, Mélenchon, Sanders, dan ‘pemerintahan-pemerintahan progresif’ di Amerika Latin.
Massa tertarik kepada mereka karena oposisi mereka yang tampak radikal terhadap kebijakan penghematan. Namun proses itu terhenti ketika keterbatasan reformisme terungkap: melalui pengkhianatan pemerintahan Syriza di Yunani; dukungan Sanders terhadap Clinton; runtuhnya Corbynisme; serta bergabungnya Podemos ke dalam pemerintahan koalisi di Spanyol.
Di negara-negara yang didominasi oleh imperialisme, kita menyaksikan pemberontakan dan pergolakan massa (di Puerto Rico, Haiti, Ekuador, Chili, Sudan, Kolombia, dan lain-lain). Mobilisasi besar-besaran dalam perjuangan untuk republik di Catalonia pada 2017 dan 2019 juga merupakan bagian dari arus umum yang sama.
Namun, ketiadaan kepemimpinan berarti tak satu pun dari gerakan-gerakan itu berujung pada penggulingan kapitalisme, yang sebenarnya memungkinkan.
Pandemi COVID-19 pada 2020 menjadi guncangan eksternal bagi perekonomian global pada saat ia sudah berada di ambang resesi baru (karena belum pernah benar-benar pulih dari krisis 2008). Inilah yang akhirnya mendorong ekonomi dunia ke tubir jurang.
Sekali lagi, dalam kepanikan, kelas penguasa mengambil langkah-langkah putus asa untuk mencegah ledakan sosial. Di negara-negara kapitalis maju, kaum pekerja dibayar oleh negara untuk tetap tinggal di rumah, dengan biaya yang sangat besar bagi keuangan publik, yang sebelumnya pun sudah terbebani utang akibat krisis sebelumnya.
Selama 15 tahun terakhir, berbagai upaya untuk menggerakkan kembali ekonomi dunia melalui suntikan likuiditas besar-besaran seperti quantitative easing, suku bunga super rendah (2009–2021), dan langkah-langkah panik lainnya, telah gagal total untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berarti. Kaum kapitalis, meskipun dibanjiri uang, tetap enggan berinvestasi.
Faktor kuncinya adalah bahwa kaum kapitalis membutuhkan pasar untuk menjual produk mereka guna merealisasikan profit. Akumulasi utang yang sangat besar membuat rumah tangga dan dunia usaha tidak mampu mendorong konsumsi.
Total utang global—yang mencakup rumah tangga, negara, dan korporasi—telah mencapai sekitar $313 triliun, atau 330 persen dari PDB dunia, naik dari sekitar $210 triliun satu dekade lalu.
Utang mencerminkan kenyataan bahwa batas-batas sistem ini telah didorong hingga titik patahnya dan kini menjadi penghalang besar bagi perkembangan lebih lanjut. Kombinasi antara tingginya utang negara dan naiknya suku bunga telah membuat sejumlah negara yang didominasi jatuh ke jurang krisis. Akan ada lebih banyak lagi yang menyusul.
Pandemi juga berdampak pada kesadaran massa, membongkar ketidakmampuan sistem kapitalis yang berlandaskan laba pribadi dalam menangani darurat kesehatan, serta menunjukkan bagaimana profit lebih diutamakan daripada nyawa manusia oleh raksasa farmasi.
Pada 1990-an dan 2000-an, ekonomi dunia memang mengalami pertumbuhan tertentu, meskipun laju pertumbuhannya jauh lebih rendah dibandingkan masa ledakan ekonomi pasca-perang antara 1948 hingga 1973, ketika kekuatan-kekuatan produktif berkembang pesat. Pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh perluasan kredit dan apa yang disebut sebagai ‘globalisasi’. Melalui mekanisme tersebut, sistem kapitalisme mampu melampaui batas-batas alaminya, meski hanya secara parsial dan untuk jangka waktu terbatas. Globalisasi di sini berarti meluasnya perdagangan dunia, penghapusan hambatan tarif, turunnya harga barang-barang konsumsi, serta terbukanya pasar-pasar dan ladang-ladang investasi baru di negeri-negeri yang berada di bawah dominasi imperialisme.
Kini, semua faktor tersebut telah berbalik menjadi kebalikannya. Perluasan kredit dan likuiditas telah berubah menjadi gunung utang.
Globalisasi (ekspansi perdagangan dunia) adalah salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi setelah runtuhnya Stalinisme di Rusia serta restorasi kapitalisme di Cina yang kemudian terintegrasi ke dalam ekonomi dunia. Namun kini kita menyaksikan tarif dan perang dagang di antara blok-blok ekonomi besar seperti Cina, Uni Eropa, dan AS, masing-masing berusaha menyelamatkan perekonomian sendiri dengan mengorbankan yang lain.
Pada 1991, perdagangan dunia hanya mencakup sekitar 35 persen dari PDB global, angka yang tidak banyak berubah sejak 1974. Namun setelah itu, perdagangan global mengalami lonjakan tajam hingga mencapai puncaknya 61 persen pada 2008. Sejak saat itu angka tersebut stagnan.
Sebelum gelombang tarif baru-baru ini diberlakukan, IMF memperkirakan bahwa perdagangan dunia hanya akan tumbuh sekitar 3,2 persen per tahun dalam jangka menengah—jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 4,9 persen pada periode 2000 hingga 2019. Perdagangan dunia tak lagi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi seperti sebelumnya. Kini, seluruh proses itu justru bergerak mundur.
Kecenderungan menuju proteksionisme, yang merupakan gejala dari krisis kapitalisme, telah menguat selama beberapa waktu. Pada 2023, pemerintah di seluruh dunia memberlakukan 2.500 kebijakan proteksionis—mulai dari insentif pajak, subsidi yang ditargetkan, hingga pembatasan perdagangan—jumlah ini tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan lima tahun sebelumnya.
Selama masa kepresidenan pertama Trump, AS mengambil sikap proteksionis yang agresif, tidak hanya terhadap Cina, tetapi juga terhadap UE, sebuah kebijakan yang kemudian dilanjutkan oleh Biden. Biden memberlakukan serangkaian undang-undang (CHIPS, Inflation Reduction Act, dll.) serta kebijakan-kebijakan yang secara jelas menguntungkan produksi dalam negeri dengan mengorbankan impor dari negara lain. Sejak Trump terpilih kembali, seluruh kecenderungan menuju proteksionisme meningkat tajam dan kini telah berkembang menjadi perang dagang terbuka.
Kebangkitan proteksionisme dan implementasi tarif akan menjadi satu guncangan lagi bagi perekonomian global, setelah guncangan dari pandemi dan perang Ukraina sebelumnya. Ini akan semakin memperkuat tekanan inflasi, di atas tekanan dari pembiayaan defisit, belanja militer, dan perubahan demografi, serta memperlemah permintaan pasar.
Situasi ekonomi sangatlah penuh dengan ketidakpastian. Ada potensi resesi besar di periode mendatang, dan bahkan mungkin depresi.
Tarif Trump
Belokan tajam Trump menuju proteksionisme dan perang dagang terbuka dengan Cina adalah gejala dari krisis kapitalisme AS. Ini merupakan pengakuan bahwa perusahaan manufaktur AS tak mampu bersaing di pasar global tanpa campur tangan negara. Pada saat yang sama, proteksionisme menjadi cara bagi negara-negara kapitalis yang bersaing untuk memindahkan beban krisis ke negara lain. ‘America First’ pada dasarnya berarti ‘yang lain belakangan’.
Dengan berbagai langkah proteksionis, Trump mengejar beberapa tujuan sekaligus. 1) Menerapkan tarif atas impor barang-barang manufaktur agar pekerjaan manufaktur kembali ke AS. 2) Menghentikan kebangkitan Cina sebagai rival ekonomi. 3) menggunakan pendapatan dari tarif untuk mengurangi defisit anggaran AS, sehingga ia dapat mempertahankan kebijakan pemotongan pajak. 4) Menjadikan tarif sebagai alat tawar dalam negosiasi dengan negara lain demi memperoleh konsesi politik dan ekonomi.
Memang benar bahwa beberapa perusahaan telah mengumumkan rencana investasi di AS untuk menghindari tarif dan mempertahankan akses ke pasar AS, yang merupakan pasar konsumen terbesar di dunia. Namun, pembangunan pabrik-pabrik baru adalah proses yang memakan waktu, dan dampak jangka pendek dari tarif terhadap rantai pasokan kemungkinan besar akan mengimbangi potensi keuntungan dalam bentuk penciptaan lapangan kerja baru.
Hari ini, setelah tiga dekade globalisasi, rantai pasokan telah menjadi sangat panjang, dengan berbagai negara mengambil peran khusus dalam tiap tahap proses produksi. Industri otomotif di AS, Meksiko, dan Kanada sangat terintegrasi, dengan komponen yang melintasi batas negara berkali-kali sebelum dirakit secara bertahap di berbagai tempat. Setiap upaya untuk memendekkan jalur pasokan akan langsung mengguncang perekonomian, menyebabkan kenaikan harga produk, atau bahkan kelangkaan dalam beberapa kasus. Ketidakpastian akibat penggunaan tarif sebagai alat tawar oleh Trump juga berdampak negatif terhadap keputusan investasi.
Ekonomi AS dan Cina terkait erat dan bergantung satu sama lain. Bagi AS, saat ini belum ada pengganti yang layak untuk sektor manufaktur Cina—produk-produk Cina tidak hanya terjangkau tetapi juga berkualitas tinggi. Upaya untuk mengusirnya dari pasar AS, seperti yang didorong oleh Trump, kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian ekonomi yang serius jauh sebelum ada tanda-tanda kebangkitan industri manufaktur dalam negeri, jika hal itu akan terjadi sama sekali.
Setiap upaya untuk melepaskan keterkaitan ini akan membawa dampak buruk bagi perekonomian dunia secara keseluruhan. Perlu diingat bahwa setelah krisis 1929, kecenderungan umum menuju proteksionisme justru mendorong dunia dari resesi ekonomi menuju depresi. Volume perdagangan global merosot hingga 25 persen antara tahun 1929 dan 1933, dan sebagian besar penurunan itu merupakan akibat langsung dari meningkatnya hambatan perdagangan.
Selama seluruh periode, globalisasi memungkinkan sistem kapitalisme melampaui batas-batas negara bangsa secara parsial dan sementara. Proteksionisme kini menjadi upaya untuk memaksa kembali kekuatan-kekuatan produktif masuk ke dalam batas-batas sempit negara bangsa, demi menegaskan kembali dominasi imperialisme AS atas negara-negara lain. Seperti yang telah diperingatkan Trotsky pada 1930-an:
“Di kedua sisi Atlantik, tak sedikit tenaga mental dihamburkan untuk memecahkan persoalan yang mustahil: bagaimana mengembalikan buaya ke dalam telur ayam. Nasionalisme ekonomi ultra-modern ditakdirkan gagal karena wataknya yang reaksioner; ia menghambat dan merendahkan kekuatan produktif manusia.” (Nationalism and Economic Life, 1934)
Sebagaimana telah diduga, para pemimpin serikat buruh di berbagai negara merespons proteksionisme dengan berbaris rapi di belakang kelas penguasa mereka sendiri, dengan dalih ‘membela lapangan kerja’ di negara mereka sendiri. Kaum revolusioner harus berpijak pada posisi kelas yang independen dan internasionalis. Musuh kelas buruh adalah kelas penguasa—terutama yang ada di negeri sendiri—bukan buruh di negeri lain.
Dihadapkan dengan penutupan pabrik, kita harus memajukan slogan okupasi pabrik. Alih-alih terus menyelamatkan perusahaan swasta dengan dana negara, kita menuntut agar kapitalis membuka pembukaan mereka dan menasionalisasi perusahaan mereka di bawah kendali buruh. Jika pabrik-pabrik tak bisa meraup profit di bawah sistem kapitalisme, maka mereka harus disita dan dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang berguna, di bawah rencana produksi yang demokratis. Baik perdagangan bebas maupun proteksionisme bukanlah demi kepentingan kelas buruh. Keduanya hanyalah kebijakan ekonomi berbeda yang digunakan kelas penguasa untuk menangani krisis kapitalisme. Alternatif kita adalah menggulingkan sistem yang melahirkan krisis tersebut.
Krisis legitimasi institusi-institusi borjuis
Krisis kapitalisme, sebagai sistem ekonomi yang kini tak lagi mampu mengembangkan kekuatan produktif secara berarti, dan karena itu tak sanggup lagi meningkatkan standar hidup dari generasi ke generasi, telah melahirkan krisis legitimasi yang dalam dan terus membesar terhadap seluruh institusi politik borjuis.
Ada polarisasi kekayaan yang begitu mencolok, di mana segelintir miliarder terus menumpuk aset mereka, sementara semakin banyak kaum buruh yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dihantam oleh pemotongan anggaran, daya beli upah yang tergerus inflasi, kenaikan tagihan listrik, krisis perumahan, dan sebagainya.
Media, politisi, partai-partai status-quo, parlemen, dan lembaga peradilan semuanya dipandang sebagai perwakilan segelintir elite yang berprivilese, yang membuat keputusan demi kepentingan sempit dan egois mereka sendiri, alih-alih memenuhi kebutuhan rakyat banyak.
Hal ini sangat penting karena di masa-masa normal kelas penguasa berkuasa melalui lembaga-lembaga tersebut, yang umumnya diterima dan dipandang sebagai representasi dari ‘kehendak mayoritas’. Kini, semua itu mulai dipertanyakan oleh semakin banyak lapisan masyarakat.
Alih-alih mekanisme normal demokrasi borjuis yang berfungsi meredam kontradiksi kelas, gagasan tentang aksi langsung untuk mencapai tujuan kini semakin diterima. Sebuah artikel di Le Monde memperingatkan Macron di Prancis bahwa dengan mencegah partai yang memiliki jumlah anggota parlemen terbanyak untuk membentuk pemerintahan, ia berisiko membuat rakyat menyimpulkan bahwa pemilu tidak ada gunanya. Di AS, satu dari empat orang percaya bahwa kekerasan politik bisa dibenarkan demi “menyelamatkan” negara, naik dari 15 persen setahun sebelumnya. Dalam hal ini, penting untuk menyoroti meningkatnya kecenderungan teroris di Amerika Serikat. Dalam beberapa bulan saja, kita menyaksikan dugaan pembunuhan CEO United Healthcare oleh Luigi Mangione, sebagai cara untuk mengecam korporasi-korporasi layanan kesehatan swasta, pembunuhan dua karyawan kedutaan Israel di Washington oleh seorang aktivis pro-Palestina, dan pembunuhan seorang anggota kongres dari Partai Demokrat dan suaminya di Minnesota, serta serangan lain pada hari yang sama terhadap seorang senator dari Partai Demokrat, juga di Minnesota. Serangan terakhir tersebut dilakukan oleh kaum fanatik sayap kanan. Fenomena terorisme politik yang berulang di AS ini mencerminkan keresahan yang mendalam dan kontradiksi yang sangat besar yang mengguncang masyarakat Amerika.
Munculnya para demagog anti-kemapanan merupakan tanda dari terkikisnya legitimasi demokrasi borjuis dan lembaga-lembaganya. Dahulu, ketika pemerintahan sayap-kanan kehilangan kepercayaan, biasanya akan digantikan oleh pemerintahan ‘kiri’ sosial-demokrat, dan ketika pemerintahan ‘kiri’ ini terdiskreditkan, ini akan digantikan oleh pemerintahan konservatif. Namun, proses itu kini tidak lagi berlangsung secara otomatis.
Sebaliknya, yang terjadi adalah ayunan tajam ke kiri dan ke kanan, yang dalam pemberitaan media sering digambarkan sebagai pertumbuhan ‘ekstremisme politik’. Namun, menguatnya kutub-kutub ekstrem dalam politik hanyalah cerminan dari proses polarisasi sosial dan politik, yang pada gilirannya mencerminkan semakin tajamnya perjuangan kelas. Runtuhnya politik tengah inilah yang membuat kelas penguasa ketakutan. Mereka ingin menghentikannya dengan segala cara, tetapi mereka tak berdaya untuk melakukannya.
Alasannya tidak sulit dipahami. Pemerintahan kiri maupun kanan saat ini pada dasarnya menjalankan kebijakan yang sama: pemotongan anggaran dan penghematan. Hal ini menyebabkan politik secara umum kehilangan kredibilitas, diikuti oleh meningkatnya angka golput dan kemunculan berbagai partai alternatif ketiga yang sering kali bersifat sementara. Para demagog kanan berhasil memanfaatkan suasana anti-kemapanan yang ada, juga karena ketidakmampuan ‘kiri’ resmi untuk menawarkan alternatif yang nyata.
Kepanikan kaum kapitalis liberal tentang ‘bahaya fasisme’ dan ‘ancaman dari sayap kanan’ digunakan untuk menggalang dukungan untuk politik minus malum, bahwa ‘kita semua harus bersatu membela demokrasi’, bahwa kita harus ‘membela Republik’. Padahal, di banyak negara saat ini, justru pemerintahan liberal-lah yang melancarkan serangan terhadap kelas pekerja, mengobarkan militerisme, serta merongrong hak-hak demokratis.
Trump disebut ‘fasis’ atau ‘otoriter’ ketika ia menjalankan kebijakan mengusir kaum imigran karena dukungan mereka terhadap Palestina. Lalu bagaimana dengan pemerintah negara-negara Eropa yang telah melarang dan dengan brutal merepresi demonstrasi-demonstrasi pro-Palestina? Bagaimana dengan Jerman dan Prancis di mana kaum imigran ditangkap dan dideportasi karena menyuarakan dukungan terhadap Palestina? Apa sebutan untuk mereka?
Kaum liberal menggunakan lembaga peradilan untuk memberlakukan langkah-langkah yang sepenuhnya tidak demokratis guna melarang politisi yang tidak mereka sukai ikut dalam pemilu (seperti Le Pen di Prancis) atau, seperti di Rumania, membatalkan hasil pemilu jika hasilnya tidak mereka sukai! Lalu mereka berbalik menyerukan ‘persatuan untuk membela demokrasi’ dan membangun ‘cordon sanitare terhadap sayap kanan’.
Ini adalah kebijakan yang kriminal, yang justru memperkuat dukungan terhadap para demagog sayap kanan yang kemudian dapat berkata: ‘Lihat, kanan dan kiri, semuanya sama saja.’
Kaum revolusioner akan menentang setiap kebijakan reaksioner yang merugikan kelas buruh dan hak-hak demokratis. Namun, adalah kesalahan besar jika kita terlihat mendukung ‘demokrasi’ secara umum—karena itu berarti mendukung negara kapitalis—atau jika kita mencampur aduk panji kita dengan kaum liberal saat mereka menyerang para demagog sayap kanan.
Pada kenyataannya, daya tarik demagog sayap kanan akan terungkap sebagai ilusi begitu bertabrakan dengan fakta. Trump kini berkuasa di AS dan sudah mengutarakan banyak janji. Dia menunggangi harapan jutaan orang yang percaya ia benar-benar akan ‘Membuat Amerika Hebat Lagi’. Namun itu hanyalah khayalan semata. Bagi massa kelas buruh, ‘Membuat Amerika Hebat Lagi’ berarti mendapatkan pekerjaan layak dengan upah baik. Ini berarti mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sampai sampai akhir bulan tanpa terpaksa mengambil dua atau tiga pekerjaan, atau bahkan menjual plasma darah demi bertahan hidup.
Jutaan rakyat Amerika masih memendam ilusi kuat bahwa Trump akan mengembalikan masa-masa kejayaan AS setelah Perang Dunia II. Namun satu hal yang pasti: itu tidak akan terjadi. Krisis kapitalisme saat ini membuat mustahil kembalinya era keemasan boom ekonomi pascaperang atau dekade 1920-an yang bergemuruh.
Bukan tidak mungkin bahwa beberapa kebijakan—seperti tarif yang mendorong pertumbuhan industri di Amerika dengan mengorbankan negara lain—akan memberi dampak sementara. Banyak orang juga mungkin masih memberi Trump waktu dan kepercayaan. Ia pun bisa memanfaatkan narasi bahwa yang menghalangi jalannya adalah deep state atau ‘negara bayangan’ yang tak membiarkannya merealisasikan kebijakannya.
Namun ketika kenyataan mulai terasa dan ilusi itu runtuh, kemarahan anti-kemapanan yang dulu mendorong Trump ke tampuk kekuasaan bisa dengan cepat berubah arah. Bukan tak mungkin kita akan menyaksikan ayunan pendulum politik yang sama tajam dan mengguncang—kali ini ke arah kiri.
Dalam sebuah artikel berjudul If America Should Go Communist, Trotsky menyinggung watak khas orang Amerika yang ia sebut “energetik dan keras.” Ia mengatakan bahwa, seturut tradisi Amerika, perubahan besar jarang terjadi tanpa keberpihakan yang tegas dan benturan yang keras.
Buruh Amerika dikenal sebagai sosok yang pragmatis dan menuntut hasil konkret. Ia tak segan bertindak demi mencapai tujuan. Farrell Dobbs, pemimpin pemogokan besar Minneapolis Teamster tahun 1934, bergeser dari pendukung Partai Republik langsung menjadi pemimpin Trotskis. Dalam kisahnya tentang pemogokan itu, ia menjelaskan alasannya. Baginya, kaum Trotskis-lah yang menawarkan solusi paling masuk akal dan efektif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi kaum pekerja.
Situasi yang eksplosif: radikalisasi di kalangan muda
Kenyataannya, situasi dunia saat ini sarat dengan potensi revolusioner. Gelombang pemberontakan pada 2019–2020 sempat terhenti sebagian akibat lockdown selama pandemi COVID-19, namun kondisi yang memicunya belum hilang. Pada 2022, pemberontakan di Sri Lanka menjatuhkan presiden ketika massa menyerbu istana kepresidenan. Aksi mogok massal menentang reformasi pensiun di Prancis pada 2023 membuat pemerintah berada di ujung tanduk. Pada 2024, massa di Kenya yang dipimpin oleh kaum muda revolusioner menyerbu parlemen dan memaksa pemerintah membatalkan rancangan undang-undang keuangan. Di Bangladesh, gerakan mahasiswa yang dihadapi dengan represi brutal memicu pemberontakan nasional dan menggulingkan rezim Hasina yang dibenci.
Ciri umum dari semua gerakan ini adalah peran utama yang dimainkan oleh kaum muda. Siapa pun yang berusia di bawah 30 tahun telah menjalani seluruh kehidupan politiknya dalam bayang-bayang krisis 2008, pandemi COVID-19, perang di Ukraina, dan pembantaian di Gaza.
Baru-baru ini, kita menyaksikan gerakan massa besar di Turki, Serbia, dan Yunani. Di Yunani, kemarahan besar terhadap upaya menutup-nutupi bencana kereta api di Tempi, ditambah dengan kemarahan yang telah terakumulasi karena kemelaratan massa yang disebabkan oleh program penghematan permanen dan kebuntuan kapitalisme Yunani, mengarah ke pemogokan umum yang luas dan aksi protes terbesar sejak tumbangnya junta militer pada 1974. Pemogokan yang masif ini, yang melibatkan tidak hanya kelas buruh tetapi juga lapisan masyarakat lainnya (pedagang kecil, dll.), menunjukkan perimbangan kekuatan yang sesungguhnya dalam masyarakat kapitalis modern. Ketika kelas buruh bergerak, ia mampu menarik seluruh lapisan tertindas bersamanya.
Di Serbia, gelombang protes akibat runtuhnya kanopi stasiun Novi Sad telah menciptakan krisis revolusioner, dengan demonstrasi terbesar dalam sejarah negara itu. Mahasiswa memainkan peran menentukan, dengan menduduki universitas, membentuk plenum-plenum (majelis-majelis) mahasiswa dan secara sadar berupaya memperluas gerakan ini ke kelas buruh dan rakyat luas melalui pembentukan zborovi, yaitu majelis-majelis rakyat di kota-kota maupun di sejumlah tempat kerja. Gerakan ini telah bertahan lebih dari 9 bulan, dan setiap usaha dari rejim Vucic untuk menghentikan gerakan ini justru menjadi bumerang dan semakin mendorong maju gerakan ini.
Kedua gerakan ini menyoroti dua ciri utama dari situasi saat ini: potensi kekuatan kelas buruh yang luar biasa serta bobot sosialnya yang dominan di satu sisi, dan kelemahan ekstrem faktor subjektif di sisi lain.
Di samping itu, lapisan kaum muda juga teradikalisasi oleh isu-isu hak demokratis, gerakan massa perempuan melawan kekerasan dan diskriminasi (seperti di Meksiko dan Spanyol), perjuangan untuk hak aborsi (di Argentina, Chile, Irlandia, Polandia), dukungan terhadap pernikahan sesama jenis (Irlandia), serta gerakan massa menentang kekerasan polisi terhadap warga kulit hitam (AS dan Inggris), dan sebagainya.
Krisis iklim juga menjadi faktor yang mendorong radikalisasi generasi muda saat ini, yang dengan sangat kuat—dan memang beralasan—merasakan bahwa jika tidak ada perubahan radikal, kehidupan di Bumi terancam, dan sistem yang ada adalah penyebab utamanya.
Kemunafikan dan standar ganda imperialisme terkait pembantaian di Gaza, apa yang disebut ‘hukum internasional’, serta represi polisi terhadap gerakan solidaritas Palestina telah membuka mata mereka terhadap hakikat negara kapitalis, media kapitalis, dan lembaga-lembaga internasional.
Dalam semua gerakan ini, kita menjumpai beragam gagasan, termasuk feminisme, reformisme, Stalinisme, atau nasionalisme. Tugas kitalah untuk memajukan posisi kelas dan tampik menonjol dengan jelas di tengah lautan kebingungan borjuis kecil. Namun, ini selalu merupakan pertanyaan konkret, dimulai dari gagasan yang kita temui, serta tugas dan pertanyaan yang diajukan oleh gerakan itu sendiri. Tergantung pada keadaan, kita biasanya akan memulai dengan pendekatan yang bersahabat, dimulai dengan hal-hal yang kita sepakati, kemudian menunjukkan bagaimana solusi yang diusulkan tidak memadai, menghubungkannya dengan tugas-tugas perjuangan untuk sosialisme yang lebih luas. Seperti yang dikatakan Lenin pada bulan April 1917: “untuk memberi massa penjelasan yang sabar, sistematis, dan gigih mengenai kekeliruan taktik mereka, penjelasan yang terutama disesuaikan dengan kebutuhan praktis massa.”
Pada saat yang sama, jelas ada semakin banyak kaum muda yang mulai mengidentifikasi diri dengan ide-ide revolusioner sebagai alternatif paling radikal terhadap sistem kapitalis dan kita bisa menggapai mereka dengan program lengkap kita. Meskipun belum menjadi mayoritas, bahkan di kalangan muda sekalipun, ini tetap merupakan perkembangan yang sangat berarti.
Runtuhnya Stalinisme sudah berlalu 35 tahun, sehingga bagi generasi ini, propaganda kelas penguasa tentang ‘kegagalan sosialisme’ nyaris tidak punya makna. Yang mereka rasakan secara langsung dan cemaskan adalah kegagalan kapitalisme!
Krisis kepemimpinan
Materi-materi yang mudah terbakar menumpuk di berbagai penjuru dunia. Krisis sistem kapitalisme dalam segala bentuknya telah memicu gelombang demi gelombang pemberontakan revolusioner. Apa-yang-disebut tatanan dunia liberal, yang selama puluhan tahun membentuk lanskap global, kini runtuh di hadapan mata kita. Peralihan ke proteksionisme dan perang dagang mengguncang fondasi ekonomi dengan dahsyat.
Pertanyaannya bukanlah apakah akan muncul gerakan-gerakan revolusioner di periode mendatang. Itu sudah pasti. Yang harus kita pertanyakan adalah: akankah semua itu berujung pada kemenangan kelas buruh?
Selama lima belas tahun terakhir kita telah menyaksikan sejumlah gerakan revolusioner dan pemberontakan. Semua itu menunjukkan semangat dan daya ledak revolusioner massa yang luar biasa begitu mereka mulai bergerak. Mereka sanggup menerobos represi brutal, keadaan darurat, pemadaman informasi, bahkan rezim paling represif sekalipun. Namun pada akhirnya, tak satu pun dari gerakan itu berhasil membawa kelas buruh ke tampuk kekuasaan.
Yang selalu absen dalam setiap momen itu adalah kepemimpinan revolusioner yang sanggup membawa gerakan hingga ke ujung logisnya. Revolusi Arab tahun 2011 berakhir dengan rezim-rezim Bonapartis yang menindas (seperti di Mesir dan Tunisia), atau bahkan lebih buruk lagi, perang saudara reaksioner (seperti di Libya dan Suriah). Pemberontakan di Chile disalurkan kembali ke jalur aman konstitusionalisme borjuis. Revolusi di Sudan pun tenggelam dalam perang saudara yang sepenuhnya reaksioner.
Trotsky menulis dalam Program Transisional bahwa “krisis historis umat manusia tereduksi menjadi krisis kepemimpinan revolusioner”. Hari ini kata-katanya menjadi lebih relevan daripada sebelumnya. Faktor subjektif—yakni organisasi kader revolusioner yang berakar di kelas buruh—sangat lemah bila dibandingkan dengan besarnya tugas-tugas besar yang dituntut oleh sejarah. Selama puluhan tahun, kita telah berjuang melawan arus dan terus didorong mundur oleh gelombang objektif yang begitu kuat.
Ini secara tak terelakkan berarti bahwa krisis-krisis revolusioner yang akan datang tidak akan terselesaikan dalam waktu singkat. Maka dari itu, kita tengah menghadapi sebuah periode panjang yang dipenuhi pasang surut, kemajuan dan kekalahan. Namun melalui seluruh proses ini, kelas buruh akan belajar, dan barisan pelopornya akan menjadi lebih kuat. Akhirnya, arus sejarah mulai bergerak ke arah kita, dan kini, kita bisa berenang mengikuti arus, bukan melawannya.
Tugas kita adalah untuk terlibat langsung, berdampingan dengan massa kelas buruh, dan menghubungkan program revolusi sosialis yang telah matang dengan hasrat yang belum matang dari elemen-elemen termaju akan perubahan revolusioner yang mendasar.
Pendirian organisasi revolusioner adalah langkah yang sangat penting, dan kita tidak boleh meremehkan apa yang telah dicapai: sebuah organisasi internasional yang berdiri kokoh di atas dasar teori revolusioner. Selama periode terakhir, kekuatan revolusioner kita telah tumbuh secara signifikan. Namun demikian, kita harus tetap bisa mengukur kekuatan kita sendiri, bahwa kekuatan kita masih jauh dari memadai untuk tugas-tugas besar yang menanti di depan.
Lemahnya faktor subjektif tak pelak berarti bahwa dalam periode mendatang, radikalisasi massa akan mengekspresikan dirinya dalam kebangkitan dan kejatuhan berbagai formasi dan tokoh reformis kiri yang baru. Beberapa dari mereka bahkan akan menggunakan bahasa yang sangat radikal, namun semuanya akan terbentur pada batas-batas reformisme: ketidakmampuan mereka untuk mengajukan masalah penggulingan sistem kapitalis dan perebutan kekuasaan oleh kelas buruh. Karena itulah, pengkhianatan itu inheren dalam reformisme. Namun untuk sementara waktu, formasi-formasi dan tokoh-tokoh reformis kiri ini dapat membangkitkan antusiasme dan mendapat dukungan massa.
Harus ada urgensi untuk membangun organisasi di mana-mana. Tidaklah sama dampaknya ketika kita memiliki 100, 1.000, atau 10.000 anggota saat pemberontakan massa kembali meletus. Sebuah organisasi dengan 1.000 kader terlatih di awal revolusi Bolivarian di Venezuela, atau 5.000 kader yang berakar di kelas buruh ketika Corbyn memenangkan kepemimpinan Partai Buruh di Inggris, bisa saja mengubah jalannya situasi. Setidaknya, dengan kebijakan dan pendekatan yang tepat terhadap gerakan massa, mereka bisa tumbuh menjadi kekuatan yang signifikan dalam gerakan kelas buruh, menjadi titik acuan bagi lapisan yang lebih luas.
Dalam kondisi yang tepat, di tengah arus peristiwa, bahkan organisasi yang relatif kecil pun dapat berubah menjadi kekuatan yang jauh lebih besar dan berjuang merebut kepemimpinan massa. Itu adalah tugas untuk masa depan. Tugas saat ini adalah kerja sabar merekrut, dan yang terpenting, mendidik serta melatih kader, terutama dari kelas pekerja muda, mahasiswa, dan pelajar.
Sebuah organisasi yang berakar kuat di dalam massa dan dipersenjatai dengan teori revolusioner akan mampu merespons dengan cepat perubahan-perubahan dalam situasi. Namun, kepemimpinan revolusioner tidak bisa diimprovisasi ketika peristiwa revolusioner meletus. Ia harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Inilah tugas paling mendesak yang kita hadapi hari ini. Keberhasilan atau kegagalan kita akan sangat menentukan arah seluruh situasi. Gagasan ini harus menjadi kekuatan pendorong utama di balik seluruh kerja, pengorbanan, dan upaya kita. Dengan tekad dan ketekunan yang diperlukan, kita bisa dan akan berhasil.