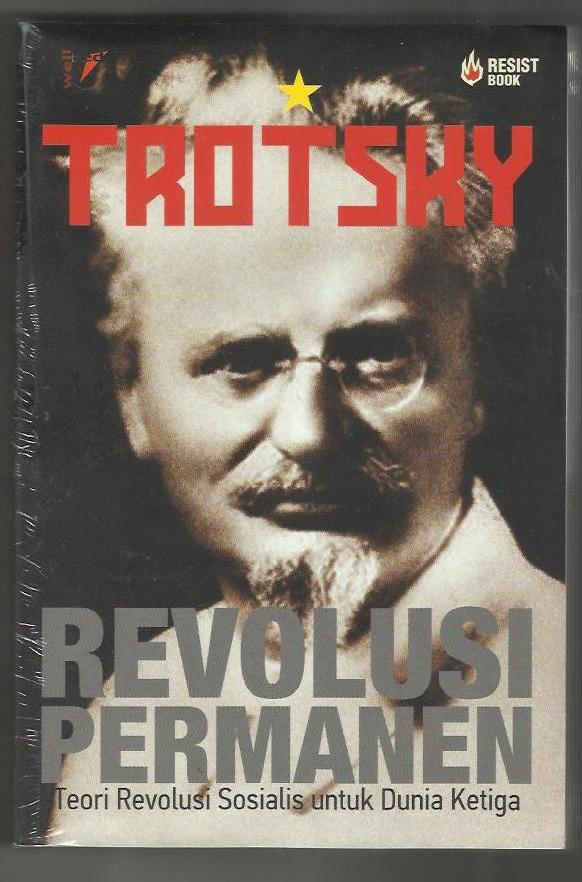Semua teori, program, dan kebijakan cepat atau lambat akan menemukan ekspresinya di dalam praktek. Teori Revolusi Permanen, yang merupakan salah satu perkembangan teori Marxis yang paling penting, sudah dikonfirmasikan secara positif oleh Revolusi Oktober 1917 di Rusia. Teori ini juga sudah dikonfirmasikan, secara negatif, di dalam banyak peristiwa semenjak itu. Contoh yang paling buruk dari ini adalah pembantaian satu setengah juta kaum komunis Indonesia pada tahun 1965.
Trotsky pertama kali mengembangkan teori Revolusi Permanen ini semenjak tahun 1904. Apa isi teori ini? Revolusi Permanen, walaupun menerima fakta bahwa tugas-tugas objektif yang dihadapi oleh kelas buruh Rusia adalah tugas-tugas revolusi borjuis demokratrik, menjelaskan bahwa bagaimana di sebuah negara yang terbelakang di dalam era imperialisme, kaum “borjuis nasional” tidak mampu memainkan peran yang progresif.
Alasannya adalah karena kaum borjuis yang lemah di kerajaan Tsar Rusia terikat dan tidak terpisahkan dengan tuan-tuan tanah feodal di satu pihak dan kekuatan modal imperialis di pihak yang lain, dan oleh karena itu mereka sama sekali tidak mampu melaksanakan tugas-tugas historis mereka (reformasi agraria, modernisasi masyarakat, demokrasi, masalah nasional, dll). Gagasan ini diuji setahun kemudian (pada tahun 1905) di dalam Revolusi Rusia yang pertama, ketika kaum borjuis liberal yang diwakili oleh Partai Kadet mengkhianati revolusi tersebut dan mendukung otokrasi Tsar.
Sudah ada beberapa contoh sebelumnya. Bahkan pada tahun 1848-49, selama periode revolusi borjuis demokratik di Eropa, Marx and Engels tanpa belas kasihan menelanjangi peran kaum borjuis yang penakut dan kontra-revolusioner, dan menekankan pentingnya bagi para buruh untuk mempertahankan keindependenan kelas mereka, bukan hanya dari kaum borjuis liberal tetapi juga dari kaum borjuis kecil demokrat yang plin-plan. Marx menekankan ini di dalam banyak artikel, seperti The Bourgeoisie and the Counter-Revolution (1848). Dan sebenarnya, Marx lah yang pertama kali menggagaskan ide Revolusi Permanen. Tetapi Trotskylah, yang mengambil Marx sebagai titik tolaknya, yang kemudian mengembangkan ide ini menjadi sebuah teori yang lengkap yang dapat diaplikasikan di situasi sekarang ini.
Leninisme dan Menshevisme
Sebelum Perang Dunia Pertama, ada perdebatan yang sengit di dalam tubuh Sosial Demokrasi Rusia mengenai perspektif Revolusi Rusia. Kaum Menshevik, yang merupakan sayap oportunis dari gerakan buruh Rusia, mengembangkan teori dua-tahap sebagai perspektif mereka untuk revolusi Rusia. Mereka berargumen bahwa, karena tugas-tugas revolusi ini adalah tugas-tugas revolusi borjuis demokratrik, maka kelas borjuis demokratik nasional-lah yang harus mengambil kepemimpinan revolusi ini. Mereka menunda revolusi sosialis ke hari depan yang jauh, dan menyerahkan kepemimpinan buruh kepada kaum liberal. Teori Revolusi Permanen adalah jawaban yang paling sempurna terhadap posisi reformis dan kolaborasi-kelas dari kubu Menshevik.
Apa posisi Lenin dalam hal ini? Dalam masalah politik yang utama (hubungan antara partai pekerja dengan kaum borjuis), posisi Lenin dekat dengan posisi Trotsky, dan dia berjuang melawan posisi kolaborasi-kelas Menshevik. Lenin setuju dengan Trotsky bahwa kaum liberal Rusia tidak mampu melaksanakan revolusi borjuis-demokratik, dan tugas ini hanya bisa dilaksanakan oleh kaum proletar yang beraliansi dengan kaum tani miskin.
Mengikuti jejak langkah Marx, yang telah menjelaskan bahwa “bagi kaum buruh, partai borjuis demokratik lebih berbahaya daripada kaum liberal sebelumnya”, Lenin menjelaskan bahwa kaum borjuis Rusia, jauh dari menjadi sekutu kaum buruh, pasti akan berpihak pada konter revolusi. Dia menulis pada tahun 1905, “Kaum borjuis pasti akan berpihak pada konter revolusi, dan akan melawan rakyat segera setelah kepentingan-kepentingannya yang sempit dan egois terpenuhi, segera setelah mereka ‘mundur’ dari demokrasi yang konsisten (dan mereka sudah mulai mengambil langkah mundur dari demokrasi yang konsisten).” (Lenin, Collected Works, vol. 9, hal.98)
Dalam pandangannya Lenin, kelas mana yang dapat memimpin revolusi borjuis-demokratik? “Yang tersisa adalah ‘rakyat’, yakni kaum proletar dan tani. Kaum proletarlah satu-satunya kelas yang bisa diandalkan untuk berjalan hingga garis finis, karena mereka berjalan melampaui revolusi demokratik. Inilah mengapa kaum proletar berjuang di garis depan untuk pembentukan sebuah republik dan menolak saran yang bodoh dan tak bernilai untuk memikirkan mengenai kemungkinan mundurnya kaum borjuis.” (Ibid.)
Di dalam semua pidato dan tulisan Lenin, peran konter-revolusioner dari kelas borjuis demokratik ditekankan oleh Lenin berulang kali. Akan tetapi, sampai pada tahun 1917, dia tidak percaya kalau kaum buruh Rusia akan dapat berkuasa sebelum revolusi sosialis di Eropa Barat – sebuah perspektif yang dipertahankan hanya oleh Trotsky sebelum tahun 1917 ketika ini diadopsi oleh Lenin di Tesis April-nya.
Revolusi Oktober
Kelas pekerja Rusia – seperti yang Trotsky prediksi pada tahun 1904 – meraih kekuasaan sebelum para pekerja Eropa. Mereka melaksanakan semua tugas-tugas revolusi borjuis-demokratik, dan dengan segera menasionalisasi industri dan menuju pelaksanaan tugas-tugas revolusi sosialis. Kaum borjuis secara terbuka memainkan sebuah peran konter-revolusioner, tetapi ini dipatahkan oleh kaum pekerja yang beraliansi dengan kaum tani miskin. Oleh karena itu, Revolusi Oktober secara megah mendemonstrasikan kebenaran dari teori Revolusi Permanen.
Setelah mengambil kekuasaan dan menyita para tuan tanah dan para kapitalis, kaum Bolshevik menyerukan sebuah seruan revolusioner kepada para buruh sedunia untuk mengikuti contoh mereka. Lenin tahu dengan sangat baik bahwa tanpa kemenangan revolusi di negara-negara kapitalis maju, terutama di Jerman, Revolusi Rusia tidak akan bisa selamat terisolasi, terutama di negara terbelakang seperti Rusia. Apa yang terjadi kemudian (baca: degenerasi Uni Soviet yang menjadi birokratis) menunjukkan bahwa perspektif ini adalah benar-benar tepat. Pembentukan International Ketiga (Komunis International), yakni partai dunia untuk revolusi sosialis, merupakan manifestasi konkrit dari perspectif tersebut.
Bila saja Komunis Internasional tetap memegang teguh posisi Lenin dan Trotsky, kemenangan revolusi sedunia sudah pasti akan terjamin. Sayangnya, tahun-tahun pertumbuhan Komintern terjadi seiring dengan konter revolusi Stalinis di Rusia, yang memiliki sebuah efek yang menghancurkan bagi Partai-Partai Komunis di seluruh dunia. Birokrasi Stalinis, setelah meraih kontrol di Uni Soviet, mengembangkan sebuah perspektfi yang sangat konservatif.
Teori bahwa sosialisme bisa dibangun di satu negara adalah sebuah penyelewengan terhadap ide-ide Marx dan Lenin. Pada awalnya, Stalin bahkan mengakui hal ini. Sampai pada bulan Februari 1924, di dalam tulisannya The Foundations of Leninisme, Stalin menyimpulkan pandangan Lenin mengenai pembangunan sosialisme:
“Penumbangan kekuasaan kaum borjuis dan pembentukan pemerintahan proletariat di satu negara belumlah menjadi kemenangan mutlak sosialisme. Tugas utama sosialisme – yakni pengorganisiran produksi secara sosialis – masih harus dilaksanakan. Dapatkan tugas ini dipenuhi, dapatkah kemenangan akhir sosialisme di satu negara tercapai, tanpa bantuan bersama dari kaum proletar di beberapa negara maju? Tidak, ini adalah hal yang mustahil. Untuk menumbangkan kaum borjuis, usaha satu negara adalah cukup – sejarah dari revolusi kita sudah menunjukkan ini. Unuk kemenangan akhir sosialisme, untuk pengorganisiran produksi secara sosialis, usaha dari satu negara terutama sebuah negara petani seperti Rusia, tidaklah cukup. Untuk ini, bantuan dari kaum proletar di beberapa negara maju dibutuhkan.”
“Secara keseluruhan, inilah ciri karakteristik dari teori Leninis mengenai revolusi proletarian.“
Tidak ada keraguan sama sekali kalau kalimat diatas mewakili ciri karakteristik dari teori Leninis mengenai revolusi proletarian, yang saat itu tidak dipertanyakan oleh siapapun. Akan tetapi, sebelum tahun 1924 berakhir, buku Stalin sudah dirubah, dan isi di atas diganti dengan isi yang benar-benar terbalik. Pada bulan November 1926, Stalin mengatakan:
“Untuk titik tolaknya, partai ini selalu mulai dengan gagasan bahwa kemenangan sosialisme di negara itu dan tugasnya dapat dicapai dengan kekuatan dari satu negara.”
Ini merepresentasikan sebuah revisi yang fundamental terhadap ide Marxisme-Leninisme. Yang sebenarnya direfleksikan oleh ide ini adalah mentalitas kaum birokrat, yang tidak ingin lagi menghadapi badai dan stress revolusi, dan ingin segera memulai tugas “membangun sosialisme di Rusia”. Dengan kata lain, mereka inign melindungi dan memperbesar hak-hak istimewa mereka dan tidak “membuang-buang” sumber daya negara untuk mengejar revolusi dunia. Di pihak yang lain, mereka takut kalau revolusi di negara-negara lain dapat berkembang dengan sehat dan mengancam dominasi mereka di Rusia, dan oleh karena itu mereka secara aktif mencoba mencegah revolusi di negara yang lain.
Daripada mengadopsi sebuah kebijakan revolusioner yang berdasarkan keindependenan kelas, seperti yang Lenin selalu anjurkan, mereka menganjurkan sebuah aliansi antara Partai Komunis dengan “kaum borjuis nasional yang progresif” (dan bila tidak ada kaum borjuis nasional yang progresif di lapangan, mereka siap untuk menciptakannya) untuk melaksanakan revolusi demokratik, dan setelah itu, di masa depan yang sangat jauh, ketika negara tersebut sudah mengembangkan sebuah sistem ekonomi kapitalis yang matang, barulah mereka berjuang untuk sosialisme. Kebijakan ini merupakan sebuah perpecahan total dari Leninisme dan kembali ke posisi Menshevisme yang tua dan sudah tercemar – yakni teori “dua-tahap”.
Revolusi Permanen di masa kini
Kondisi politik sekarang bahkan lebih jelas dibandingkan dengan tahun 1917. Semenjak Perang Dunia Kedua, semua “negara ketiga” telah melalui sebuah periode gejolak sosial yang berkelanjutan. Pencapaian kemerdekaan secara formal, walaupun disambut oleh kaum Marxis, tidaklah menyelesaikan masalah-masalah bekas negara koloni ini. Selama mereka tetap berada di dalam basis kapitalisme, tidak ada jalan ke depan. Mereka tetap diperbudak oleh negara-negara kapitalis maju. Menggantikan penjajahan militer-birokratik yang langsung, kita sekarang memiliki dominasi tidak langsung melalui mekanisme pasar dunia dan perdagangan internasional.
Kaum borjuis nasional di negara-negara koloni ini memasuki pentas sejarah terlalu telat, ketika dunia sudah dibagi-bagi antara beberapa kekuatan imperialis. Mereka tidak mampu memainkan peran progresif apapun dan mereka lahir dibawah telapak kaki mantan tuan penjajahnya. Seperti halnya di kerajaan Tsar Rusia, kaum borjuis yang lemah dan korup di Asia, Amerika Latin, dan Afrika terlalu tergantung pada modal asing dan imperialisme untuk bisa membawa maju masyarakat mereka. Mereka terikat dengan seribu benang, bukan hanya pada modal asing, tetapi juga pada kelas tuan tanah, yang bersama-sama dengan mereka membentuk satu blok reaksioner yang menentang semua kemajuan.
Apapun perbedaan yang mungkin eksis antara elemen-elemen ini (kaum borjuis nasional, modal asing, dan tuan tanah), perbedaan tersebut adalah tidak signifikan dibandingkan dengan ketakutan mereka terhadap massa, ketakutan yang menyatukan mereka untuk melawan massa. Hanya kelas proletar, bekerja sama dengan kaum tani miskin dan kaum miskin kita, yang dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan merebut kekuasaan ke tangan mereka, menyita kaum imperialis dan kaum borjuis, dan memulai tugas merubah masyarakat secara sosialis.
Dibawah kondisi masa kini, tugas-tugas revolusi borjuis-demokratik di negara-negara terbelakang tidak dapat diselesaikan dengan basis relasi properti kapitalis. Kaum borjuis yang lemah dari negara-negara eks-koloni ini terlalu terikat dengan modal asing internasional untuk bisa melaksanakan revolusi nasional sampai ke garis akhir. Dan mereka juga tidak bisa berkompetisi dengan kompetitor dari negara industri maju untuk pasar dunia. Sebagai akibatnya, status ekonomi mereka memburuk terus menerus dibandingkan dengan negara-negara kapitalis maju.
Penghancuran ekonomi dari negara-negara terbelakang ini menciptakan kondisi krisis sosial yang akut dan permanen. Di satu pihak, masyarakat tani subsisten semakin terkikis berangsur-angsur, di pihak yang lain, kelas kapitalis tidak mampu menerapkan sistem ekonomi kapitalis di seluruh masyarakat. Bangkitnya negara polisi-militer di seluruh “dunia ketiga” hanyalah sebuah ekspresi dari ketidakmampuan kaum borjuis dari negara-negara koloni tersebut untuk menyelesaikan tugas-tugas revolusi demokratik. Hanya melalui kediktaturan revolusioner dari kelas proletar, beraliansi dengan kaum tani miskin, maka negara-negara terbelakang ini mampu mulai menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan sosial mereka.
Dengan berdiri di muka bangsa dan memimpin semua lapisan tertindas di dalam masyarakat (kaum borjuis kecil urban dan rural), kaum proletar dapat mengambil kekuasaan dan kemudian melaksanakan tugas-tugas revolusi borjuis-demokratik (terutama reformasi agraria dan penyatuan negara dan pembebasan negara dari dominasi asing).
Akan tetapi, setelah berkuasa, kelas proletar tidak akan berhenti disana dan akan mulai mengimplementasikan kebijakan-kebijakan sosialis dan mengekspropriasi kaum kapitalis. Dan karena tugas-tugas ini tidak dapat diselesaikan di satu negara saja, terutama di satu negara yang terbelakang, ini akan menjadi permulaan dari revolusi dunia. Oleh karena itu, revolusi ini “permanen” dalam dua hal: karena revolusi ini mulai dengan tugas-tugas borjuis-demokratik dan berlanjut ke tugas-tugas sosialis, dan karena revolusi ini mulai di satu negara dan berlanjut ke skala internasional.
Peran Partai-Partai Komunis
Teori dua-tahapnya Menshevik dan Stalinis telah memainkan satu peran yang kriminal di dalam perkembangan revolusi di negara-negara koloni. Dimana saja teori ini sudah diaplikasikan, ia telah menghasilkan malapetaka. Pada tahun 1920an, mengikuti teorinya Stalin “blok empat kelas”, Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang masih muda saat itu dipaksa untuk bergabung dengan partai borjuis nasional Kuomintang, yang kemudian secara fisik menghancurkan PKT, serikat-serikat buruh, dan soviet-soviet tani selama Revolusi Cina 1925-27. Alasan mengapa Revolusi Cina kedua (tahun 1949) mengambil bentuk perang tani dimana kelas buruh Cina berperan pasif adalah karena hancurnya kelas proletar akibat kebijakan-kebijakan Stalin, yang Trotsky gambarkan sebagai “sebuah karikatur Menshevisme yang buruk.”
Di Irak pada tahun 1950an dan 1960an, Partai-Partai Komunis disana adalah kekuatan besar yang mampu mengorganisir demonstrasi satu juta orang di Baghdad. Saat itu, mereka bisa saja dengan mudah mengambil kekuasaan. Tetapi, dari pada mengambil sebuah kebijakan kelas yang independen dan memimpin buruh dan tani untuk merebut kekuasaan, mereka mencari aliansi dengan kaum borjuis “progresif” dan seksi-seksi tentara yang “progresif”. Tentara “progresif” ini, setelah naik ke tampuk kekuasaan di atas punggung Partai-Partai Komunis Irak, kemudian menghancurkan mereka dengan membunuh dan memenjara anggota-anggota dan pimpinan-pimpinan mereka. Rakyat Irak membayar sangat mahal dengan dikuasai oleh diktatur Saddam Hussein, dan horor peperangan dan okupasi asing yang berlanjut dari sana.
Di Sudan, proses yang sama terjadi bukan sekali saja, tetapi dua kali. Pada tahun 1967, Partai Komunis Sudan (PKS) mampu memanggil demonstrasi 2 juta orang di Khartoum. Tetapi para pemimpin PKS mengadopsi kebijakan “Aliansi Patriot” dengan kaum borjuis “progresif”. Apa hasil dari aliansi ini? Hasilnya adalah kediktaturan Nimeiri, pembantaian PKS dan kemenangan kaum reaksioner di Sudan dengan konsekuensi-konsekuensi yang tragis. Akan tetapi, semua malapetaka ini kecil dibandingkan dengan pembantaian para Komunis di Indonesia pada tahun 1965.
Indonesia
Indonesia bukanlah pengecualian. Walaupun memiliki potensial produksi yang besar, Indonesia tetap terpuruk miskin dan terbelakang. Pada satu ketika, Indonesia adalah daerah surplus-beras; pada tahun 1965, Indonesia harus mengimpor 150 ribu ton beras setiap tahunnya. Ekonomi Indonesia terpuruk dengan hutang besar kepada komunitas bank internasional, terutama bank AS. Setiap tahun, defisit anggaran meningkat dua kali lipat. Jumlah defisit pada tahun 1965 adalah sekitar 1000 milyar rupiah. Mata uang Rupiah telah jatuh menjadi 1/100 dari harga legalnya sebagai akibat dari inflasi kronik, yang 6 tahun sebelum kudeta 1965 telah membuat ongkos kehidupan naik 2 ribu persen.
Walaupun ekonomi sedang runtuh, Negara Indonesia saat itu membelanjakan 75% anggaran untuk persenjataan (1 milyar dollar AS setiap tahun). Dengan ekonomi yang meluncur ke bawah dengan cepat, Sukarno terpaksa menasionalisasi semakin banyak perusahaan-perusahaan asing. Untuk melakukan ini, dia harus bersandar pada dukungan Partai Komunis Indonesia – sebuah aksi yang tidak luput dari perhatian Washington.
Rejim Bonapartis dari Sukarno dipenuhi dengan korupsi. Di tengah-tengah kemiskinan massal, upah rendah dan masalah perumahan yang besar, Sukarno dan elit-elitnya hidup seperti raja. Di bawah arahan Sukarno, sejumlah uang yang besar diboroskan untuk membangun gedung-gedung mewah seperti Hotel Indonesia di Jakarta, dimana, mengutip Sunday Times, “Tiga juta rakyat, yang kebanyakan miskin, tinggal … di rumah-rumah kumuh … yang kebanyakan akan runtuh”. Sukarno tinggal di sebuah vila putih – yang dulunya adalah tempat tinggal gubernur Belanda – dan dikelilingi dengan perabotan-perabotan mewah dan karya-karya seni yang mahal. “Tiga ruang utama yang megah tersebut tampak seperti museum dalam kebesarannya dan aurannya. Setiap ruang itu diperaboti dengan megah dan dikarpeti. Setiap ruang digantungi dengan sebagian dari koleksi lukisan megahnya Sukarno.”
Kemiskinan dan kesukaran rakyat mengakibatkan tumbuhnya PKI secara pesat. Tidak ada gerakan buruh di “Negara Ketiga” yang tumbuh sepesat Indonesia. PKI, yang secara praktikal hilang keberadaannya setelah kudeta yang gagal pada tahun 1948, menjadi Partai Komunis terbesar ketiga di dunia – hanya Partai Komunis Tiongkok dan Uni Soviet yang lebih besar.
Kebijakan Menshevik PKI
Jumlah anggota PKI saat itu adalah 3 juta. Ia memiliki dukungan 10 juta anggota serikat buruh dan kaum tani yang terorganisir. Yang terlebih penting, PKI mengklaim dukungan 40 persen dari tentara Indonesia. Partai Bolshevik pada tahun 1917 tidak memiliki basis yang sekuat itu. Pada bulan Februari, Bolshevik hanya memiliki 8000 anggota di sebuah negara besar dengan 150 juta rakyat. Namun hanya dalam 9 bulan, Lenin dan Trotsky memimpin Partai Bolshevik untuk menaklukkan kekuasaan. Secara kontras, PKI dengan kekuatannya yang besar, memimpin kaum buruh dan tani Indonesia menuju kekalahan yang penuh darah. Mengapa?
Di dalam perpecahan Sino-Soviet, PKI berpihak dengan Peking, dan mempertahankan hubungan yang dekat dengan kaum Stalinis Cina. Kita mungkin berpikir bahwa ini adalah sebuah kombinasi yang revolusioner. Tetapi ini salah. Kebijakan PKI adalah kebijakan kolaborasi kelas. Kepemimpinan PKI mengekori kepemimpinan sang borjuis Bonapartis yang “progresif”, Sukarno. Setelah 1948, semua sisa-sisa ideologi revolusioner secara sistematis dihapus dari program PKI. Program dan Konstitusi PKI tahun 1962 menggarisbawahi tugas partai untuk membentuk “negara rakyat demokratik”. Ini tidak ada kesamaannya dengan sosialisme.
“Negara rakyat demokratik” ini akan merupakan sebuah “demokrasi tipe baru”, yang bukan berdasarkan kelas buruh, tetapi berdasarkan sebuah blok kaum buruh dan tani dengan bermacam-macam koleksi “sekutu”, termasuk ” kaum borjuis kecil perkotaan, kaum intelektual, kaum borjuis nasional (!), elemen-elemen aristokrat yang maju (!!) dan elemen-elemen patriotik secara umum (!!!)” Dari bentuk ini, sangatlah sulit untuk meraih kesimpulan mengenai karakter kelas dari “negara rakyat demokratik” karena bentuk tersebut diatas hanyalah daftar semua kelas dan strata di Indonesia. Ini berarti bahwa program PKI dengan orientasi Peking yang “revolusioner” hanyalah mempertahankan status quo.
Daripada kediktaturan proletar, PKI merujuk pada “otoritas” dari “rakyat” – sebuah formula yang tidak ada artinya. Pada tahun 1955, PKI mengadvokasikan sebuah koalisi nasional, dan menawarkan untuk menumpulkan program mereka yang sudah tumpul menjadi sebuah daftar tujuan-tujuan yang sepenuhnya non-komunis. Ahli teori utama dari PKI, yakni Aidit, menganjurkan teori “dua-tahap”nya Menshevik-Stalinis, yang menunda revolusi sosialis ke masa depan yang jauh:
“Pada saat kita menyelesaikan tahapan pertama dari revolusi kita yang sekarang sedang dalam progres, kita dapat melakukan negosiasi bersahabat dengan elemen-elemen progresif lainnya di dalam masyarakat kita, dan tanpa perjuangan bersenjata kita akan memimpin bangsa ini menuju revolusi sosialis. Lagipula, kaum kapitalis nasional di negara kita adalah lemah dan tak terorganisir. Sekarang, di dalam revolusi demokratik nasional kita, kita berpihak dengan mereka dan berjuang di dalam perjuangan bersama untuk menendang keluar dominasi modal asing dari tanah air ini”.
Argumen Aidit penuh kontradiksi. Bila kaum borjuis nasional adalah lemah dan tak terorganisir, maka lebih banyak alasan untuk menyapu mereka ke samping dan membentuk pemerintahan buruh dan tani. Kenyataannya, seperti yang Lenin garisbawahi ratusan kali, justru karena kelemahan kaum borjuis nasional yang membuat mereka menjadi batu halangan yang reaksioner di dalam jalan menuju revolusi demokratik di negara-negara terbelakang. Mereka (baca kaum borjuis nasional) meragukan kemampuan mereka untuk mengontrol kekuatan-kekuatan yang dilepaskan dari gerakan nasional demokratik itu sendiri, mereka menjadi ambigu, dan akhirnya mereka terdorong ke pihak reaksioner karena takut terhadap kelas pekerja mereka sendiri. Untuk alasan ini, sangatlah reaksioner bila kita mencoba memisahkan secara mekanis fase-fase revolusi demokratik dan revolusi sosialis di negara-negara terbelakang. Pilihannya adalah: revolusi demokratik “bergerak menuju” kediktaturan proletariat, atau revolusi demokratik tersebut hancur di bawah palu reaksi.
Apa yang disebut posisi “Leninis” dari Aidit dan pemimpin-pemimpin PKI lainnya adalah identik dengan posisi kaum Menshevik yang dilawan dengan gigih oleh Lenin sampai pada tahun 1917. Bagi mereka, kediktaturan proletariat yang revolusioner ditunda sampai masa depan yang jauh (dan oleh karena itu aman) – 50, 100, bahkan 300 tahun kemudian. Pertama-tama, kita selesaikan dahulu “tahapan pertama”, lalu setelah ini “tercapai sepenuhnya”, kita “lakukan negosiasi bersahabat” dengan mereka yang mungkin tertarik dengan “tahapan kedua”. Akan tetapi, sejarah tidaklah terjadi seperti itu.
“Gerakan 30 September”
Puluhan tahun kebijakan dua-tahap Menshevik yang diadopsi oleh kepemimpinan PKI akhirnya menghancurkan partai tersebut dan bersama-sama dengan itu seluruh gerakan buruh dan tani di Indonesia dengan satu sapuan. Ini menyebabkan kehancuran gerakan Komunis di Indonesia – yang saat itu adalah Partai Komunis ketiga terbesar setelah Uni Soviet dan Cina – dan sebuah pergeseran radikal di dalam politik Indonesia dan seluruh Asia Tenggara. Peristiwa yang memicu malapetaka ini adalah Gerakan 30 September.
Washington bersihkeras untuk menumbangkan Sukarno dan menghancurkan PKI. Mereka mengganggap prospek sebuah pemerintahan Komunis di Indonesia sebagai hari kiamat. Pada sebuah pidato tahun 1965, Richard Nixon membenarkan pemboman Vietnam Utara sebagai satu cara untuk melindungi “kekayaan mineral yang besar” di Indonesia. Seperti yang ditulis oleh ahli sejarah John Rossa di dalam bukunya Pretext for Mass Murder, yang merupakan buku sejarah yang terbaru mengenai Gerakan 30 September:
“Tentara yang mulai tiba di Vietnam pada bulan Maret 1965 tidak akan berguna bila kaum Komunis menang di sebuah negara yang lebih besar dan strategis. Kemenangan PKI di Indonesia akan membuat intervensi di Vietnam sia-sia … McGeorge Bundy, seorang penasehat keamanan nasional untuk Presiden Kennedy dan Johnson, juga telah menekankan bahwa Vietnam sudah bukan lagi kepentingan yang vital ‘setelah revolusi anti-komunis di Indonesia’.”
Kebijakan-kebijakan Sukarno melawan perusahaan-perusahaan asing, kebijakan Non-Bloknya (yang diperagakan di Konferensi Asia-Afrika 1955), pengutukannya terhadap imperialisme Barat, dan ketergantungannya pada PKI yang semakin meningkat, semua ini meyakinkan Pemerintahan AS untuk membuat aliansi dekat dengan perwira-perwira reaksioner seperti Jendral Nasution yang sangat anti-komunis. Dari tahun 1958 hingga 1965, Amerika melatih, mendanai, menasehati, dan mensuplai seksi dari tentara Indonesia yang anti-komunis.
Akan tetapi, seperti yang dipaparkan di dalam dokumen-dokumen rahasia pemerintahan AS yang telah dibuat publik, para jendral sayap kanan ini sadar kalau mereka tidak akan dapat melakukan kudeta model lama untuk melawan Sukaro dan PKI – karena Sukarno masih terlalu populer dan PKI memiliki dukungan massa. Usaha-usaha sebelumnya untuk membelah Indonesia ke dalam negara-negara yang lebih kecil (“zona komunis” dan “zona non-komunis’) – seperti yang terjadi di Korea dan Vietnam – gagal total. Usaha-usaha yang gagal ini justru memperkuat Sukarno dan PKI karena garis anti-imperialisme mereka terbukti benar di mata rakyat.
Untuk alasan-alasan ini, sebuah kudeta terbuka tidak dapat dilakukan di Indonesia. Supaya kudeta sayap-kanan dapat berhasil, ia harus disamarkan sebagai sebuah usaha untuk menyelamatkan Presiden Sukarno. Pada tahun 1959, Dewan Keamanan Nasional AS sudah mengakui bahwa serangan terbuka terhadap PKI harus “dibenarkan secara politik untuk kepentingan Indonesia sendiri” dan PKI harus didorong “ke posisi dimana mereka menentang secara terbuka Pemerintahan Indonesia [Sukarno].” Howard Jones, Duta Besar AS di Jakarta (1958-1965), mengatakan di dalam sebuah pertemuan tertutup di Filipin pada bulan Maret 1965, “Tentu saja dari sudut pandang kita, sebuah usaha kudeta yang gagal dari PKI adalah sebuah perkembangan yang paling efektif untuk memulai sebuah pemutaran balik tren politik di Indonesia.” Triknya adalah untuk memprovokasi PKI untuk mengambil aksi yang terburu-buru yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menghancurkannya.
Perangkap ini diluncurkan dan pemimpin-pemimpin PKI jatuh ke dalam perangkap ini. Para pemimpin PKI, daripada memobilisasi massa untuk melawan kaum reaksioner tersebut, justru berusaha meluncurkan sebuah kudeta istana dengan membunuh para jendral pemimpin sayap-kanan. Saya menulis sebuah artikel mengenai peristiwa ini, Perspectives, pada bulan Oktober 1965, beberapa minggu setelah kemenangan konter-revolusi. Di dalam artikel ini saya menjelaskan bahwa bukannya membeberkan rencana-rencana kaum sayap kanan, bukannya memobilisasi massa untuk mogok umum dan menyerukan kepada pendukungnya di dalam angkatan bersenjata untuk melucuti para perwira mereka dan bergabung dengan buruh untuk menumbangkan rejim yang busuk ini, kepemimpinan PKI justru berkonspirasi untuk membunuh para jendral reaksioner tersebut – sebuah konspirasi yang sangat rahasia sehingga selain Aidit tak seorangpun dari anggota Komite Pusat yang mengetahui rencana ini.
Enam jendral dibunuh, tetapi Nasution selamat. Bersama-sama dengan Suharto dan perwira sayap kanan lainnya, mereka memanggil pasukan mereka, melepaskan propaganda media anti-komunis yang luar biasa, dan memobilisasi demonstrasi mahasiswa (yang sebagian didanai oleh duta besar AS). Revolusi istana ini rubuh. Kebijakan-kebijakan keliru dari Aidit dan kepemimpinan PKI menaruh nyawa tiga juta buruh dan tani komunis di tangan kaum reaksioner. Koran Daily Telegraph menganalisa situasi ini di dalam editorialnya pada tanggal 12 Oktober, yang berjudul The Civil War in Indonesia:
“Sangatlah jelas dari kejadian-kejadian sepuluh hari terakhir di Indonesia bahwa ini bukanlah sebuah kudeta istana seperti sebelumnya yang mengguncang Republik Sukarno, ini adalah sebuah perang sipil yang menyebar. Tanah konfontrasi sekarang mengkonfrontasi dirinya sendiri. Tiga kepala dari sang naga ini, Muslim, Nasionalis, dan Komunis, saling menggigit satu sama lain, dan pertikaian ini telah menyebar dari Jawa ke Sumatra. Persaingan ketiga kekuatan ini yang telah ditangani oleh Dr. Sukarno sekarang meledak. Bila angkatan bersenjata mencurigai sebuah kudeta Komunis, mereka jelas-jelas terkejut dengan kekejamannya dan mereka terkacaukan dengan terbunuhnya enam jendral mereka. Sekarang jelas kalau Dr. Sukarno ada di bawah perlindungan angkatan bersenjata, dan dia telah mentoleransi kampanye melawan gerilya komunis dan akhirnya menanggalkan kepura-puraan kalau Nasakom atau Front Persatuan dia masih eksis.”
Perang sipil ini dimainkan oleh satu pihak saja. Bukannya meluncurkan ofensif yang agresif melawan kaum reaksioner – yang pada jam-jam terakhir ini dapat menyelamatkan Partai Komunis – kepemimpinan PKI justru mengandalkan aliansi mereka dengan “borjuis progresif” Sukarno. Saat kaum komunis berjuang melawan massa reaksioner, PKI tetap diwakili di kabinet Sukarno, mendukung demagog Sukarno mengenai “kesatuan nasional”, kestabilan, dll. Sampai akhirnya, mereka tetap menempel pada Sukarno, tetapi Sukarno dan kabinetnya sudah impoten.
Puluhan ribu anggota PKI yang jujur dan militan, yang kebingungan karena tidak adanya kepemimpinan dari partai mereka, menyerahkan diri mereka ke kaum reaksioner, karena mereka percaya – seperti yang dikatakan oleh pemimpin mereka – bahwa Sukarno akan melindungi mereka. Akan tetapi, sang Bonapartis Sukarno sudah menjadi hanya sebuah simbol dan tidak berkuasa lagi. Dengan begini, puluhan ribu anggota PKI sesungguhnya menyerahkan diri mereka ke massa reaksioner seperti domba yang pergi menuju tempat pemotongan hewan.
Pemerintahan Indonesia tergantung di udara. Perjuangan politik yang sesungguhnya telah pindah ke jalanan. Nasution memobilisasi kekuatan Muslim reaksioner. Markas PKI di Jakarta di serbu dan dibakar oleh massa ribuan pemuda, yang berteriak “Gantung Aidit”. Massa menyeruak di jalanan, menempel poster-poster bertulisan “Hancurkan Kaum Komunis”. Massa di depan duta besar Amerika berteriak “Hidup Amerika”. Sebuah demonstrasi 500 ribu orang menuntut aksi terhadap semua yang berpartisipasi di Gerakan 30 September. Hasil akhirnya adalah pembantaian setidaknya satu setengah juta kaum Komunis.
CIA memainkan peran yang aktif di dalam pembunuhan massal ini. Yang disebut-sebut sebagai pahlawan demokrasi di Washington, London, dan Paris dengan segera mengakui rejim pembunuh ini. Peran kriminal dari imperialisme sangatlah jelas. Tetapi para imperialis tidak akan dapat meraih kemenangan yang semudah ini bila bukan karena kebijakan-kebijakan kepemimpinan PKI yang membawa malapetaka. Ketika kekuasaan negara secara terbuka ditantang di dalam sebuah perang sipil, “moderasi” dan “jalan tengah” menghilang seperti uap air. Tetapi kepemimpinan PKI bahkan tidak bisa menyerukan mogok umum. Mereka bertingkah seperti para pemimpin Sosial Demokrat dan Stalinis di Jerman pada tahun 1933 – dan mereka membayarnya dengan harga yang sama.
Dimana kelas pekerja dikalahkan tanpa perlawanan sama sekali, ini menyebabkan runtuhnya moral yang sangat besar dan melumpuhkan rakyat untuk waktu yang sangat lama. Kekalahan 1965 mengusung sebuah periode militer-reaksioner yang kejam. Ini juga menyebabkan runtuhnya moral dari kaum buruh dan tani di Malaysia. Tidak mengejutkan kalau koran Daily Telegraph mengekspresikan dengan jelas kepuasan mereka terhadap pesta-pora konter-revolusi di Indonesia. Sebagai penutup, pengalaman Indonesia mengekspos kepalsuan frase-frase “revolusioner” dari kaum Stalinis Cina. Satu-satunya respon dari kaum birokrasi Cina terhadap pergolakan di Indonesia adalah pesan “salam hangat” kepada Sukarno ketika dia akhirnya keluar dari persembunyiannya.
Pelajaran dari Kekalahan
Masalah ketepatan sebuah teori atau masalah teori Menshevik-Stalinis bukanlah masalah akademik tetapi merupakan masalah yang praktikal. Pengalaman dari kebijakan-kebijakan Stalinis di dalam berbagai revolusi telah secara pasti membuktikan karakter konter-revolusioner mereka. Selama puluhan tahun, kelas pekerja negara-negara kolonial atau eks-kolonial telah membuktikan keberanian dan potensial revolusioner mereka. Berkali-kali mereka telah bergerak untuk melaksanakan transformasi revolusioner di negara mereka.
Di Irak, Sudan, Iran, Chile, Argentina, India, Pakistan, dan Indonesia, kaum pekerja telah menunjukkan bahwa mereka ingin menjadi tuan dari tanah air mereka. Bila mereka gagal, ini bukan karena mereka tidak bisa berhasil, tetapi ini karena mereka kekuarangan sebuah syarat penting untuk merebut kekuasaan: yakni sebuah kepemimpinan yang benar-benar revolusioner. Setiap kali, mereka terbentur dengan sebuah tembok karena partai dan pemimpin yang mereka percayai untuk memimpin mereka menuju transformasi sosialis justru menjadi halangan yang besar. Napoleon pernah berkata: “pasukan yang kalah belajar dengan baik”. Bagi kaum Marxis, pelajaran dari kekalahan lebih penting daripada pelajaran dari kemenangan.
Para buruh bisa mempelajari kesalahan-kesalahan mereka, tetapi hanya bila pengalaman-pengalaman ini dijelaskan dan dianalisa dengan sabar oleh kaum pelopor revolusioner. Kaum Marxis revolusioner memiliki sebuah tugas untuk menjelaskan pelajaran-pelajaran dari kejadian 1965 di Indonesia kepada gerakan buruh. Apa perbedaan utama antara Rusia pada tahun 1917 dan Indonesia pada tahun 1965? Perbedaan utamanya bukanlah di kondisi-kondisi objektif. Kondisi objektif di Indonesia pada tahun 1964-65 sangatlah mendukung. Rakyat Indonesia telah mengalahkan imperialisme Belanda. Kaum komunis memiliki dukungan mayoritas kelas buruh dan tani. Tetapi sebuah kebijakan dan perspektif yang keliru cukup untuk menghancurkan revolusi ini. Bila Revolusi Oktober membuktikan ketepatan teori Revolusi Permanen secara positif, maka malapetaka Indonesia membuktikan ketepatan teori Revolusi Permanen secara negatif dan secara sangat brutal.
Kesimpulannya sangat jelas. Tanpa sebuah partai revolusioner, potensial dari kaum proletar tetaplah akan menjadi potensial. Hubungan antara kelas dan partai adalah serupa dengan hubungan antara uap dan mesin piston. Tetapi, keberadaan partai tidaklah cukup untuk memastikan kesuksesan. Partai ini harus dipimpin oleh pria dan wanita yang dipersenjatai dengan pemahaman akan tugas-tugas revolusi, taktik, strategi, dan perspektif, dan bukan hanya tugas-tugas nasional tetapi juga internasional.
Untuk meraih kekuasaan, tidaklah cukup kalau kaum pekerja siap untuk bertempur. Bila cukup hanya dengan kesiapan untuk bertempur, maka kelas pekerja sudah meraih kekuasaan di semua negara tersebut dari dulu. Ini akan sangat mudah dicapai karena mereka ada di dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan kaum pekerja Rusia pada tahun 1917. Tetapi mereka tidak meraih kekuasaan. Mengapa tidak? Karena kelas pekerja membutuhkan sebuah partai dan sebuah kepemimpinan. Untuk mengabaikan kenyataan fundamental ini adalah anarkisme yang kekanak-kanakan. Marx menjelaskan semenjak dulu bahwa tanpa organisasi, kelas pekerja hanyalah bahan mentah untuk eksploitasi. Walaupun berjumlah banyak dan memainkan peran kunci di dalam produksi, kaum proletar tidak akan mampu merubah masyarakat kecuali bila ia menjadi sebuah kelas di dalam dan untuk dirinya sendiri (“in-and-for itself”) dengan kesadaran, perspektif, dan pemahaman yang dibutuhkan.
Untuk menunggu sampai kelas proletar secara keseluruhan memperoleh pemahaman yang dibutuhkan untuk merebut kekuasaan dan merubah masyarakat adalah sebuah proposisi yang utopis, yang pada intinya berarti menunda revolusi untuk selamanya. Kita perlu mengorganisir lapisan kelas proletar yang paling maju, mendidik para kader, dan memenuhi mereka dengan perspektif revolusioner, bukan hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam skala internasional, untuk mengintegrasikan mereka ke dalam rakyat di semua level, dan untuk secara sabar mempersiapkan diri untuk menghadapi momen ketika perjuangan-perjuangan parsial menjadi sebuah ofensif revolusioner yang umum.
Krisis ekonomi global sekarang ini adalah sebuah gejala dari sistem kapitalisme dunia yang telah kehabisan potensial untuk maju. Dan ini hanyalah permulaan dari sebuah proses revolusioner yang akan bergulir di dalam tahun-tahun ke depan. Bila sebuah partai Leninis yang sejati eksis, ini akan berakhir di sebuah revolusi proletar yang klasik. Walaupun menderita kekalahan dan kemunduran, kaum pekerja dan tani Indonesia pasti akan mengambil jalan perjuangan lagi dan lagi. Penggulingan Suharto merupakan indikasi dari kenyataan ini. Satu persatu negara Asia, para buruh, tani, dan pelajar akan mengambil jalan perjuangan karena tidak ada lagi alternatif.
Revolusi Indonesia – yang hanya bisa mengambil karakter sosialis – sekarang ada di agenda lagi. Sebuah revolusi di Indonesia akan menggoncang seluruh Asia dan memiliki pengaruh yang besar terhadap kaum pekerja dan tani di Malaysia, Filipin, India, Pakistan, Bangladesh dan Sri Lanka. Pembentukan federasi sosialis Indonesia, Malaysia, dan Filipin akan menyelesaikan masalah-masalah nasional secara adil. Potensial produksi yang besar dari negara-negara ini hanya bisa direalisasikan dengan sebuah ekonomi sosialis terencana, yang akan menciptakan kondisi untuk merubah hidup rakyat banyak.
Syaratnya adalah bagi rakyat pekerja untuk mengambil kekuasaan ke tangan mereka. Kaum pekerja dan tani Indonesia memiliki sejarah perjuangan yang luar biasa. Generasi kaum pekerja dan tani yang baru akan menemukan kembali tradisi-tradisi ini, mempersenjatai diri mereka dengan ide-ide Marxisme dan memimpin massa ke kemenangan akhir. Mereka akan membalas dendam martir-martir mereka yang terbunuh, menggulingkan penindas mereka, dan membangun kembali masyarakat ini secara sosialis.
London, 17 Desember 2008