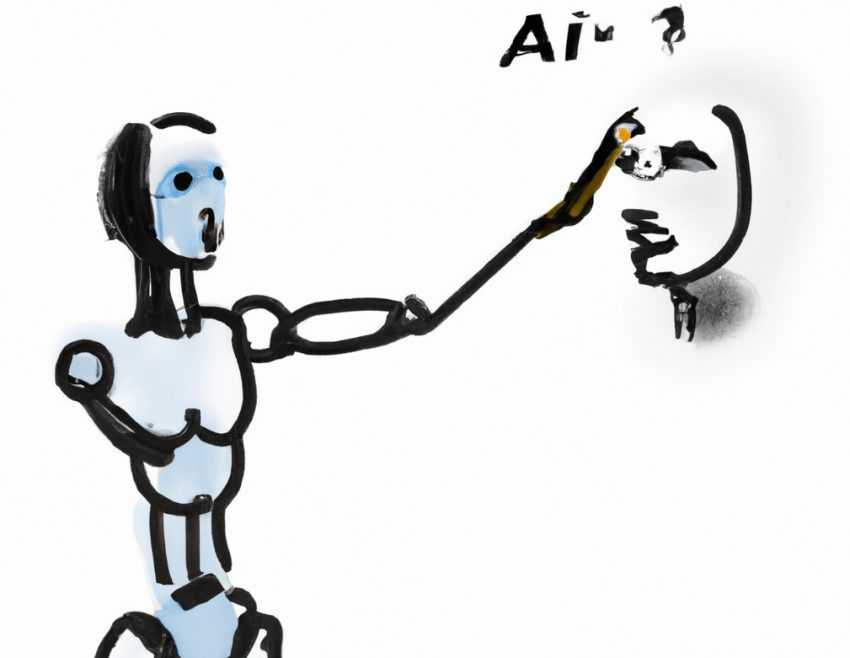Belakangan ini, terdapat sebuah tren baru dalam dunia seni yang menciptakan kontroversi hebat, yaitu penggunaan AI atau Artificial Intelligence (kecerdasan buatan) dalam seni yang juga disebut sebagai seni AI. Dengan cepat seni AI menjadi kontroversi akibat kemampuannya dalam menggunakan gambar dan desain buatan manusia sebagai referensi. Selain itu, kemampuan AI untuk menciptakan karya seni secara instan juga mengurangi kebutuhan akan seniman dan buruh kreatif, sehingga mengancam penghasilan mereka. Kontroversi ini mengekspos kontradiksi teknologi dalam kapitalisme yang, alih-alih mempermudah hidup buruh dan seniman, justru mempersulit hidup mereka.
Seni AI dan Kontroversinya
Seni AI dibuat dengan teknologi pembuatan gambar dengan kecerdasan buatan yang diterapkan pada aplikasi seperti DALL-E, Stable Diffusion, dan Midjourney yang muncul pada tahun 2022. Aplikasi tersebut mampu menciptakan gambar, lukisan, dan desain visual dengan hanya menggunakan kata tertentu hampir secara instan. Selain itu, banyaknya aplikasi seni AI yang berbasis website menjadikan seni AI dapat dibuat kapan pun, di mana pun, dan dengan gawai apa pun.
Teknologi yang digunakan dalam aplikasi tersebut berdasar algoritma pemrograman machine learning yang membuat sebuah aplikasi berkembang dengan sendirinya. Teknologi ini telah digunakan dalam banyak kasus sebelumnya, misalnya algoritma media sosial yang mampu memberikan rekomendasi konten berdasar perilaku pengguna. Dengan aplikasi seni AI, aplikasi pembuat gambar mengambil gambar, lukisan, dan desain visual di internet dan mempelajari elemen yang ada pada objek visual tersebut untuk menyesuaikan kata dari pengguna dan membuat gambar.
Dengan cepat kemunculan seni AI menimbulkan keresahan di antara seniman dan buruh kreatif. Beberapa poin keresahan di antaranya adalah ketidakmampuan bagi mereka untuk mengalahkan peningkatan produktivitas dari AI art. Selain itu, muncul ketakutan dari seniman akan masalah hak cipta akibat karya mereka digunakan dalam algoritma AI art tanpa adanya kompensasi dan atribusi yang sesuai. Dengan adanya teknologi AI, setiap orang akan dapat dengan mudah memplagiat gaya dari seorang buruh kreatif.
Selain itu penggunaan AI art yang kontroversial seperti menggunakan AI art dalam kontes seni dan penggunaan teknologi AI yang sembrono dalam pembuatan video game menjadikan masyarakat umum mulai bersimpati terhadap keresahan dalam penggunaan AI dalam seni. Keresahan yang telah menumpuk dari buruh kreatif dan masyarakat yang bersimpati berubah menjadi aksi protes yang terorganisir. Pada Desember 2022, seniman dan buruh kreatif yang menggunakan media berbagi karya ArtStation memprotes munculnya AI art dalam situs tersebut dengan mengunggah logo anti-AI secara bersamaan. Aksi ini begitu besar hingga logo anti-AI memenuhi halaman utama ArtStation.
Aksi protes pada ArtStation memperkuat sentimen anti AI hingga pada titik paranoia. Dalam situs Reddit, sebuah media sosial berbasis forum terbesar dan internasional, Ben Moran, seorang seniman digital terkena ban dari r/Art, komunitas seni terbesar di Reddit akibat tuduhan bahwa karya yang dibuat oleh Moran sendiri adalah karya yang dibuat oleh AI. Selain itu, masyarakat dengan cepat menghina sebuah karya apapun yang menggunakan AI. Karya animasi pendek “The Dog & The Boy” yang dirilis oleh Netflix Jepang segera dihina di Twitter akibat mengaku menggunakan AI dan menghindari membayar tenaga kerja manusia, meskipun penggunaan tersebut diawasi oleh manusia.
Kontroversi AI art menunjukkan adanya kontradiksi dalam kapitalisme. Penggunaan AI dalam karya seni memang jauh dari sempurna, dengan jurnalis dan seniman berkali-kali telah mengekspos fakta ini sebagai perlawanan terhadap AI art. Namun di sisi lain, fakta bahwa penggunaan AI dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam industri kreatif, terutama bagi proyek besar, tidak dapat dihindari. Tetapi, alih-alih peningkatan produktivitas ini disambut dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia secara umum, justru usaha ini disambut dengan negatif, skeptis, dan bahkan memunculkan paranoia. Lantas, kenapa hal ini bisa terjadi?
Konteks Sejarah Gerakan Anti Seni AI
Jika kita melihat kembali dalam sejarah, peristiwa seperti ini bukan yang pertama kali terjadi. Pada awal abad ke-19, terdapat Luddites, organisasi radikal rahasia yang dibentuk oleh para pengrajin di Inggris yang melakukan sabotase dengan merusak mesin tekstil. Sabotase dilakukan sebagai bentuk ketakutan bahwa kemampuan mereka akan menjadi sia-sia dengan munculnya revolusi industri yang menghasilkan mesin yang mampu memproduksi komoditas secara massal. Dengan demikian, dua abad yang lalu, kita dapat temui gerakan yang serupa dengan gerakan anti seni AI.
Secara umum, persamaan kondisi material kehidupan anggota Luddites dapat dengan mudah ditemukan dalam kondisi hidup seniman dan buruh kreatif. Meski demikian, teknologi modern membawa kompleksitas tersendiri pada situasi saat ini dan seniman dan buruh kreatif jelas bukan kelompok yang homogen. Beberapa seniman besar berdiri sendiri sebagai borjuis kecil. Mereka memiliki relasi dengan broker, pemilik galeri, atau borjuis-borjuis besar yang siap membeli komoditas yang mereka buat. Menghadapi perkembangan teknologi, mereka dapat beradaptasi dengan mudah.
Di bawah segelintir seniman besar tersebut, terdapat mayoritas besar seniman kecil yang termakan arus industrialisasi. Mereka mau tidak mau harus mengabdi kepada industri, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Sebagian bekerja melalui metode freelance, tidak ubahnya buruh borongan. Mereka menjual tenaga mereka secara online, lewat perjanjian-perjanjian tertentu.
Sebagian lain sepenuhnya menjual tenaga mereka kepada kelas borjuasi, dan terikat erat dalam relasi kerja tradisional kapitalisme. Mereka telah melalui tahapan proletarisasi. Pada awalnya, bekerja dengan perusahaan kreatif ini menjadi impian bagi pelajar seni atau seniman amatir. Posisi tersebut dianggap sebagai bukti kompetensi dan menjadi titik aman karena reputasi yang diraih mampu digunakan untuk berganti pekerjaan di masa depan.
Namun, ilusi surga perusahaan kreatif dengan cepat runtuh. Ekspose jurnalis mengenai kejamnya perlakuan terhadap buruh kreatif dalam perusahaan kreatif menunjukkan bahwa meski mereka adalah buruh terampil, nasib mereka tidak jauh seperti buruh pabrik. Banyak pekerja visual effects (vfx) harus bekerja lembur tanpa bayaran tambahan. Sam, seorang pekerja vfx yang telah mengerjakan enam film Marvel, menceritakan pengalamannya: “Saya tidak memiliki satu hari istirahat pun selama lima minggu. Dan ini bukan 8 jam kerja. Ini 10 jam kerja setiap harinya.” Eksploitasi buruh kreatif ini terjadi akibat berbagai studio produksi berusaha memotong ongkos produksi sebanyak mungkin demi meraih kontrak dengan Marvel atau studio besar lainnya
Studio animasi Jepang Madhouse mempekerjakan karyawan mereka dalam 400 jam sebulan dan 37 hari bekerja terus menerus tanpa libur. Bahkan terdapat seorang karyawan Madhouse yang bunuh diri akibat bekerja selama 600 jam dalam sebulan. Shingo Adachi, animator dan desainer karakter seri anime populer Sword Art Online mengatakan dengan sinis bahwa “tidak ada pekerjaan impian”. Meskipun seseorang dapat bekerja dalam karya hit, kini reputasi itu bukan jaminan. Karyawan Rockstar Games, perusahaan video game raksasa bekerja lembur hingga 100 jam per minggu, hingga salah satu karyawan harus cuti sakit selama 6 bulan. Karyawan perusahaan video game raksasa Activision Blizzard juga mengalami pelecehan seksual hingga menderita trauma psikologis.
Situasi kerja yang mengerikan ini mendorong semakin banyak pekerja seni dan kreatif untuk berorganisasi dan membentuk serikat buruh. Bila sebelumnya banyak pekerja kreatif yang takut menyuarakan tuntutan mereka, kini mereka sudah mulai menolak upah murah dan kerja lembur tak-berbayar. Ada perubahan kesadaran di antara lapisan pekerja seni dan kreatif, yang kini melihat diri mereka sama tidaklah berbeda dengan buruh umumnya. Di masa lalu, pekerja kreatif melihat diri mereka sebagai pekerja yang unik: pekerja “mental” kelas-menengah yang berbeda dengan pekerja “fisik” kerah-biru. Tetapi ilusi ini dengan cepat hancur. Pada dasarnya, siapa saja yang menjual daya kerja mereka (labour power) kepada kapitalis, mereka adalah buruh atau proletariat: entah mereka menggunakan tenaga fisik atau mental, entah mereka buruh pabrik, sopir, guru, staf kantor, penjaga toko, jurnalis, graphic designer, dsb.
Gelombang pembentukan serikat di antara pekerja seni ini mulai membuat kapitalis cemas akan profit mereka. Untuk menekan ongkos produksi, kapitalis memperkenalkan mesin atau teknologi baru ke dalam produksinya. Inilah yang kini terjadi dalam sektor industri seni, dengan perkembangan AI art. Membuat karya seni hanya dengan kata-kata jelas mengurangi kebutuhan akan jasa seniman. Jika sebelumnya memerlukan uang dan waktu untuk membuat potret karakter favorit untuk media sosial, kini seseorang yang sama sekali tidak tahu seni dapat membuatnya dalam waktu sekejap. Meskipun kualitasnya tidak seunik karya manusia, sebagian besar pasar tidak terlalu memedulikan kualitas. Selama kapitalis bisa membuat profit, mereka tidak peduli mengenai kualitas seni.
Reaksi gerakan anti AI art jelas adalah reaksi yang normal. Para pekerja seni dengan benar melihat bahwa teknologi baru ini merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup mereka. Para pekerja menolak teknologi baru bukan karena mereka “reaksioner”, atau anti kemajuan. Justru kapitalisme-lah yang reaksioner karena setiap teknologi baru hanya menciptakan pengangguran dan upah murah, dalam kata lain lebih banyak kesengsaraan di sisi pekerja.
Pada akhirnya, reaksi ini sebenarnya adalah penentangan terhadap kapitalisme secara tidak sadar, yang mengalienasi buruh dan seniman dari hasil kreasinya dan merenggut jiwa dari hasil karya mereka. Brutalitas industri meradikalisasi mereka seperti revolusi industri meradikalisasi kaum Luddite. Namun tanpa gagasan yang tepat, reaksi ini hanya akan berujung pada pesimisme dan perilaku reaksioner. Jelas sudah bahwa pada akhirnya sistem kapitalisme dan kepemilikan alat produksi secara pribadi adalah penyebab dari penderitaan pekerja seni di seluruh dunia pada saat ini, dengan dan tanpa adanya AI art.
Jalan buntu borjuasi dan gerakan
Pemerintah borjuasi masih dalam masa kebingungan menghadapi masalah ini. Kebingungan ini sesungguhnya tidaklah berbeda dengan problem otomatisasi industri yang dihadapi kelas penguasa kapitalis umumnya. Di satu sisi, otomatisasi industri dapat memangkas ongkos produksi, karena ini menekan upah buruh dan jumlah buruh yang perlu dipekerjakan. Dengan demikian ini dapat memberi laba besar bagi perusahaan. Tetapi di sisi lain, otomatisasi dapat menciptakan pengangguran massal yang kronik. Kapitalis dan kelas penguasa tentunya tidak peduli dengan buruh yang menganggur selama profit mereka terjaga, tetapi mereka khawatir akan problem sosio-politik dan ekonomi yang bisa mengusik tatanan mereka. Pengangguran massal menciptakan keresahan dalam masyarakat, yang bisa berujung pada gejolak sosial. Lebih dari itu, secara ekonomi, bila semakin banyak buruh menganggur, maka siapa yang akan membeli komoditas berlimpah yang dihasilkan oleh robot-robot itu? Inilah mengapa beberapa waktu yang lalu sejumlah pengamat dan ekonom menganjurkan solusi utopis Universal Basic Income (Jaminan Pendapatan Dasar) sebagai jawaban atas problem otomatisasi produksi. Kami sudah menjawab mimpi utopis UBI dalam artikel “Mimpi Universal Basic Income yang tak Kunjung Tiba”.
Debat mengenai AI art sebagian besar berkutat di masalah hak cipta. Sejumlah artis mengeluh bagaimana program-program AI art ini telah menggunakan karya-karya seni orang lain tanpa izin. Ini dianggap seperti plagiat, sebuah tindakan yang dianggap tidak etis. Sehingga salah satu tuntutan yang diajukan oleh sekelompok seniman (seperti Concept Art Association) adalah meregulasi hukum Intellectual Property dan privasi data, sehingga dapat melindungi hak cipta seniman. Intinya, bila tool AI art ini bisa menghasilkan uang, maka para seniman ini ingin dikompensasi bila karya seni mereka digunakan oleh AI ini sebagai bagian dari machine learning. Tetapi ini adalah tuntutan yang utopis. Pengetatan hak karya cipta tidak akan menghentikan perkembangan AI dan algoritma machine learning, serta monopoli AI oleh segelintir korporasi besar. Sebaliknya, dengan cara pandang seperti itu, korporasi-korporasi di balik AI Art justru telah melontarkan konter-argumen bahwa yang mereka lakukan adalah “demokratisasi seni”. Tentu saja ini adalah omong kosong. Bagi kapitalis, “demokratisasi” adalah “komodifikasi” demi profit.
Selain itu, argumen pengetatan hak karya cipta (IP) justru akan memperkuat monopoli perusahaan-perusahaan media terhadap karya seni. Merekalah yang menguasai tuas-tuas ekonomi utama, dan dengan demikian memiliki kontrol terhadap IP yang sangat penting bagi monopoli mereka. Seni seharusnya dijadikan milik publik, seperti halnya semua pengetahuan. Tetapi di bawah kapitalisme, banyak pekerja seni yang mata pencahariannya sangat tergantung pada karya seni sebagai komoditas yang mereka perjual belikan. Ini membuat seni secara fetis terhubungkan dengan kepemilikan pribadi. Seni menjadi terdistorsi.
Kita dapat memaklumi bagaimana para pekerja seni ingin melindungi hak cipta karya mereka, karena di bawah kapitalisme mereka terpaksa beroperasi dengan logika pasar dan komoditas. Tanpa AI saja, nilai karya mereka terus ditekan oleh kapitalis, dan banyak yang bahkan terpaksa bekerja gratis dengan alasan mencari pengalaman dan eksposure. Kini dengan berkembangnya AI, ini adalah serangan lebih lanjut, dimana mereka dapat dengan mudah digantikan.
Solusi Revolusioner
Perkembangan AI tidak bisa dilawan dengan menolaknya semata, tetapi dengan perjuangan massa secara kolektif. Ketika buruh umumnya juga diancam keberlangsungan hidupnya oleh dikenalkannya mesin-mesin modern ke dalam pabrik, mereka awalnya melawanya dengan menghancurkan mesin tersebut, seperti yang dilakukan kaum Luddite. Tetapi ini tidak menghentikan berkembangnya mesin. Kaum Ludditte ini lalu memahami, bahwa yang mereka perlukan adalah membangun serikat buruh yang berjuang dengan aksi massa guna melawan PHK dan upah murah. Musuh mereka bukanlah mesin, tetapi pemilik mesin tersebut, kapitalis yang memeras profit.
Maka dari itu buruh kreatif dan seniman harus menyatukan sesama mereka di bawah organisasi serikat. Selain memperjuangkan jaminan kepastian kerja dan jaminan upah layak, serikat ini harus memiliki program radikal untuk melawan kapitalisme. Mereka harus berjuang untuk menasionalisasikan dan mengkolektivisasikan industri-industri kreatif, dalam negeri maupun multinasional, dan berjuang untuk menuntut pendanaan publik bagi seniman-seniman, agar seni kembali lagi jadi milik publik bukan milik kapitalis dan swasta. Mereka juga harus melebur dalam gerakan buruh yang lebih luas, memperkuat perjuangan kelas, dan menyatukan barisan bersama kelas buruh dalam industri lain.
Pada akhirnya, perjuangan harus ditujukan untuk menghabisi kapitalisme dan menggantinya dengan sosialisme. Dengan sosialisme, horor penindasan dan eksploitasi dari sistem kepemilikan pribadi akan berakhir. Monopoli teknologi dan fasilitas distribusi karya oleh borjuis seperti Disney dan Warner Bros akan menghilang. Teknologi AI pada akhirnya dapat menjadi kekuatan produksi yang progresif dengan kontrol yang demokratis bagi seniman dan buruh kreatif. Sesungguhnya, teknologi AI memiliki potensi besar, tetapi di bawah kapitalisme potensi ini didistorsi demi kepentingan profit. Tidak heran korporasi-korporasi besar menginvestasikan banyak uang untuk mengembangkan AI art, karena mereka mencium profit besar.
Dengan tuas produksi yang dimiliki oleh kelas buruh, termasuk di sini seni sebagai bagian penting dalam produksi manusia, seniman dan buruh kreatif akhirnya dapat berkarya dengan bebas dan memiliki waktu luang untuk berkontemplasi dan bereksplorasi. Mereka tidak lagi jadi budak kapital, di mana seni mereka jadi komoditas untuk diperjual belikan.
Jika kebebasan ini dianggap sebagai utopia semata, era awal dari Uni Soviet jelaslah memajukan budaya dan seni dalam masyarakatnya. Gerakan konstruktivisme yang berkembang setelah Revolusi Oktober menjadi dasar bagi gerakan seni modern seperti sekolah Bauhaus dan brutalisme. Seniman seperti Vladimir Mayakovsky dan Alexander Rodchenko terus menjadi inspirasi bagi seniman internasional. Direktur film Lev Kuleshov dapat bereksplorasi dengan filmografi yang pada akhirnya menghasilkan trik terkenal “Kuleshov effect”. Selain itu, era awal Uni Soviet membuka akses seni yang berkualitas bagi rakyat jelata. Teater dan bioskop yang sebelumnya tertutup bagi mereka pada akhirnya dibebaskan.
Kapitalisme sudah begitu membusuk hingga turut meracuni seni dan budaya. Selain memperkosa kesenian dengan sengaja mendistribusikan karya buruk demi profit, kapitalisme juga memecah belah seniman dan buruh kreatif, membawa mereka pada ketakutan dan kompetisi non-produktif yang tiada henti. Namun, kapitalisme tidak bisa berakhir tanpa adanya perlawanan sadar dan terorganisir dari buruh, petani, buruh kreatif, seniman, intelektual, dan kaum tertindas lainnya. Melalui perlawanan yang terorganisir di bawah teori dan perspektif revolusioner akan tercipta masyarakat yang lebih demokratis dan sejahtera, dan seni yang bebas dari pelacuran, pemerkosaan dan eksploitasi.